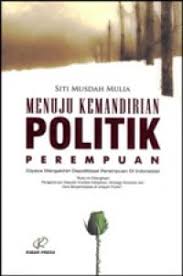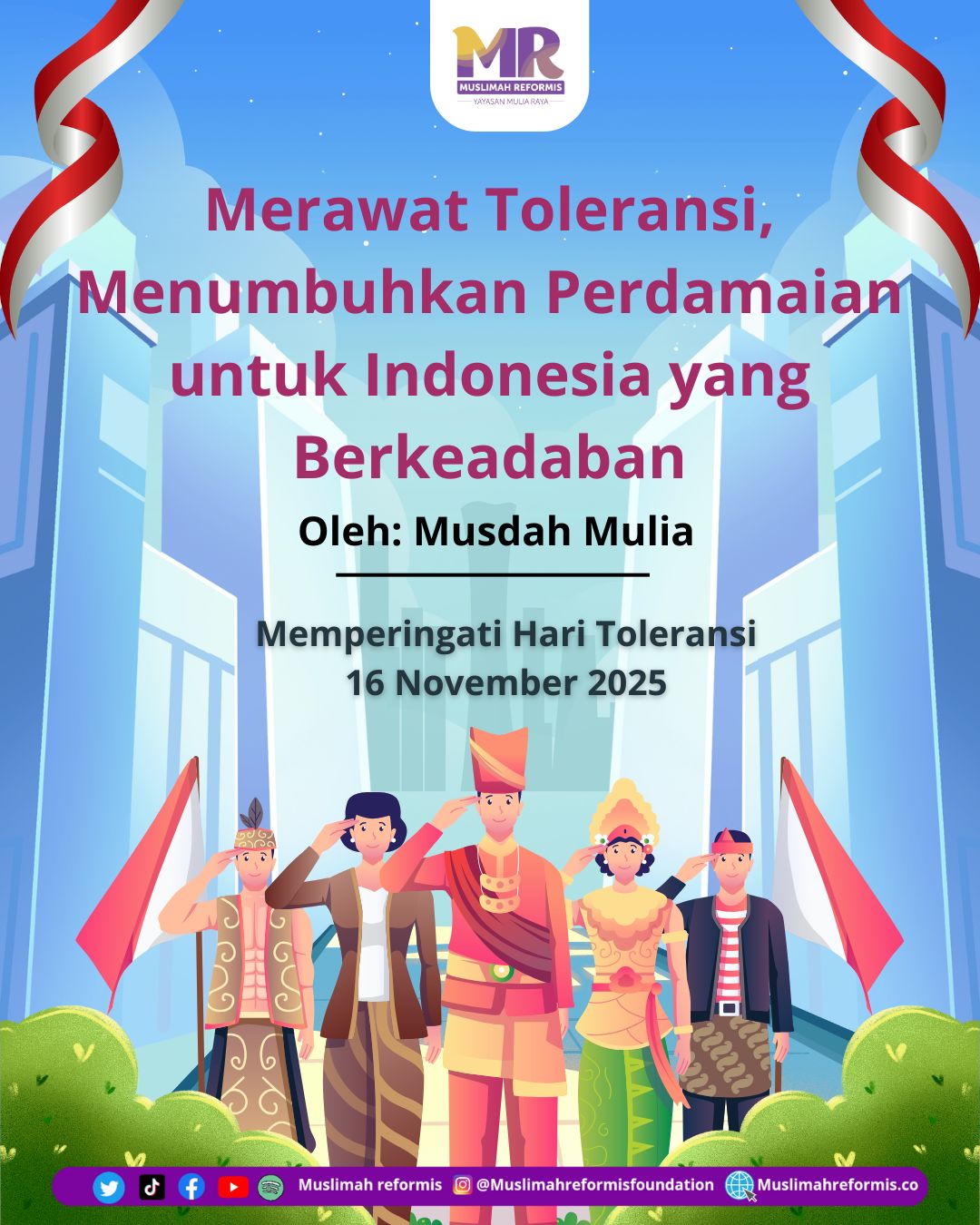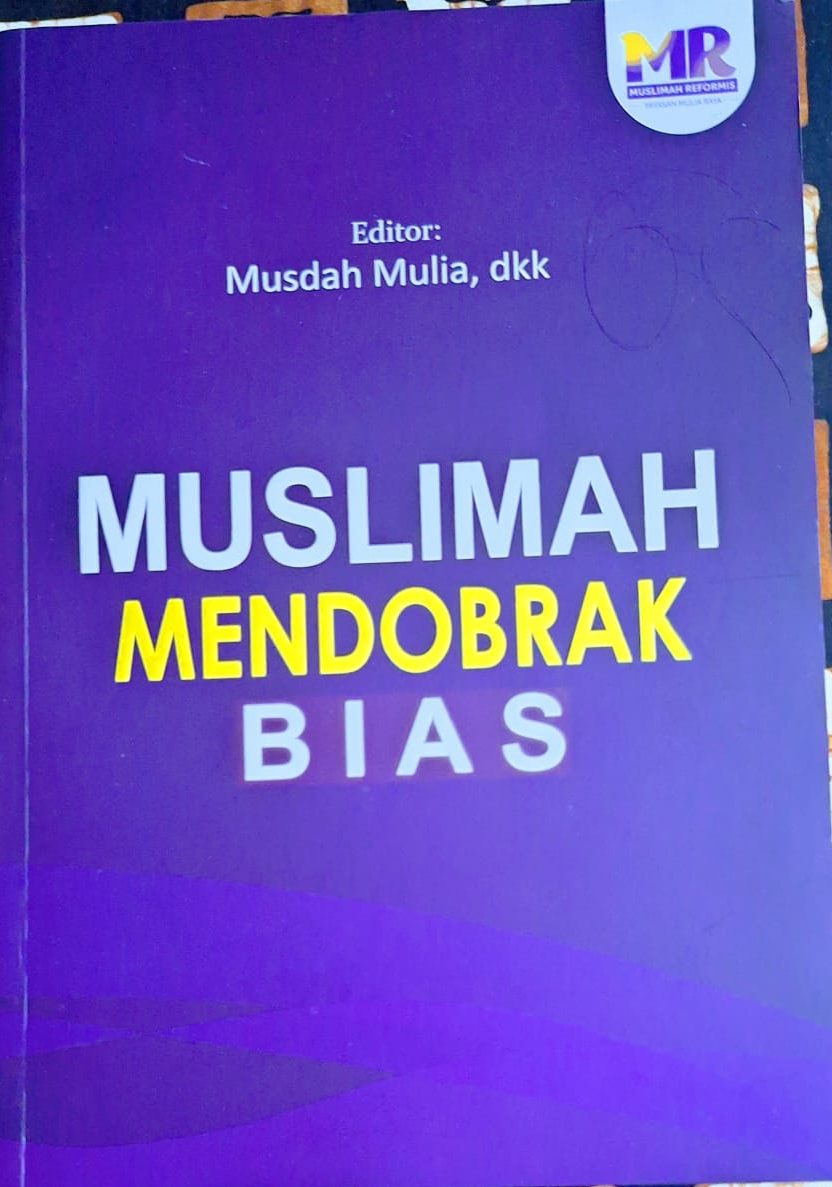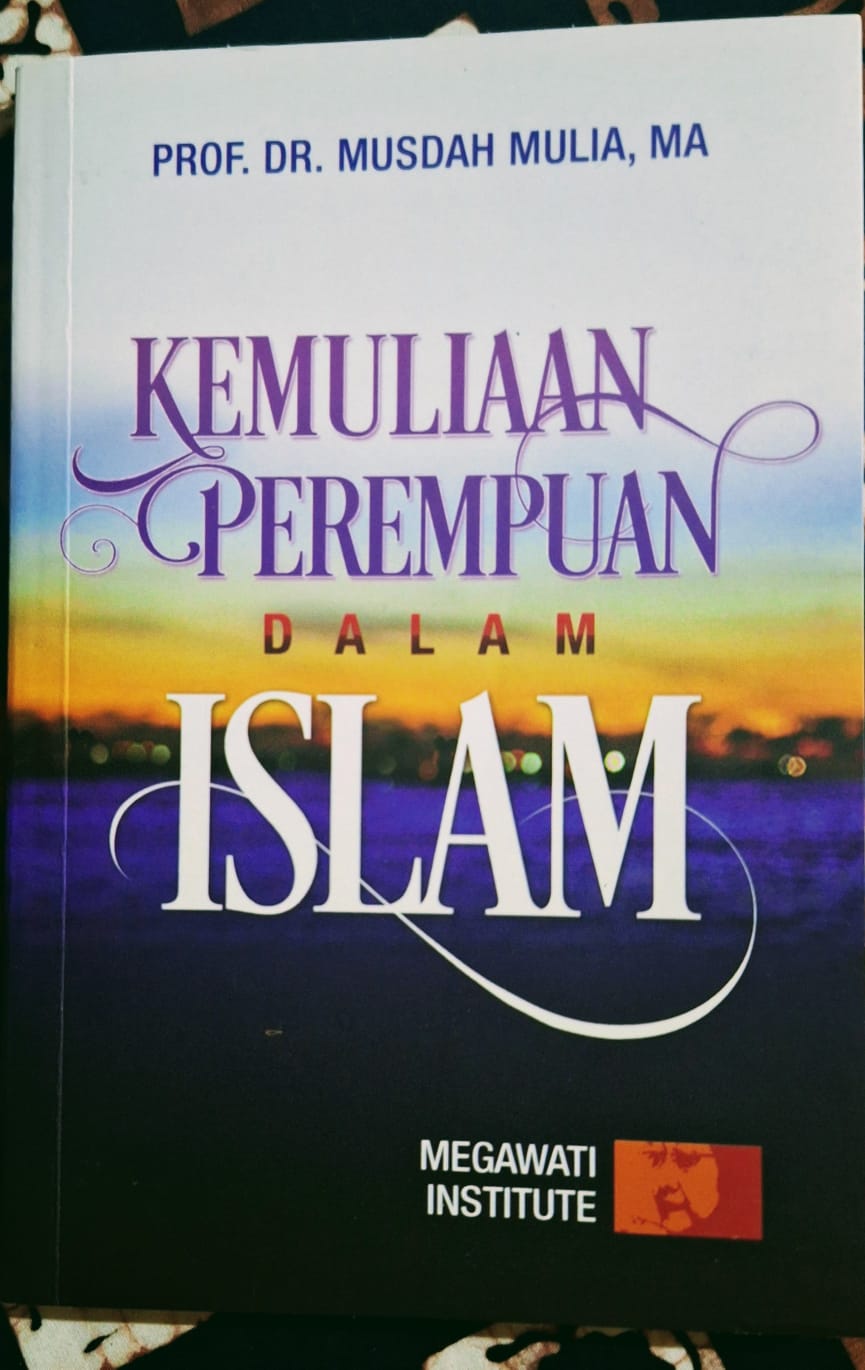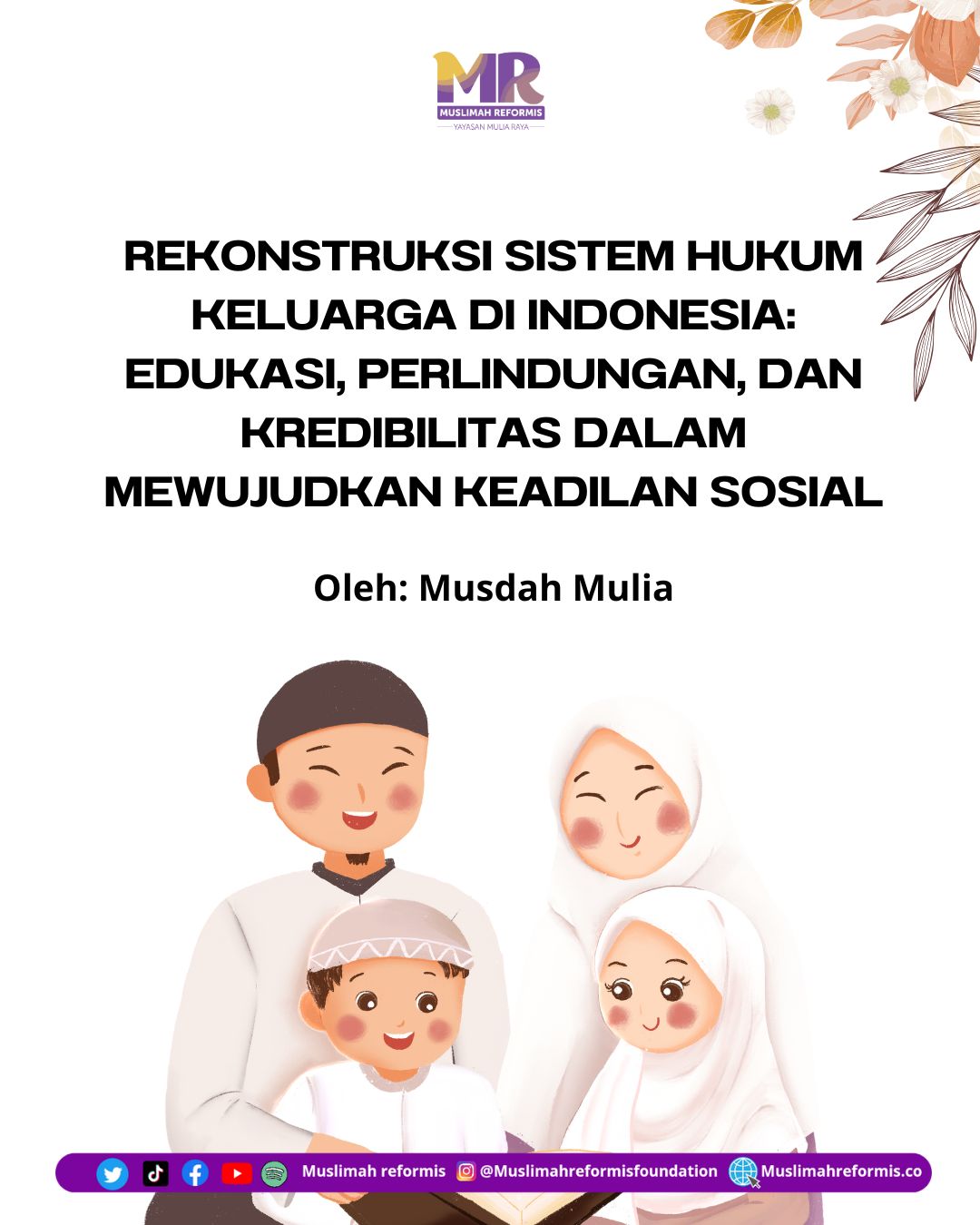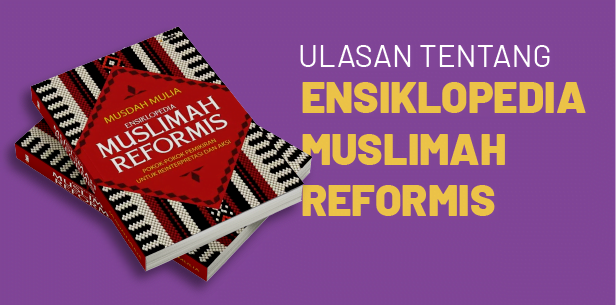Oleh: Musdah Mulia
Pendahuluan
Hari ini kita membicarakan sesuatu yang sangat fundamental bagi keberlangsungan bangsa, yaitu rekonstruksi sistem hukum keluarga di Indonesia. Mengapa hal ini penting? Karena keluarga merupakan pilar utama peradaban: dari keluarga lahir generasi penerus, pemimpin masa depan, sekaligus cermin kualitas masyarakat. Maka, jika hukum keluarga rapuh, maka rapuh pula sendi-sendi keadilan sosial dalam masyarakat.
Rekonstruksi sistem hukum keluarga bukan sekadar agenda hukum, melainkan agenda peradaban. Ia menuntut edukasi yang mencerahkan, perlindungan yang menyejahterakan, dan kredibilitas yang menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan itulah, kita dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Jika kita melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari perspektif keadilan gender dan perlindungan anak, memang ada beberapa masalah mendasar yang sudah lama dikritik para akademisi, aktivis, dan praktisi hukum. Masalah utama UU Perkawinan 1974 terletak pada ideologi patriarki yang masih kuat dan minimnya perlindungan hak anak. Walaupun sudah ada perbaikan melalui amandemen (UU No. 16 Tahun 2019) dan putusan-putusan MK, rekonstruksi menyeluruh masih sangat dibutuhkan agar hukum keluarga benar-benar sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, keadilan substantif, dan perlindungan anak.
UU Perkawinan 1974 bermasalah karena masih sarat bias patriarki (menempatkan perempuan dalam posisi subordinat) dan kurang melindungi hak anak (terutama dalam isu usia perkawinan, pencatatan nikah, dan status anak luar nikah). CLD KHI hadir sebagai respon untuk merekonstruksi hukum keluarga agar selaras dengan prinsip HAM, keadilan gender, dan perlindungan anak.
Pentingnya Rekonstruksi Hukum Keluarga
Hukum keluarga di Indonesia, baik yang berbasis agama, adat, maupun hukum positif, sering menghadapi persoalan serius sebagai berikut:
- Ketimpangan gender, seperti praktik diskriminasi dalam perkawinan, perceraian, maupun waris.
- Kekerasan dalam rumah tangga, yang meskipun sudah ada UU PKDRT, masih sering tersembunyi dalam budaya “domestikasi”.
- Praktik pernikahan anak, yang meski usia minimum perkawinan telah direvisi, tetap tinggi di beberapa daerah.
- Lemahnya perlindungan anak, baik dari aspek hak sipil, pendidikan, maupun kesehatan.
Rekonstruksi hukum keluarga berarti membangun ulang sistem, norma, dan praktik agar lebih sesuai dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip Maqashid Syari’ah’
Pilar Rekonstruksi: Edukasi, Perlindungan, dan Kredibilitas
1. Edukasi
Tidak ada hukum yang kuat tanpa kesadaran masyarakat. Edukasi hukum keluarga harus mencakup tiga hal berikut. Pertama, memberikan literasi hukum kepada masyarakat, sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya. Kedua, memasukkan pendidikan keluarga dan relasi gender dalam kurikulum, agar generasi muda tidak terjebak dalam praktik diskriminatif. Ketiga, menyediakan pendampingan hukum berbasis komunitas: paralegal, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.
2. Perlindungan
Hukum keluarga harus memprioritaskan perlindungan kelompok rentan: perempuan, anak, lansia, dan disabilitas. Prinsip perlindungan ini mencakup: Pertama, Perlindungan dari kekerasan domestik: hukum harus tegas, cepat, dan berperspektif korban. Kedua, perlindungan dari perkawinan anak dengan memperkuat regulasi dan menindak praktik dispensasi yang longgar. Ketiga, perlindungan hak ekonomi dalam perkawinan dan perceraian, agar perempuan dan anak tidak jatuh dalam kemiskinan.
3.Kredibilitas
Hukum keluarga harus kredibel, artinya dipercaya masyarakat. Kredibilitas ini hanya lahir jika:
- Sistem hukum konsisten menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
- Aparat hukum bebas dari praktik korupsi, kolusi, atau diskriminasi.
- Putusan pengadilan keluarga benar-benar berorientasi pada maslahah(kemaslahatan) dan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.
Hukum Keluarga dan Keadilan Sosial
Keadilan sosial bukan jargon kosong. Dalam konteks keluarga, ia berarti: Semua anggota keluarga memperoleh hak yang sama untuk hidup bermartabat. Negara menjamin keadilan distributif, misalnya dalam hak waris, harta bersama, dan nafkah. Sistem hukum mampu menjadi ruang transformasi sosial, bukan sekadar mempertahankan tradisi yang sudah tidak relevan dengan semangat keadilan zaman ini. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga bukan hanya urusan internal rumah tangga, melainkan strategi besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rekomendasi Strategis
Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum keluarga yang adil, perlu langkah konkret:
- Revisi regulasi hukum keluargaagar lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dan hak anak.
- Penguatan peran Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan lembaga adatsebagai mediator keadilan.
- Kolaborasi lintas agama dan budayauntuk menemukan titik temu hukum keluarga yang humanis dan inklusif.
- Penguatan riset akademikagar setiap kebijakan hukum keluarga berbasis pada data empiris, bukan sekadar dogma atau kompromi politik.
Berbagai problem Hukum Keluarga
- Masalah dari Perspektif Keadilan Gender
- Dominasi Laki-laki dalam Perkawinan: Pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Ini menegaskan relasi hierarkis, menempatkan perempuan pada posisi subordinat, seolah tidak punya ruang kesetaraan dalam kepemimpinan keluarga.
- Poligami yang Masih Dilegalkan : Pasal 3 ayat (2) membuka peluang poligami dengan syarat tertentu. Meskipun syaratnya ketat (izin pengadilan, persetujuan istri), dalam praktik banyak kasus perempuan tidak berdaya menolak poligami. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hakdan juga mencederai martabat perempuan.
- Perceraian yang Cenderung Memberatkan Perempuan: Walau perceraian harus di pengadilan, praktiknya banyak perempuan kesulitan menuntut hak ekonomi pasca-cerai (nafkah, harta bersama, hak asuh anak). Ada bias dalam implementasi: suami lebih mudah menjatuhkan talak, sementara istri menghadapi prosedur panjang untuk menggugat cerai.
- Masalah dari Perspektif Perlindungan Anak
- Usia Perkawinan yang Rendah: Semula, Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia minimal kawin: 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Ini membuka peluang besar praktik child marriage. Baru pada 2019 direvisi menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Namun, dispensasi kawin masih sering diberikan pengadilan, sehingga praktik perkawinan anak tetap tinggi.
- Lemahnya Jaminan Hak Anak: UU Perkawinan 1974 belum menekankan secara tegas prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Anak sering menjadi korban dalam sengketa perceraian: hak asuh tidak selalu mempertimbangkan psikologis anak, sementara nafkah anak kerap diabaikan oleh ayah pasca-cerai.
- Status Anak di Luar Nikah: Pasal 42–43 menyebutkan anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ini menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. Baru setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah diakui memiliki hubungan perdata juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (DNA).
- Dampak Sosialnya: Perempuanrentan menjadi korban diskriminasi hukum dan praktik patriarki yang dilegitimasi UU.Anak terjebak dalam lingkaran kerentanan: perkawinan usia dini, kurangnya perlindungan dalam perceraian, dan stigma terhadap anak luar nikah.
Perbandingan UU Perkawinan 1974, KHI 1991, dan CLD KHI
| Isu | UU Perkawinan 1974 | KHI 1991 | CLD KHI (2004) |
| Definisi Perkawinan | Akad mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah, bernilai ibadah | Sama dengan UUP, menekankan ibadah | Akad sosial (mitsaqan ghalidzan) atas dasar kerelaan & kesepakatan, bukan kewajiban ibadah
|
| Kepala Keluarga | Suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga (Pasal 31) | Sama, ditegaskan lagi (Pasal 79) | Suami-istri setara dalam hak, kewajiban, kepemimpinan keluarga
|
| Poligami | Diperbolehkan dengan syarat ketat (Pasal 3, 4, 5) | Dibolehkan sampai 4 istri (Pasal 55) | Dilarang, asas perkawinan adalah monogami (Pasal 3 CLD) |
| Usia Perkawinan | Laki-laki 19 thn, perempuan 16 thn (Pasal 7) | Sama (Pasal 15 KHI) | Minimal 19 thn bagi laki-laki & perempuan; kedewasaan penuh 21 thn
|
| Wali Nikah | Perempuan wajib ada wali | Wali rukun sah nikah (Pasal 19) | Wali hanya untuk perempuan <21 thn; dewasa bisa menikahkan diri
|
| Saksi Nikah | Minimal 2 saksi laki-laki Muslim | Saksi laki-laki Muslim, adil, baligh, tidak cacat (Pasal 25) | Saksi bisa laki-laki atau perempuan; penyandang disabilitas tidak didiskriminasi |
| Pencatatan Nikah | Wajib dicatat, tapi bukan syarat sah | Sama, sekadar administrasi (Pasal 5–7) | |
| Nusyuz | Konsep bias: istri durhaka pada suami | Sama, hanya istri dianggap nusyuz (Pasal 84) | Nusyuz bisa dilakukan suami atau istri; bisa dilaporkan sebagai tindak pidana jika berupa KDRT |
| Hak & Kewajiban | Suami pemimpin, istri taat & urus rumah tangga | Sama, suami pembimbing, istri wajib bakti (Pasal 80–83) | Hak & kewajiban setara: saling mendukung, mendidik anak, boleh memilih peran (Pasal 49–51 CLD) |
| Nafkah | Suami wajib menanggung nafkah | Sama (Pasal 80 ayat 4,6) | Nafkah tanggung jawab bersama; tugas reproduksi perempuan dihargai setara atau lebih tinggi |
| Perkawinan Beda Agama | Dilarang (Pasal 2 UUP + PP 9/1975) | Dilarang (Pasal 40, 44 KHI) | Diperbolehkan, dengan prinsip saling menghargai; anak boleh pilih agama |
| Status Anak Luar Nikah | Hanya hubungan dengan ibu (Pasal 42–43 | Dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Negara harus membantu memberikan kepastian identitas anak |
Rekonstruksi Hukum Keluarga:
Perbandingan UU Perkawinan 1974, KHI 1991, dan CLD KHI 2004
Pembahasan tentang hukum keluarga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tiga instrumen penting: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, dan Counter Legal Draft KHI (CLD KHI) tahun 2004. Ketiganya merupakan representasi dari tiga tahap sejarah hukum keluarga di Indonesia: legislasi nasional, kodifikasi hukum Islam, dan inisiatif reformasi berbasis prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.
1. Definisi Perkawinan
UUP 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah” serta menekankannya sebagai ibadah. Rumusan ini diadopsi kembali oleh KHI 1991. Namun CLD KHI menawarkan perubahan mendasar: perkawinan adalah akad sosial yang serius (mitsaqan ghalidzan) antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan kesepakatan. Pergeseran dari “ibadah wajib” ke “akad sosial sukarela” penting untuk menghapus pemaksaan perkawinan dan trafficking berkedok nikah
2. Relasi Suami-Istri dan Kepemimpinan Keluarga
UUP 1974 (Pasal 31) dan KHI 1991 (Pasal 79–83) secara tegas menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib taat. Hal ini melanggengkan ideologi patriarki. CLD KHI mengoreksi dengan menegaskan bahwa suami-istri setara dalam hak, kewajiban, dan peran (Pasal 49–51). Mereka sama-sama pemimpin keluarga, saling mendukung, mengasuh anak, dan berhak menentukan peran sesuai kesepakatan
3. Poligami
UUP 1974 dan KHI 1991 tetap membuka ruang poligami dengan syarat tertentu (izin pengadilan, persetujuan istri, dan keadilan suami). Namun, CLD KHI dengan tegas menutup pintu poligami dengan menjadikan monogami sebagai asas perkawinan. Poligami dinilai tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak
4. Usia Perkawinan
UUP 1974 menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. KHI 1991 mengulang ketentuan ini (Pasal 15). CLD KHI memajukan agenda perlindungan anak dengan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta mengakui kematangan penuh pada usia 21 tahun. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU Perlindungan Anak
5. Wali dan Saksi
KHI 1991 masih mengikuti pandangan fikih klasik bahwa perempuan wajib menikah dengan wali laki-laki, dan saksi hanya boleh laki-laki Muslim, adil, dan tidak cacat (Pasal 19, 25). CLD KHI memperkenalkan paradigma baru: perempuan dewasa (21 tahun) berhak menikahkan diri sendiri, sementara wali hanya diperlukan bagi perempuan di bawah 21 tahun. Selain itu, saksi bisa laki-laki atau perempuan, dan kelompok disabilitas tidak boleh didiskriminasi
6. Pencatatan Nikah
UUP 1974 dan KHI 1991 mewajibkan pencatatan perkawinan hanya untuk kepentingan administrasi, bukan syarat sah. Akibatnya, perkawinan siri tetap dianggap sah, meski merugikan perempuan dan anak. CLD KHI mempertegas: pencatatan adalah syarat sah perkawinan, dengan analogi dari perintah pencatatan transaksi hutang dalam Al-Baqarah 2:282
7. Nusyuz
Dalam UUP 1974 maupun KHI 1991, konsep nusyuz dilekatkan pada istri yang dianggap durhaka pada suami (Pasal 84 KHI). CLD KHI menolak standar ganda ini, dengan merumuskan nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Lebih jauh, jika nusyuz berwujud kekerasan, maka dapat diproses sebagai tindak pidana
8. Nafkah
UUP 1974 dan KHI 1991 menegaskan nafkah sebagai kewajiban suami semata (Pasal 80). CLD KHI mengubah paradigma ini: nafkah adalah tanggung jawab bersama, namun tugas reproduksi perempuan (hamil, melahirkan, menyusui) dihargai sebagai kontribusi yang lebih tinggi dan berhak mendapatkan imbalan
9. Perkawinan Beda Agama
UUP 1974 secara implisit melarang, dan KHI 1991 secara eksplisit menegaskan larangan bagi perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim (Pasal 40, 44). CLD KHI justru membuka peluang perkawinan beda agama dengan syarat penghormatan pada kebebasan beragama dan penjelasan dari negara kepada calon mempelai. Anak dari perkawinan beda agama berhak memilih agama secara bebas.
10. Status Anak Luar Nikah
UUP 1974 dan KHI 1991 hanya mengakui hubungan hukum anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 42 UUP, Pasal 100 KHI). CLD KHI menawarkan terobosan: anak hasil perkawinan hamil atau luar nikah tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan (misalnya melalui tes DNA).
Perbandingan ini menunjukkan bahwa UUP 1974 dan KHI 1991 masih sarat dengan bias patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan serta lemah dalam melindungi hak-hak anak. CLD KHI 2004 hadir sebagai upaya rekonstruksi hukum keluarga yang berbasis pada prinsip keadilan gender, kesetaraan, perlindungan anak, dan penghormatan HAM, sekaligus tetap berakar pada semangat maqashid al-syari‘ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, CLD KHI bukan sekadar alternatif, melainkan peta jalan menuju hukum keluarga Indonesia yang lebih adil, egaliter, dan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Perbandingan Indonesia dengan Tunisia, Maroko, Turki, dan Mesir
Hukum keluarga di dunia Islam mengalami dinamika yang berbeda-beda. Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 1991 (KHI) masih menyisakan sejumlah problem serius: ketidaksetaraan gender, peluang poligami, perkawinan anak, serta lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Gagasan Counter Legal Draft KHI (2004) sebenarnya sudah mencoba melakukan reformasi progresif, namun belum berhasil masuk ke ranah legislasi formal. Sebagai perbandingan, sejumlah negara Islam lain telah melangkah lebih jauh: Tunisia, Maroko, Turki, dan Mesir. Keempatnya menghadirkan model berbeda yang dapat menjadi cermin bagi rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia.
1. Poligami dan Asas Monogami
- Indonesia (UUP/KHI): Poligami dibolehkan dengan syarat ketat (izin pengadilan, persetujuan istri). Dalam praktiknya, perempuan sering tidak berdaya menolak. CLD KHI mengusulkan larangan poligami.
- Tunisia: Sejak Code of Personal Status1956, poligami dilarang secara mutlak dan dikenai sanksi pidana. Ini menjadikan Tunisia sebagai negara Muslim pertama yang menghapus poligami demi prinsip kesetaraan .
- Maroko: Moudawana 2004tidak menghapus poligami, tetapi memperketat: hanya dengan izin hakim dan persetujuan istri pertama; syaratnya hampir mustahil dipenuhi. Praktis, poligami sangat jarang terjadi .
- Turki: Sejak Civil Code1926, perkawinan sipil monogami wajib; poligami dilarang dan bisa dihukum .
- Mesir: Poligami masih diperbolehkan, namun pengadilan dapat menilai dampaknya terhadap istri. Reformasi terbatas, dan tekanan konservatif tetap kuat .
Analisis: Indonesia masih tertinggal dibanding Tunisia dan Turki. Model Maroko bisa jadi jalan tengah: poligami tidak langsung dihapus, tetapi dikontrol ketat hingga nyaris tidak mungkin.
2. Usia Perkawinan dan Perlindungan Anak
- Indonesia: UUP 1974 menetapkan 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki); direvisi pada 2019 menjadi 19 tahun untuk keduanya. Namun dispensasi kawin masih longgar.
- Tunisia: Menetapkan usia minimal perkawinan 18 tahun, tanpa diskriminasi gender, dan penegakan hukumnya relatif ketat .
- Maroko: Moudawana2004 juga menetapkan 18 tahun, namun hakim dapat memberi dispensasi. Meski masih ada perkawinan anak, jumlahnya menurun signifikan .
- Turki: Menetapkan usia perkawinan 18 tahun; 17 tahun dengan izin orang tua. Sistem sipil meminimalisasi perkawinan dini .
- Mesir: Undang-undang menetapkan 18 tahun, tetapi praktik perkawinan anak masih terjadi, terutama di daerah rural karena lemahnya implementasi .
Analisis: Indonesia masih menghadapi tantangan serupa Mesir (dispensasi longgar). Tunisia dan Turki lebih tegas dalam implementasi.
3. Pencatatan Perkawinan
- Indonesia: Pencatatan diwajibkan, tetapi bukan syarat sah; akibatnya, nikah siri masih marak. CLD KHI menawarkan pencatatan sebagai syarat sah.
- Tunisia & Maroko: Pencatatan merupakan syarat sah perkawinan. Perkawinan hanya sah jika dilakukan di hadapan pejabat negara .
- Turki: Perkawinan sipil adalah satu-satunya perkawinan yang sah. Nikah agama tidak punya kekuatan hukum .
- Mesir: Pencatatan diwajibkan, tetapi masih ada kontradiksi antara norma agama dan praktik sosial.
Analisis: Model Turki paling tegas, sedangkan Indonesia masih mengizinkan praktik nikah tanpa pencatatan.
4. Relasi Suami-Istri dan Hak Asasi Perempuan
- Indonesia: UUP 1974 menegaskan suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. KHI 1991 menegaskan kewajiban istri taat kepada suami. CLD KHI menawarkan kesetaraan penuh.
- Tunisia: Menetapkan kesetaraan penuh antara suami dan istri dalam hak dan kewajiban keluarga .
- Maroko: Moudawanamenegaskan konsep “kemitraan” suami-istri dalam rumah tangga: mereka berbagi tanggung jawab dan saling menghormati .
- Turki: Sejak 2001, Civil Code baru menegaskan kesetaraan suami-istri dalam kepemimpinan rumah tangga, pengelolaan harta, dan hak asuh .
- Mesir: Relasi masih bias gender; suami tetap diposisikan sebagai kepala keluarga, meskipun ada beberapa putusan pengadilan progresif.
Analisis: Indonesia berada di posisi serupa Mesir; Tunisia, Maroko, dan Turki lebih maju dalam menegakkan kesetaraan.
5. Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Indonesia: UU PKDRT (2004) sudah ada, tetapi implementasi sering terhambat budaya patriarki.
- Tunisia: UU 2017 tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dianggap salah satu paling progresif di dunia Arab .
- Maroko: Ada reformasi hukum pidana terkait kekerasan, meski kritik masih muncul terkait implementasi .
- Turki: Pernah meratifikasi Konvensi Istanbul, namun tahun 2021 menarik diri; perlindungan masih ada, tetapi melemah.
- Mesir: Perlindungan hukum terhadap KDRT masih lemah; banyak kasus tidak masuk ranah hukum pidana.
Analisis: Tunisia memberikan teladan kuat; Indonesia sudah punya dasar hukum, tetapi perlu perkuatan implementasi.
Kesimpulan Komparatif
- Tunisiamenjadi model paling progresif: melarang poligami, menaikkan usia nikah, kesetaraan penuh, dan perlindungan KDRT.
- Marokomenghadirkan kompromi progresif: poligami dikontrol ketat, usia nikah dinaikkan, kesetaraan ditegaskan.
- Turkimengandalkan pendekatan sekuler: hanya nikah sipil sah, monogami wajib, kesetaraan hukum ditegakkan.
- Mesirmasih stagnan: ada perbaikan terbatas, namun masih mempertahankan banyak bias patriarki.
Implikasi untuk Indonesia:
- Penting larangan atau pembatasan ketat poligami(Tunisia/Maroko).
- Usia nikah minimal 18–19 tahun tanpa dispensasi longgarharus ditegakkan (Tunisia/Turki).
- Pertegas aspek pencatatan sebagai syarat sah perkawinan(Turki).
- Relasi suami-istri harus egaliter dalam hukum(Tunisia, Maroko, Turki).
- Penguatan perlindungan dari KDRTharus jadi bagian integral hukum keluarga (Tunisia)
Tabel Perbandingan Hukum Keluarga
| Isu | Indonesia (UUP 1974 & KHI 1991) | CLD KHI (2004) | Tunisia | Maroko (Moudawana 2004) | Turki (Civil Code) | Mesir |
| Poligami | Dibolehkan dengan syarat (izin pengadilan, persetujuan istri). | Dilarang, asas monogami. | Dilarang total, sanksi pidana. | Diperbolehkan, tapi syarat sangat ketat, izin hakim & persetujuan istri. Praktis jarang terjadi. | Dilarang total, hanya monogami sah. | Masih dibolehkan, hakim bisa batasi. |
| Usia Nikah | 19 (laki-laki), 16 (perempuan) → direvisi jadi 19 keduanya (2019), tapi dispensasi longgar. | 19 tahun min., 21 kedewasaan penuh. | 18 tahun, tanpa diskriminasi gender. | 18 tahun, tapi hakim bisa beri dispensasi (masih problem). | 18 tahun (17 dengan izin orang tua). | 18 tahun, tapi praktik perkawinan anak masih ada. |
| Pencatatan | Wajib dicatat, tapi bukan syarat sah → nikah siri tetap sah agama. | Syarat sah perkawinan. | Pencatatan resmi syarat sah. | Pencatatan wajib dan syarat sah. | Hanya nikah sipil yang sah; nikah agama tidak punya kekuatan hukum. | Pencatatan wajib, tapi praktik nikah tradisional masih terjadi. |
| Relasi Suami-Istri | Suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP, Pasal 79 KHI). | Suami-istri setara, berbagi hak & kewajiban. | Suami-istri setara penuh dalam keluarga. | Suami-istri sebagai mitra, berbagi tanggung jawab rumah tangga. | Sejak 2001, egaliter dalam hak, kewajiban, dan kepemimpinan rumah tangga. | Masih bias gender: suami kepala keluarga, istri wajib taat. |
| Nafkah | Tanggung jawab suami. | Nafkah tanggung jawab bersama, peran reproduktif perempuan dihargai. | Kewajiban bersama sesuai kesepakatan. | Kedua pihak wajib berkontribusi sesuai kapasitas. | Tanggung jawab ekonomi bersama. | Suami wajib nafkah; istri terbatas hak ekonominya. |
| Perkawinan Beda Agama | Dilarang. | Diperbolehkan dengan prinsip saling menghormati. | Tidak diakui. | Tidak diakui secara formal. | Tidak diatur agama; sipil → bisa lintas agama. | Tidak diperbolehkan. |
| Status Anak Luar Nikah | Hanya diakui hubungan perdata dengan ibu. | Anak diakui memiliki hubungan dengan ayah biologis (dapat dibuktikan). | Anak luar nikah mendapat perlindungan hukum. | Ada proteksi lebih baik, meskipun belum penuh. | Anak luar nikah diakui hukum sipil (DNA & pencatatan). | Hanya diakui dengan ibu, kecuali ada pembuktian. |
| Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | Ada UU PKDRT (2004), implementasi lemah. | Diperlakukan sebagai tindak pidana, perspektif korban. | UU 2017 anti-KDRT, progresif & komprehensif. | Ada aturan pidana, tapi implementasi lemah. | Pernah ratifikasi Konvensi Istanbul; perlindungan hukum ada, tapi politik konservatif melemahkan. | Belum ada UU khusus, KDRT sering dianggap urusan privat. |
Pembelajaran dari perbandingan tsb:
- Jadikan pencatatan/perkawinan sipil sebagai syarat sah, mengurangi kawin sirri dan melindungi hak istri/anak (Teladan: Turki, praktik Tunisia & Maroko).
- Tegaskan asas monogami/atur poligami sangat ketat. Tunisia menunjukkan larangan efektif; Maroko menunjukkan opsi kontrol peradilan (pilih model kebijakan sesuai konteks sosial-politik).
- Samakan dan naikkan usia minimal kawin + batasi dispensasi pengadilan. untuk mencegah perkawinan anak (Tunisia/Maroko).
- Kodifikasi kesetaraan suami-istri dalam hak & kewajiban keluarga(mis. hak asuh, keputusan reproduksi, pembagian pekerjaan rumah tangga), teladan Turki/CLD.
- Perkuat perlindungan terhadap KDRT dan akses layanan(hukuman, shelter, layanan hukum), contoh undang-undang Tunisia 2017 sebagai model pelengkap reformasi keluarga.
- Pastikan reformasi disertai strategi implementasi: pelatihan hakim, harmonisasi antara lembaga agama dan negara, dana untuk layanan sosial, pelajaran dari keterbatasan implementasi Maroko.
Mengapa sulit rekonstruksi?
Upaya rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia memang berulang kali diusulkan melalui amandemen UU Perkawinan, gagasan CLD KHI (2004), maupun revisi pasal-pasal terkait dalam KHI, tetapi selalu menghadapi jalan terjal. Ada beberapa alasan struktural, kultural, dan politik yang menjelaskan mengapa reformasi ini sulit:
- Dominasi Ideologi Patriarki dan Budaya Agama Konservatif
- UU Perkawinan 1974 dan KHI 1991 lahir dalam konteks sosial yang sangat dipengaruhi oleh tafsir fikih klasik patriarkal.
- Narasi agama sering digunakan untuk melegitimasi posisi subordinat perempuan dalam keluarga: suami kepala rumah tangga, istri wajib taat, poligami dianggap “syariat.”
- Ketika CLD KHI muncul dengan gagasan kesetaraan gender, penolakan keras datang dari sebagian ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menuduhnya “sekuler” atau “liberal.”
- Politik Hukum yang Elitis dan Pragmatis
- Produk hukum keluarga di Indonesia lebih merupakan kompromi politik daripada hasil perdebatan akademik atau kajian HAM.
- UU 1974 lahir dengan kompromi panjang antara kelompok Islam, nasionalis, dan pemerintah Orde Baru, sehingga banyak pasal yang ambigu dan kompromistis (misalnya soal poligami: tidak dilarang, tapi dibatasi).
- Hingga kini, setiap usulan perubahan (misalnya larangan poligami) dianggap berisiko politik karena bisa memicu resistensi ormas keagamaan dan mengganggu stabilitas politik.
- Fragmentasi Sistem Hukum
- Indonesia menganut pluralisme hukum: ada hukum negara, hukum Islam (di pengadilan agama), dan hukum adat.
- Upaya menyatukan prinsip kesetaraan gender sering berbenturan dengan dalih “kearifan lokal” atau “syariat Islam.”
- Misalnya, perkawinan anak sering dibenarkan dengan alasan adat atau tafsir agama tertentu, meski bertentangan dengan semangat perlindungan anak.
- Resistensi Institusi Agama
- Kementerian Agama dan Pengadilan Agama adalah lembaga kunci dalam implementasi hukum keluarga.
- Banyak hakim dan birokrat masih menggunakan tafsir konservatif.
- Upaya perubahan, seperti CLD KHI, ditolak keras bukan hanya oleh ormas, tetapi juga oleh lembaga resmi negara karena dianggap “mengganggu otoritas keagamaan.”
- Minimnya Kesadaran Publik dan Edukasi Hukum
- Sebagian besar masyarakat tidak melihat bias gender dalam UU/KHI sebagai masalah, karena sudah “membudaya.”
- Perempuan yang jadi korban diskriminasi pun sering tidak berdaya menggugat, karena ketimpangan ekonomi, sosial, dan pendidikan.
- Akibatnya, tekanan publik untuk perubahan hukum relatif lemah dibanding isu lain (misalnya korupsi atau politik elektoral).
- Kepentingan Status Quo
- Ada kelompok-kelompok yang diuntungkan dari sistem lama:
- Laki-laki yang memiliki privilese poligami atau hak talak.
- Institusi agama yang mendapat otoritas mengatur keluarga.
- Elit politik yang takut kehilangan dukungan jika mendukung perubahan radikal.
- Karena itu, upaya rekonstruksi selalu dipandang sebagai ancaman bagi “tatanan sosial” yang mapan.
- Kurangnya Political Will Negara
- Pemerintah cenderung berhati-hati dalam isu keluarga karena dianggap “isu sensitif.”
- Revisi usia perkawinan (2019) saja terjadi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, bukan inisiatif DPR/pemerintah.
- Isu-isu besar lain (larangan poligami, kesetaraan relasi suami-istri, status anak luar nikah) belum disentuh karena tidak ada keberanian politik.
Kesimpulan
Sulitnya rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia bukan karena kurangnya argumen akademik atau bukti empiris. Hambatannya terutama terletak pada resistensi ideologi patriarki, kompromi politik yang rapuh, pluralisme hukum yang tidak harmonis, serta lemahnya political will negara.
CLD KHI sebenarnya sudah menawarkan cetak biru hukum keluarga progresif, sejajar dengan praktik di Tunisia, Maroko, dan Turki. Namun, tanpa dukungan publik yang kuat, keberanian politik negara, dan reinterpretasi agama yang inklusif, rekonstruksi hukum keluarga akan tetap berjalan sangat lambat.
Peta Aktor Rekonstruksi Hukum Keluarga di Indonesia
| Aktor | Peran Utama | Posisi Pro-Kontra dalam Rekonstruksi Hukum Keluarga |
| Pemerintah (Eksekutif, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kemenkumham) | Regulator, pelaksana kebijakan, penyusun rancangan undang-undang, pengawas implementasi hukum keluarga. | Ambivalen: Kemenag cenderung mempertahankan tafsir konservatif (status quo), sementara KemenPPPA dan Kemenkumham lebih progresif (dorong kesetaraan, perlindungan anak). |
| DPR (Legislatif) | Membahas dan mengesahkan undang-undang, termasuk revisi UU Perkawinan. | Terbelah: sebagian fraksi progresif (nasionalis, perempuan) mendukung kesetaraan gender; sebagian fraksi konservatif menolak larangan poligami/nikah beda agama. |
| Mahkamah Konstitusi (MK) | Penguji UU terhadap UUD 1945; sering jadi jalur reformasi hukum keluarga. | Cenderung progresif: putusan MK menaikkan usia nikah jadi 19 tahun (2019); mengakui anak luar nikah punya hubungan perdata dengan ayah biologis (2010). |
| Mahkamah Agung & Pengadilan Agama | Penafsir dan pelaksana hukum keluarga (UU, KHI). | Variatif: sebagian hakim progresif (menerapkan perspektif gender), sebagian masih konservatif (menekankan ketaatan istri, membolehkan dispensasi kawin). |
| Majelis Ulama Indonesia (MUI) | Otoritas keagamaan dominan, memberi fatwa, memengaruhi kebijakan. | Konservatif: menolak CLD KHI, menentang ide kesetaraan penuh, mempertahankan poligami, posisi suami sebagai kepala keluarga. |
| Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, dll.) | Produksi tafsir agama, pendidikan keumatan, advokasi sosial. | Beragam: |
- NU: relatif moderat, ada gerakan progresif gender (Muslimat, Fatayat, Gusdurian) tapi elite NU kadang konservatif.
- Muhammadiyah: resmi moderat, sebagian kader progresif mendukung kesetaraan.
- Ormas konservatif (HTI, FPI, dsb.) keras menolak rekonstruksi.
- Akademisi & Intelektual Muslim: Produksi pengetahuan, reinterpretasi teks agama, penelitian hukum. Mayoritas progresifdalam studi gender dan Islam, tapi ada akademisi konservatif yang membela status quo. |
- LSM Perempuan (KOMNAS Perempuan, Rifka Annisa, LBH APIK, Yayasan PEKKA, dll.)| Advokasi hukum, pendampingan korban KDRT, riset dan kampanye kesetaraan gender. Progresif: garda depan dalam mendorong revisi UU Perkawinan, perlindungan anak, penghapusan poligami, dan kesetaraan suami-istri.
- Masyarakat Sipil (publik luas, komunitas lokal, tokoh adat/agama). Basis penerima dampak hukum keluarga; aktor kunci penerimaan sosial. Terfragmentasi: sebagian masyarakat (khususnya perkotaan, terdidik) mendukung kesetaraan gender; sebagian besar di daerah rural masih menerima poligami, perkawinan anak, dan hierarki patriarkal sebagai “normal.”
- Media & Jurnalis| Menyebarkan wacana, membentuk opini publik. Campuran: media progresif memberi ruang advokasi gender; media konservatif atau populis menggaungkan “ancaman sekularisasi” bila ada upaya revisi hukum keluarga. |
Analisis Akademik: Kenapa Rekonstruksi Sulit?
- Asimetri kekuatan aktor: kelompok pro-reformasi (LSM, akademisi, MK) lebih lemah dibanding aktor status quo (MUI, birokrasi Kemenag, ormas konservatif).
- Politik kompromi: DPR dan pemerintah sering menunda reformasi untuk menghindari konflik dengan kelompok agama besar.
- Fragmentasi internal: bahkan dalam ormas moderat (NU, Muhammadiyah), ada tarik menarik antara sayap progresif (feminis Muslim) dan konservatif.
- Kurangnya tekanan publik: isu hukum keluarga tidak dianggap prioritas dibanding isu ekonomi atau korupsi, sehingga elite politik tidak punya insentif kuat untuk mendorong perubahan.
Kesimpulan: Rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia sulit karena konstelasi aktor masih didominasi kubu konservatif (MUI, sebagian besar DPR, Kemenag). Gerakan progresif (LSM, akademisi, MK) ada, tetapi belum cukup kuat untuk menembus resistensi struktural dan kultural.
Apa yang seharusnya dilakukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN ?
Mereka memiliki posisi unik dalam upaya rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia. Mereka berada di persimpangan agama, akademik, dan masyarakat, sehingga punya legitimasi moral sekaligus kapasitas intelektual. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:
- Produksi Pengetahuan Baru (Reinterpretasi Teks Agama)
- Mendorong kajian kritis terhadap nash dan fikih klasik yang menjadi dasar UU Perkawinan/KHI, dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan hak asasi manusia.
- Mengintegrasikan gender studies, HAM, dan filsafat hukum Islam dalam kurikulum.
- Menghasilkan riset akademik (tesis, disertasi, jurnal) yang menguatkan argumen teologis dan sosiologis untuk rekonstruksi hukum keluarga.
UIN bisa menjadi pusat pengembangan tafsir progresif tentang poligami, perkawinan anak, dan kesetaraan suami-istri yang kemudian dikutip dalam wacana publik maupun putusan pengadilan.
- Mencetak Sarjana & Hakim Progresif
- Mayoritas hakim Pengadilan Agama dan pegawai Kementerian Agama adalah alumni UIN/PTKIN.
- Dengan kurikulum yang responsif gender, UIN bisa melahirkan hakim dan birokrat keagamaan yang berperspektif keadilan sosial, bukan sekadar formalistik.
- Membuka program khusus klinik hukum keluarga yang melatih mahasiswa memahami persoalan nyata (kekerasan domestik, hak anak, diskriminasi).
- Advokasi Akademik (Policy Engagement)
- Menjadi think tankuntuk pemerintah dan DPR dalam revisi UU Perkawinan, harmonisasi KHI, atau regulasi keluarga lainnya.
- Mengeluarkan policy brief berbasis riset ilmiah untuk mendorong pembuat kebijakan agar lebih peka terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- Membangun kolaborasi dengan KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan rekomendasi hukum.
- Pendidikan Publik dan Moderasi Beragama
- UIN bisa melaksanakan program literasi hukum keluarga untuk masyarakat, melalui dakwah kampus, Pusat Studi Gender, atau KKN tematik di desa.
- Mengarusutamakan diskursus Islam progresif yang menegaskan bahwa kesetaraan suami-istri dan perlindungan anak bukan bertentangan dengan agama, melainkan bagian dari maqashid syariah.
- Menggunakan media sosial, seminar publik, dan kuliah umum untuk mendiseminasikan gagasan reformasi hukum keluarga.
- Kemitraan dengan Ormas Islam
- UIN dapat menjembatani dialog antara kelompok progresif dan konservatif di NU, Muhammadiyah, dan ormas lain.
- Melalui akademisi UIN, bisa dilakukan ijtihad kolektifyang melahirkan tafsir moderat, tidak terlalu “liberal” tapi tetap membawa semangat kesetaraan.
- Teladan Kelembagaan
- UIN sendiri dapat menunjukkan contoh nyata:
- Kebijakan kampus yang ramah gender (anti kekerasan seksual, kesetaraan kepemimpinan).
- Kurikulum perkawinan dan keluarga yang berperspektif kesetaraan.
- Program pembinaan mahasiswa dalam hal relasi gender sehat dan etika berkeluarga.
Kesimpulan
Perguruan tinggi keagamaan Islam seperti UIN bukan hanya institusi akademik, tetapi juga agen perubahan sosial-keagamaan.
- Di ranah ilmu, UIN bisa membongkar bias patriarki dalam tafsir klasik.
- Di ranah kaderisasi, UIN bisa melahirkan hakim dan birokrat progresif.
- Di ranah masyarakat, UIN bisa menjadi corong pendidikan keluarga yang adil, setara, dan melindungi anak.
Dengan posisi ini, UIN punya peluang besar menjadi motor utama dalam rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia menjembatani teks, konteks, dan praksis sosial.
Apa yang dapat dilakukan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga di UIN, maka peran mereka bisa sangat strategis sebagai agen perubahan di level mahasiswa yang kelak akan menjadi hakim, advokat, peneliti, atau aktivis hukum keluarga?
Peran Strategis Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN
1. Penguatan Kapasitas Akademik
- Menyelenggarakan diskusi rutin dan kajian tematiktentang pasal-pasal problematis UU Perkawinan 1974, KHI 1991, dan gagasan CLD KHI.
- Membentuk “komunitas riset mahasiswa”untuk menulis paper, artikel, atau opini di media massa tentang isu perkawinan anak, poligami, status anak, dan kesetaraan suami-istri.
- Mengadakan kelas metodologi tafsir hukum progresif, agar mahasiswa mampu membaca ulang teks fikih dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, gender, dan HAM.
2. Advokasi dan Aksi Sosial
- Membuat kampanye kesadaran hukum keluargadi kalangan mahasiswa maupun masyarakat sekitar kampus (misalnya lewat seminar publik, poster edukatif, konten media sosial).
- Melakukan pendampingan hukum sederhanauntuk masyarakat sekitar kampus (contoh: sosialisasi pencatatan perkawinan, hak anak pasca-cerai, perlindungan dari KDRT).
- Bekerja sama dengan LSM perempuan(misalnya LBH APIK, Rifka Annisa, PEKKA) untuk magang atau program community service.
3. Kolaborasi dan Jaringan
- Menjalin kerja sama dengan Pusat Studi Gender & Anak (PSGA)di kampus, agar himpunan mahasiswa punya akses pada data, narasi, dan advokasi akademis.
- Mengundang hakim Pengadilan Agama progresif, peneliti, dan aktivis perempuan sebagai pembicara di forum mahasiswa.
- Membuat jaringan mahasiswa antar-UIN(misalnya forum Himpunan Hukum Keluarga nasional) untuk bertukar pengalaman dan strategi advokasi.
4. Produksi Pengetahuan Populer
- Membuat buletin hukum keluarga mahasiswa, berisi analisis singkat kasus nyata dan pandangan mahasiswa hukum keluarga.
- Membuat konten kreatif: podcast, video pendek, atau infografis edukasi soal isu hukum keluarga (contoh: “Mengapa pencatatan nikah penting?”, “Risiko perkawinan anak”).
- Membangun arsip digital mahasiswatentang perdebatan UU Perkawinan, KHI, dan CLD KHI sebagai sumber belajar terbuka.
5. Kepemimpinan dan Teladan
- Himpunan bisa menjadirole model organisasi yang ramah gender:
- Kepemimpinan inklusif (perempuan diberi ruang memimpin).
- Aturan anti-kekerasan seksual di internal organisasi.
- Budaya diskusi yang menghargai perbedaan tafsir agama.
- Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya bicara teori kesetaraan, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan organisasi.
6. Strategi Jangka Panjang
- Mempersiapkan kader mahasiswa hukum keluarga untuk menjadi hakim progresifdi Pengadilan Agama melalui study circle khusus putusan-putusan penting MK dan MA.
- Membentuk “Klinik Hukum Keluarga Mahasiswa”di bawah himpunan, yang melatih mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum di masyarakat.
- Menjadikan himpunan sebagai laboratorium advokasi hukum keluarga, tempat mahasiswa belajar bagaimana menghubungkan akademik dengan realitas sosial.
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN bisa menjadi motor penggerak rekonstruksi hukum keluarga dari bawah, dengan tiga modal:
- Pengetahuan(kajian kritis dan riset mahasiswa),
- Gerakan sosial(kampanye, penyuluhan, kolaborasi dengan LSM), dan
- Teladan organisasi(praktik kepemimpinan yang egaliter dan etis).
Unduh tulisan disini