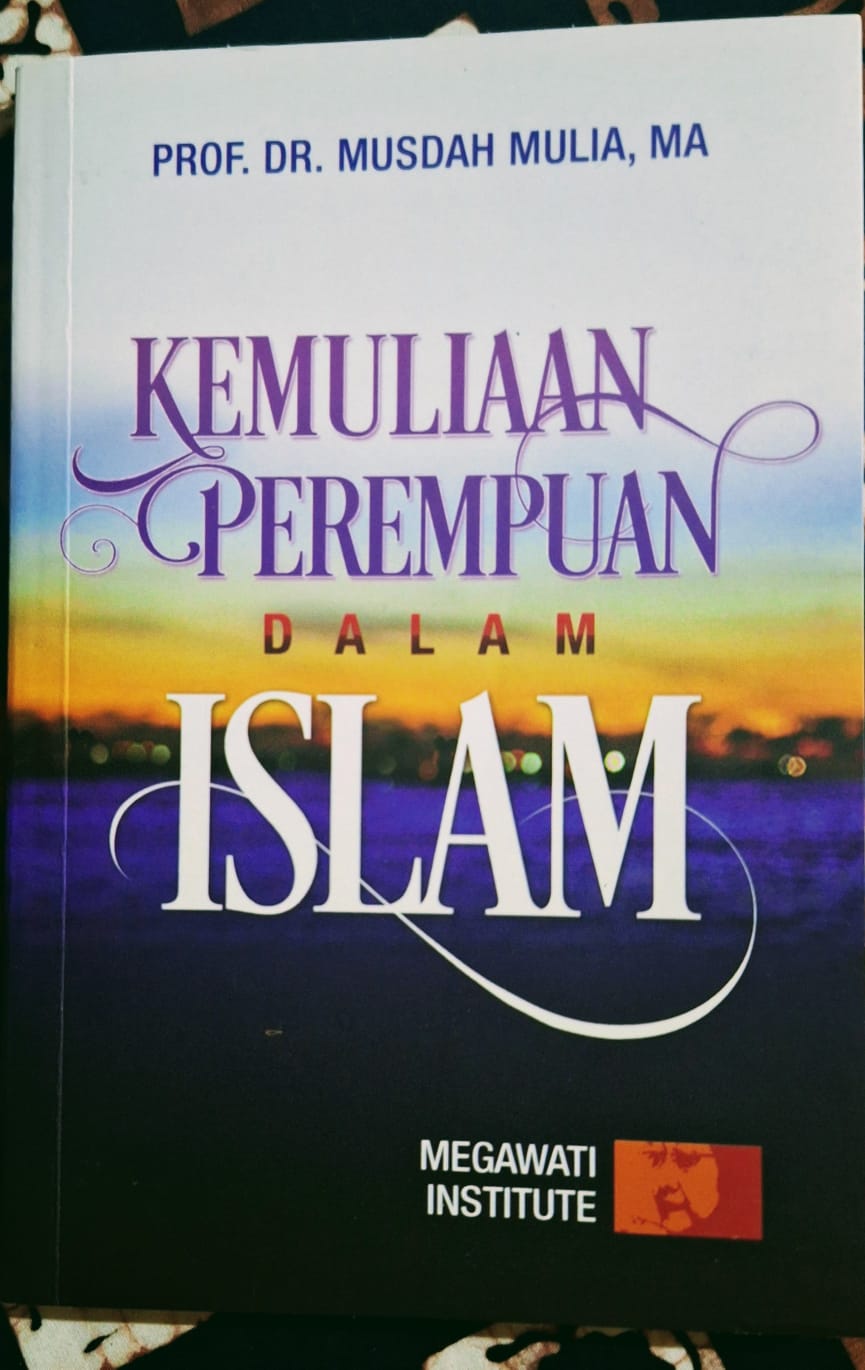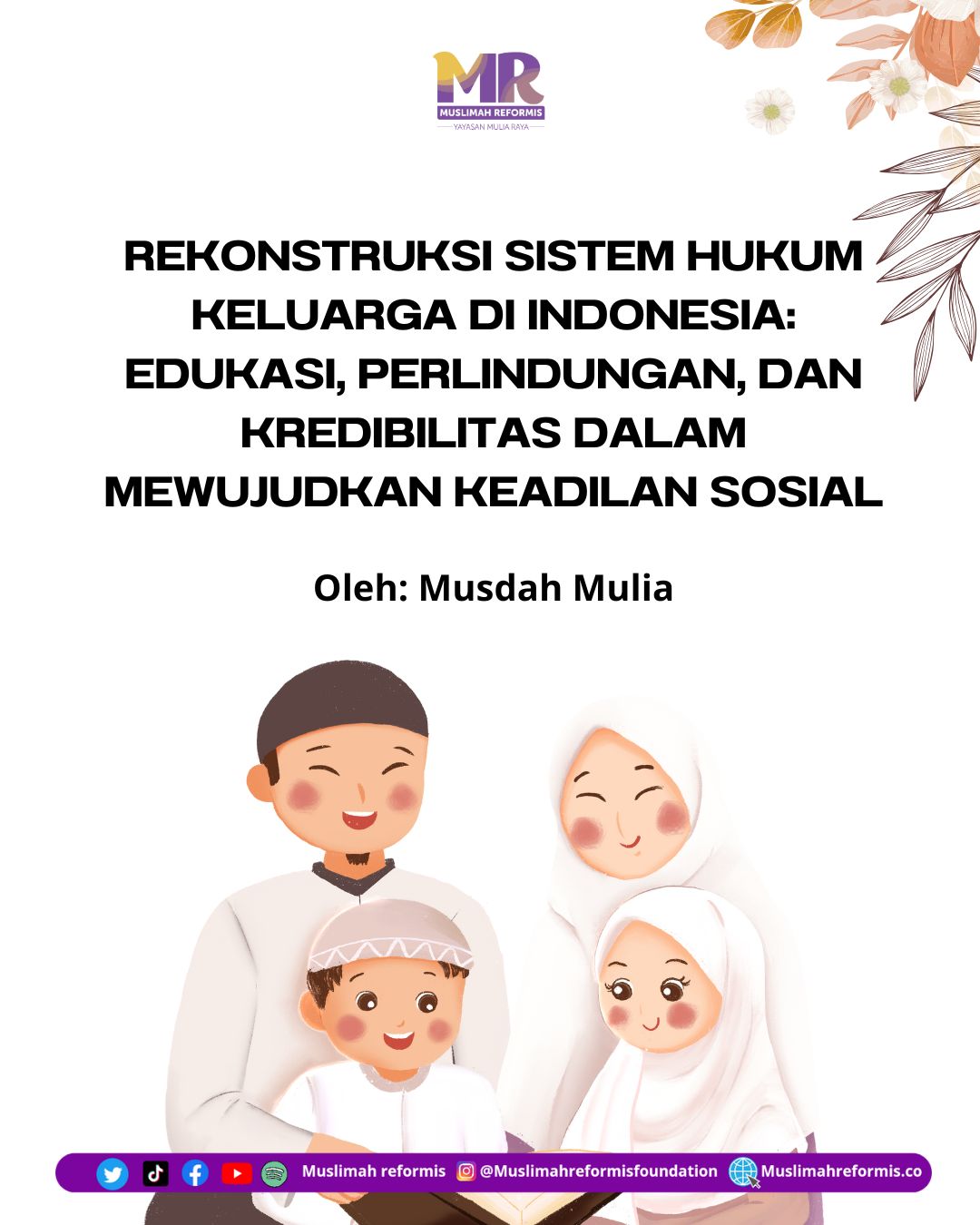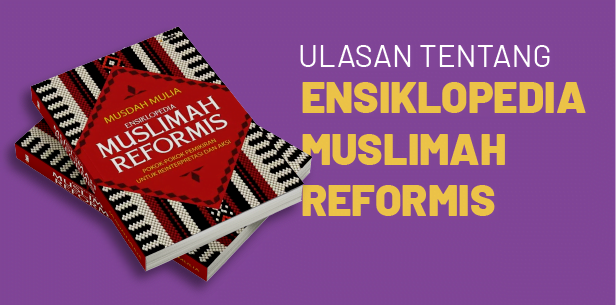Oleh: Musdah Mulia
I. Pendahuluan
Meskipun sejarah Islam dan Nusantara kaya akan figur perempuan pemimpin, literasi dan pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan masih minim. Dalam masyarakat kontemporer, perempuan sering dianggap tidak memiliki legitimasi religius dan sosial untuk memimpin, padahal jejak sejarah menunjukkan sebaliknya. Mengapa kepemimpinan perempuan yang begitu kuat di masa lalu mengalami marginalisasi dalam sejarah dan praksis sosial-politik?
Tulisan ini membahas genealogi kepemimpinan perempuan dalam perspektif sejarah Islam dan konteks kebudayaan Nusantara. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri akar-akar teologis, sosial, dan politik yang membentuk persepsi dan praktik kepemimpinan perempuan dari masa awal Islam hingga peradaban Islam di Nusantara. Tulisan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah anomali, melainkan bagian integral dari dinamika sejarah umat Islam dan bangsa-bangsa di wilayah Nusantara.
Kajian ini menegaskan bahwa meskipun interpretasi patriarkal sempat mendominasi dalam sejarah, warisan Islam awal serta tradisi lokal Nusantara sama-sama mengandung nilai egalitarian yang mengakui kapasitas perempuan dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, rekonstruksi genealogi ini menjadi penting untuk mengembalikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam wacana dan praktik kepemimpinan Islam kontemporer.
II. Landasan Konseptual
Pengertian Genealogi dan Kepemimpinan Perempuan: Genealogi dipahami sebagai metode untuk menelusuri akar historis, epistemologis, dan ideologis dari suatu konsep sosial dan ini mengacu pada Foucault dan Said, diadaptasi dalam konteks Islam dan Nusantara. Kepemimpinan perempuan tidak hanya diartikan sebagai posisi formal, tetapi juga kepemimpinan moral, sosial, dan spiritual.
Genealogi kepemimpinan perempuan adalah upaya memulihkan ingatan peradaban, bahwa perempuan sejak awal menjadi bagian dari pembentukan moral, sosial, dan politik bangsa.
Melalui pendekatan Islam yang progresif dan budaya Nusantara yang egaliter, wacana kepemimpinan perempuan dapat menjadi fondasi teologis, historis, dan etis bagi pembangunan yang adil dan berkeadaban di masa depan.
Isu kepemimpinan perempuan sering kali menjadi medan tarik-menarik antara teks keagamaan dan konteks sosial-budaya. Dalam masyarakat Muslim, perdebatan ini muncul dari berbagai tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis, khususnya terkait konsep qiwāmah (QS. An-Nisā’ [4]:34). Namun, secara historis, peran perempuan dalam kepemimpinan tidak sepenuhnya terpinggirkan. Dalam sejarah Islam klasik maupun sejarah sosial-politik Nusantara, perempuan memainkan peran penting sebagai pemimpin politik, pemimpin spiritual, dan penggerak sosial.
Membicarakan genealogi kepemimpinan perempuan bukan sekadar upaya akademik untuk “menggali sejarah,” tetapi merupakan langkah strategis untuk membongkar bias patriarki dan memulihkan ingatan kolektif tentang peran perempuan dalam peradaban Islam dan Nusantara.
Kerangka Teoretis
Membicarakan genealogi kepemimpinan perempuan adalah upaya dekonstruksi epistemologis terhadap tafsir dan struktur sosial yang menyingkirkan perempuan, sekaligus revitalisasi terhadap semangat keadilan dan rahmah (kasih sayang) yang menjadi inti ajaran Islam. Kita bisa menggunakan teori Feminisme Islam: (Amina Wadud, Asma Barlas, Musdah Mulia), reinterpretasi ayat-ayat kepemimpinan secara egaliter. Dapat juga memanfaatkan Feminisme Nusantara: (Melani Budianta, Gadis Arivia), pentingnya membaca kepemimpinan perempuan dalam konteks budaya lokal dan spiritualitas komunitarian. Sekaligus mengkritisi dekolonisasi pengetahuan: mengoreksi sejarah dan epistemologi yang menyingkirkan perempuan dari ruang kepemimpinan.
III. Literasi Kepemimpinan Perempuan
Mengapa literasi kepemimpinan perempuan tidak berkembang secara signifikan di masyarakat? Berikut analisis ilmiah dan kritis tentang mengapa hal itu terjadi, baik dari sisi historis, sosial, maupun keagamaan:
1.Dominasi Paradigma Patriarkal yang Terinstitusionalisasi: Kultur patriarki bukan hanya persoalan sikap individu, tetapi sudah mengakar dalam institusi agama, pendidikan, dan politik. Dalam banyak konteks, tafsir keagamaan dan adat budaya lebih menekankan kepatuhan perempuan daripada kapasitas kepemimpinan perempuan.
Lembaga keagamaan sering kali mereproduksi tafsir lama yang menempatkan perempuan di wilayah domestik, dan itu dianggap “kodrat”. Akibatnya, masyarakat tidak terbiasa melihat perempuan sebagai pemimpin yang sah, melainkan sebagai pengecualian. Dampaknya: setiap upaya perempuan untuk tampil memimpin sering dihadapkan pada resistensi moral atau keagamaan.
2. Minimnya Produksi Pengetahuan dan Literasi Sejarah Alternatif:Sejarah kepemimpinan di Indonesia dan dunia Islam ditulis dari sudut pandang laki-laki dan kekuasaan politik. Tidak heran jika nama-nama tokoh perempuan besar jarang masuk dalam buku pelajaran sejarah, tafsir, maupun pendidikan agama. Di perguruan tinggi pun, masih sedikit riset dan publikasi yang menggali genealogi kepemimpinan perempuan. Akibatnya: masyarakat tidak memiliki referensi atau narasi alternatif tentang perempuan pemimpin; ruang imajinasi sosial tentang “pemimpin perempuan” pun jadi sempit.
3. Keterputusan antara Tradisi dan Regenerasi
Kepemimpinan perempuan dalam sejarah, baik di Islam maupun Nusantara, sering muncul karena situasi krisis atau luar biasa, bukan hasil sistem kaderisasi berkelanjutan. Setelah tokoh perempuan besar wafat (misalnya Cut Nyak Dien atau Kartini), tidak ada sistem yang melanjutkan visinya. Organisasi perempuan pun kadang masih terfragmentasi antara isu ekonomi, sosial, dan spiritual, tanpa narasi bersama tentang kepemimpinan transformasional. Akibatnya: pengalaman kepemimpinan perempuan bersifat sporadis, tidak menjadi tradisi sosial.
4. Dogmatisasi Agama dan Resistensi terhadap Tafsir Progresif: Dalam konteks keagamaan, literasi kepemimpinan perempuan sering macet karena: Otoritas keagamaan masih sangat maskulin, dan tafsir progresif dianggap “liberal” atau “barat. ”Upaya reinterpretasi ayat-ayat tentang qiwāmah, wilayah, dan kepemimpinan dianggap mengganggu tatanan sosial.Padahal, sejarah Islam awal menunjukkan banyak figur perempuan berpengaruh, misalnya ‘Aisyah sebagai guru para sahabat, atau Ratu Balqis sebagai simbol kepemimpinan yang bijak. Namun, karena otoritas tafsir dikuasai oleh laki-laki, narasi tersebut tidak berkembang menjadi ideologi kesetaraan.
5. Sistem Sosial dan Politik yang Tidak Ramah terhadap Kepemimpinan Perempuan: Struktur partai politik dan birokrasi masih hierarkis dan didominasi laki-laki.Perempuan yang berkompeten sering terkendala oleh politik uang, budaya senioritas, dan bias gender dalam seleksi jabatan publik.Di tingkat komunitas, ruang publik perempuan sering dibatasi oleh stereotip: “perempuan baik tidak usah terlalu tampil. Maka, meski perempuan punya kapasitas kepemimpinan, ruang aktualisasinya tidak sebanding dengan potensinya.
6. Kelemahan Sistem Pendidikan dalam Menumbuhkan Kepemimpinan Inklusif
Membicarakan genealogi kepemimpinan perempuan bukan sekadar upaya akademik untuk “menggali sejarah,” tetapi merupakan langkah strategis untuk membongkar bias patriarki dan memulihkan ingatan kolektif tentang peran perempuan dalam peradaban Islam dan Nusantara. Kurikulum jarang mengajarkan kepemimpinan berbasis etika, empati, dan kesetaraan gender. Buku teks agama masih memperkuat stereotip gender (laki-laki sebagai pelindung, perempuan sebagai pengikut). Akibatnya, generasi muda tidak tumbuh dengan kesadaran kritis tentang kepemimpinan egaliter.
7. Kurangnya Ekosistem Literasi Publik yang Berkelanjutan: Gerakan literasi tentang kepemimpinan perempuan sering bersifat insidental, hanya muncul menjelang peringatan Hari Kartini, Hari Ibu, atau momentum politik. Tidak ada konsistensi dalam membangun ruang baca, media edukatif, dan narasi digitalyang menampilkan perempuan pemimpin sebagai inspirasi. Lembaga pendidikan, ormas, dan media sering bekerja sendiri-sendiri tanpa integrasi naratif. Maka, literasi kepemimpinan perempuan tidak menjadi arus utama wacana sosial.
IV. Kepemimpinan Perempuan dalam Sejarah Islam
Selama berabad-abad, sejarah ditulis oleh laki-laki dan untuk kepentingan struktur sosial patriarkal. Akibatnya, kontribusi perempuan dalam politik, agama, dan sosial sering dihapus, direduksi, atau dipinggirkan. Dalam Islam, figur seperti Khadijah, ‘Aisyah, Ummu Salamah, dan Syifa bint ‘Abdullah menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam kepemimpinan moral, ekonomi, dan intelektual.
Fakta-fakta historis menjelaskan sejak awal Islam, perempuan telah menjadi: Pemimpin ekonomi (Khadijah binti Khuwailid), Guru dan rujukan hukum (Aisyah binti Abu Bakar), Pemimpin militer (Nusaybah binti Ka’ab), Diplomat dan penasihat politik (Ummu Salamah). Maka, melihat kepemimpinan perempuan melalui paradigma Islam memungkinkan kita: Menemukan kembali genealogi peran perempuan yang otentik, Dan menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang berpihak pada keadilan.
Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, seorang pengusaha sukses dan tokoh penting dalam dakwah awal Islam. Ia menjadi simbol kepemimpinan moral, ekonomi, dan spiritual. Adapun ‘Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai ulama besar, ahli hadis, dan sosok yang terlibat dalam peristiwa politik penting seperti Perang Jamal. Perannya menggambarkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan pengaruh politik yang diakui dalam masyarakat Islam awal. Selain itu, Ummu Waraqah, Nusaybah binti Ka‘ab, dan Asma’ binti Abu Bakr menunjukkan bentuk-bentuk kepemimpinan yang variatif: dari kepemimpinan spiritual, militer, hingga sosial. Fakta ini menegaskan bahwa Islam pada masa Nabi tidak menafikan kepemimpinan perempuan, melainkan mengakui kapasitasnya sesuai dengan konteks sosialnya.
Pasca Nabi dan Awal Dinasti Islam: Terjadi restrukturisasi sosial-politik menuju sistem patriarkal, perempuan mulai tersingkir dari posisi publik. Pengaruh politik kekuasaan, penafsiran teks yang bias gender, dan budaya feodal mempersempit ruang perempuan. Hilangnya kepemimpinan perempuan setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ bukanlah karena Islam menolak perempuan memimpin, tetapi karena pergeseran sosial-politik, tafsir keagamaan, dan pembentukan struktur patriarki dalam sejarah Islam klasik. Berikut penjelasan lebih rinci dan ilmiah dalam tiga lapisan: (1) konteks historis-teologis, (2) proses politisasi tafsir dan hukum, dan (3) dampak struktural dalam peradaban Islam
Kemudian muncul era Tradisi Sufistik dengan tokoh perempuan, seperti Rabi’ah al-Adawiyyah menunjukkan bentuk kepemimpinan spiritual dan moral yang sangat berpengaruh, meski tak diakui dalam struktur formal.
Dalam masyarakat Muslim, Islam bukan sekadar agama pribadi, tetapi juga sumber nilai, legitimasi moral, dan norma sosial-politik. Segala bentuk otoritas, termasuk kepemimpinan, biasanya diuji melalui kacamata keagamaan: apakah selaras dengan ajaran Islam atau tidak. Maka, pembicaraan tentang kepemimpinan perempuan tidak bisa dilepaskan dari kerangka epistemologis Islam agar diterima secara sosial dan kultural. Dengan kata lain, paradigma Islam menjadi pintu legitimasi sosial dan moral bagi gagasan tentang kesetaraan kepemimpinan.
Islam secara prinsip menegaskan persamaan derajat laki-laki dan perempuan dalam nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral:“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan…” (QS. Ali Imran [3]: 195)
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13) Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kapasitas moral dan spiritual, bukan jenis kelamin, yang menjadi dasar keunggulan seseorang.Artinya, dari sisi teologi Islam sendiri, tidak ada penghalang prinsipil bagi perempuan untuk memimpin, selama ia amanah dan berintegritas. Karena itu, menafsir ulang paradigma Islam adalah langkah penting untuk mengembalikan semangat keadilan yang menjadi inti Islam.
Ironisnya, meskipun Islam membawa pesan kesetaraan, sejarah panjang interpretasi keagamaan justru didominasi oleh laki-laki, yang menafsirkan teks sesuai konteks sosial patriarkal pada zamannya. Konsep seperti qiwāmah (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) dan wilāyah (otoritas sosial) sering dipahami secara sempit, lalu dijadikan dalih menolak kepemimpinan perempuan. Padahal, para mufasir perempuan dan pemikir Islam progresif menunjukkan bahwa ayat-ayat itu kontekstual, bukan universal. Jadi, mengembalikan wacana kepemimpinan perempuan ke paradigma Islam adalah bentuk dekonstruksi teologis terhadap penindasan yang berlindung di balik agama.
- Islam Sebagai Sumber Etika Kepemimpinan yang Transformatif
Paradigma Islam menawarkan konsep kepemimpinan berbasis amanah, musyawarah, dan keadilan, bukan dominasi. Kepemimpinan dalam Islam bukan superioritas gender, tetapi tanggung jawab moral dan sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan model kepemimpinan yang partisipatif, penuh empati, dan egaliter, termasuk dalam memperlakukan perempuan. Dengan demikian, memahami kepemimpinan perempuan dalam kerangka Islam justru menegaskan bahwa etika kepemimpinan sejati bersifat universal dan inklusif — melampaui sekat gender.
Di dunia Muslim, termasuk Indonesia, Islam bukan hanya agama, tetapi juga bahasa legitimasi publik: Ketika kebijakan atau gagasan disandarkan pada nilai Islam, masyarakat lebih mudah menerima. Wacana kepemimpinan perempuan yang sepenuhnya sekuler sering menghadapi resistensi karena dianggap “asing” dari nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, menggunakan paradigma Islam berarti membumikan kesetaraan dalam bahasa budaya sendiri, bukan dengan kerangka impor. Ini penting untuk membangun kemandirian intelektual dan kultural dalam perjuangan perempuan Muslim.
Banyak gerakan feminis atau advokasi perempuan kehilangan daya spiritualnya karena hanya bersandar pada argumentasi politik atau hukum. Padahal, dalam masyarakat Muslim, kekuatan spiritual Islam adalah sumber motivasi moral yang sangat dalam. Jika kesetaraan dan kepemimpinan perempuan dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan luhur syariat) seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan, maka gerakan ini tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga bermakna teologis. Paradigma Islam menjadikan kesetaraan bukan sekadar hak, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral.
Kita perlu melihat kepemimpinan perempuan melalui paradigma Islam karena:
- Islam adalah basis epistemik dan moral masyarakat Muslim.
- Islam sejatinya mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan spiritual.
- Paradigma Islam perlu direvitalisasi untuk melawan distorsi patriarkal.
- Wacana ini menjadi strategi kultural dan politikagar diterima luas di masyarakat.
- Ia menghubungkan gerakan perempuan dengan akar sejarah dan spiritualitasnya sendiri.
VI. Kepemimpinan Perempuan dalam Sejarah Nusantara
- Era Pra-Kolonial: Sosok perempuan di Nusantara, seperti Cut Nyak Dien, Martha Christina Tiahahu, dan Nyi Ageng Serang menunjukkan kepemimpinan strategis dan spiritual yang luar biasa. Mewacanakan genealogi kepemimpinan perempuan berarti mengembalikan mereka ke dalam narasi sejarah, sebagai subjek, bukan objek.
Sudah dikenal sejumlah nama seperti Ratu Shima (Kalingga), Tribhuwana Tunggadewi (Majapahit), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin (Aceh) menunjukkan legitimasi perempuan sebagai pemimpin politik dan religius. Kepemimpinan perempuan berakar pada konsep kosmologis Nusantara: harmoni, keseimbangan, dan kesakralan peran perempuan sebagai penjaga kehidupan.
2. Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan: Figur seperti Cut Nyak Dien, Martha Christina Tiahahu, Rohana Kudus, Dewi Sartika, dan Rasuna Said melanjutkan tradisi kepemimpinan melalui perjuangan kemerdekaan dan pendidikan. Namun, modernisasi dan politik kolonial membawa sistem patriarki Eropa yang justru memarginalkan peran perempuan.
3. Masa Awal Kemerdekaan: Tokoh seperti Maria Ulfah Santoso, Siti Walidah Nyai Ahmad Dahlan, Rahmah el-Yunusiyyah, SK Trimurti menunjukkan model kepemimpinan perempuan modern: kombinasi spiritualitas, nasionalisme, dan advokasi sosial. Sayangnya, setelah 1950-an, representasi perempuan menurun akibat sistem politik sentralistik dan budaya patriarki yang kembali menguat.
Membahas kepemimpinan perempuan Nusantara tidak cukup hanya dari sisi sejarah faktual, tetapi juga harus dilihat sebagai proyek pengetahuan dan kebudayaan. Agar pembahasannya utuh dan relevan, berikut aspek-aspek utama yang perlu dikedepankan ketika mengkaji atau menulis tentang kepemimpinan perempuan Nusantara, lengkap dengan alasan akademiknya:
- Aspek Historis-Genealogi“Siapa perempuan-perempuan pemimpin di masa lalu, dan dalam konteks apa mereka memimpin?”Menggali genealogi kepemimpinan perempuan dari berbagai kerajaan dan komunitas adat: misalnya Ratu Kalinyamat (Jepara), Tribhuwana Tunggadewi (Majapahit), Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (Aceh), Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Nyi Ageng Serang. Menelusuri bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional yang tidak selalu formal, seperti pemimpin spiritual, adat, atau pendidik masyarakat. Menjelaskan konteks sosial-politik yang memungkinkan mereka tampil, termasuk sistem matrilineal (Minangkabau) atau nilai kesetaraan dalam budaya maritim Nusantara. Tujuannya: menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan produk modernitas Barat, tetapi memiliki akar sejarah lokal yang kuat.
- Aspek Kultural-Antropologis:“Bagaimana budaya Nusantara memandang kepemimpinan, dan di mana posisi perempuan di dalamnya?”Budaya Nusantara mengenal konsep kepemimpinan berbasis harmoni, keseimbangan, dan gotong royong, bukan dominasi. Dalam banyak tradisi lokal, perempuan dipandang sebagai penjaga keseimbangan kosmis dan sosial, misalnya konsep Ibu Pertiwi, Dewi Sri, atau Bunda Tanah. Nilai-nilai lokal seperti rasa, welas asih, dan kebijaksanaanmenjadi dimensi moral kepemimpinan perempuan. Tujuannya: menonjolkan bahwa perempuan Nusantara memimpin dengan gaya yang komunal, spiritual, dan etis, bukan otoritarian.
- Aspek Epistemologis dan Keagamaan:“Bagaimana Islam dan agama-agama lokal memberikan legitimasi bagi kepemimpinan perempuan?”Islam datang ke Nusantara dengan wajah sufistik dan dialogis, yang relatif terbuka terhadap peran perempuan. Banyak pemimpin perempuan yang mendapat legitimasi spiritual, bukan hanya politik, contohnya Sultanah Safiatuddin (Aceh) yang juga ulama dan penulis risalah teologis. Mengaitkan kepemimpinan perempuan dengan nilai-nilai Islam Nusantara: keadilan (`adl), kasih sayang (rahmah), dan amanah. Tujuannya: membangun narasi bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan Islam, justru mewakili ruh keadilan dan kemaslahatan Islam itu sendiri.
Ketika membahas kepemimpinan perempuan Nusantara, aspek-aspek yang perlu dikedepankan adalah:
- Historis–genealogis → menggali jejak kepemimpinan nyata.
- Kultural–antropologis → memahami nilai-nilai lokal yang menopangnya.
- Epistemologis–keagamaan → menafsir ulang legitimasi Islam terhadap kepemimpinan perempuan.
- Sosial–politik → melihat dampak nyata pada masyarakat.
- Filosofis–etis → menggali nilai-nilai kepemimpinan yang humanis dan spiritual.
- Kontemporer–transformasional → menghubungkan masa lalu dengan masa kini.
- Pendidikan–regeneratif → menyiapkan generasi penerus pemimpin perempuan.
VII. Analisis Kritis: Faktor Penghambat dan Pendukung
Faktor Penghambat
- Bias patriarki dalam tafsir agama dan struktur sosial.
- Sejarah yang ditulis oleh laki-laki, mengabaikan pengalaman perempuan.
- Budaya politik maskulin, yang menilai kepemimpinan berdasarkan dominasi, bukan empati atau moralitas.
- Minimnya literasi publik dan kurikulum pendidikan yang inklusif gender.
Faktor Pendukung
- Warisan kultural egaliterdari masyarakat lokal (Minangkabau, Bugis, Aceh).
- Gerakan feminisme Islam dan gerakan perempuan modern.
- Transformasi pendidikan dan media digital, membuka ruang baru bagi figur-figur perempuan inspiratif.
- Kebijakan afirmatif dan dukungan global terhadap kesetaraan gender.
VIII. Rekomendasi Strategis
- Rekonstruksi Kurikulum Sejarah dan Agama: Memasukkan tokoh-tokoh perempuan pemimpin dalam materi ajar.
- Penguatan Literasi Gender di Organisasi Perempuan dan KeagamaanMengembangkan modul pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Islam dan budaya lokal.
- Revitalisasi Narasi Kultural melalui Media dan Seni: Dokumenter, sastra, dan film tentang pemimpin perempuan Nusantara.
- Riset Interdisipliner dan Dekolonial: Menggabungkan studi Islam, antropologi, dan gender untuk menulis ulang sejarah kepemimpinan perempuan.
- Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Keagamaan: Menjadi pusat riset dan advokasi keilmuan berbasis keadilan gender.
- IX.Langkah-langkah Konkret
- Membuka Jalan bagi Transformasi Sosial dan Teologis: Ketika perempuan diakui memiliki tradisi kepemimpinan yang sah, maka: Tafsir keagamaan dapat dibuka kembali untuk membaca ulang ayat-ayat tentang kepemimpinan (imāmah, qiwāmah) secara lebih adil gender. Wacana ini memberi legitimasi historis dan teologis bagi perempuan masa kini untuk mengambil peran kepemimpinan di ruang publik maupun privat. Dengan kata lain, genealogi ini bukan nostalgia, tetapi argumen epistemologis untuk perubahan sosial.
- Menginspirasi Regenerasi Kepemimpinan Perempua: Perempuan muda membutuhkan figur teladan (role model) agar memiliki keberanian menempuh jalur kepemimpinan. Ketika sejarah hanya menyajikan pahlawan laki-laki, maka perempuan sulit melihat dirinya sebagai bagian dari narasi bangsa. Genealogi kepemimpinan perempuan berfungsi sebagai jembatan inspiratif, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan milik satu gender, melainkan ekspresi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.
- Menguatkan Agenda Kesetaraan dalam Pembangunan Nasional: Literasi kepemimpinan perempuan memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan publik:Membantu perumusan kebijakan afirmatif yang lebih peka gender dalam pendidikan, politik, dan ekonomi. Mendorong lembaga agama dan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sejarah inklusif, yang mengajarkan nilai kepemimpinan dari perempuan terdahulu. Menguatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun nasional.
- Melawan “Amnesia Kultural” dan Memulihkan Spirit Keadilan Islam: Wacana ini adalah bentuk perlawanan terhadap “amnesia kultural” yang menyebabkan kita lupa bahwa Islam pada masa Nabi justru melahirkan masyarakat yang membuka ruang bagi perempuan berperan aktif.
- Kesimpulan
Mewacanakan genealogi kepemimpinan perempuan bermakna sebagai proyek keilmuan dan keadilan sosial. Bertujuan menghidupkan kembali tradisi intelektual dan spiritual perempuan serta menjadi basis argumentatif untuk perjuangan kesetaraan di masa kini. Dengan memahami akar historis dan spiritualnya, gerakan perempuan tidak lagi sekadar reaktif terhadap diskriminasi, tetapi berdiri di atas fondasi peradaban yang sah dan kuat.
Genealogi ini memiliki implikasi penting bagi wacana kepemimpinan perempuan Muslim masa kini. Pertama, ia membongkar mitos bahwa kepemimpinan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, ia memperlihatkan bahwa Islam dan budaya Nusantara memiliki akar egalitarian yang dapat dihidupkan kembali untuk memperkuat demokrasi dan keadilan gender. Ketiga, ia mengajak lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan, dan politik untuk membangun tafsir baru yang berkeadilan dan memberdayakan perempuan sebagai pemimpin publik.
Kepemimpinan perempuan dalam Islam dan Nusantara memiliki akar historis yang kuat dan sah secara teologis. Pembacaan patriarkal terhadap teks agama adalah hasil konstruksi sosial yang dapat direvisi melalui pendekatan historis, hermeneutik, dan kontekstual. Sementara itu, sejarah Nusantara memperlihatkan bahwa budaya lokal telah lama membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin, baik di ranah spiritual, sosial, maupun politik. Dengan demikian, menghidupkan kembali genealogi kepemimpinan perempuan berarti menegakkan kembali nilai dasar Islam, seperti prinsip al-‘adl (keadilan) dan al-musāwah (kesetaraan) dalam realitas masyarakat modern.
Rekonstruksi teologi ini juga menuntut penulisan ulang sejarah Islam dengan metodologi gender.Tujuannya bukan mengubah masa lalu, melainkan mengembalikan suara yang dihapus.
Fatima Mernissi menyebut ini sebagai “eksorsisme intelektual terhadap patriarki yang menyamar sebagai Islam.”Dengan metodologi sejarah kritis, para peneliti kini menemukan kembali: ulama perempuan seperti Fatimah al-Fihri, Karima al-Marwaziyyah, dan Zaynab bint al-Kamal, serta pemimpin politik seperti Sultanah Aceh dan Syajarat al-Durr di Mesir abad ke-13. Sejarah Islam sesungguhnya penuh dengan pemimpin perempuan, hanya saja narasinya dikubur oleh penulis sejarah maskulin.
Menegakkan kepemimpinan perempuan berarti menghidupkan kembali Islam yang sejati. Islam yang membebaskan, memanusiakan, dan memuliakan seluruh ciptaan, termasuk perempuan. Selain itu, mengembalikan kejayaan Nusantara dengan nilai-nilai egalitariannya seperti termaktub dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika.
Daftar Pustaka (pilihan)
- Al-Qur’an al-Karim.
- Amina Wadud. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective.Oxford University Press, 1999.
- Riffat Hassan. An Islamic Perspective on Human Rights.
- Siti Musdah Mulia. Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi.Penerbit Dian Rakyat & BACA, 2019.
- Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680.Yale University Press, 1988.
- Azyumardi Azra. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII.Kencana, 2007.
- Peter Riddell & Tony Street (eds). Islamic Thought in the Malay-Indonesian World.ISEAS, 1997.
.