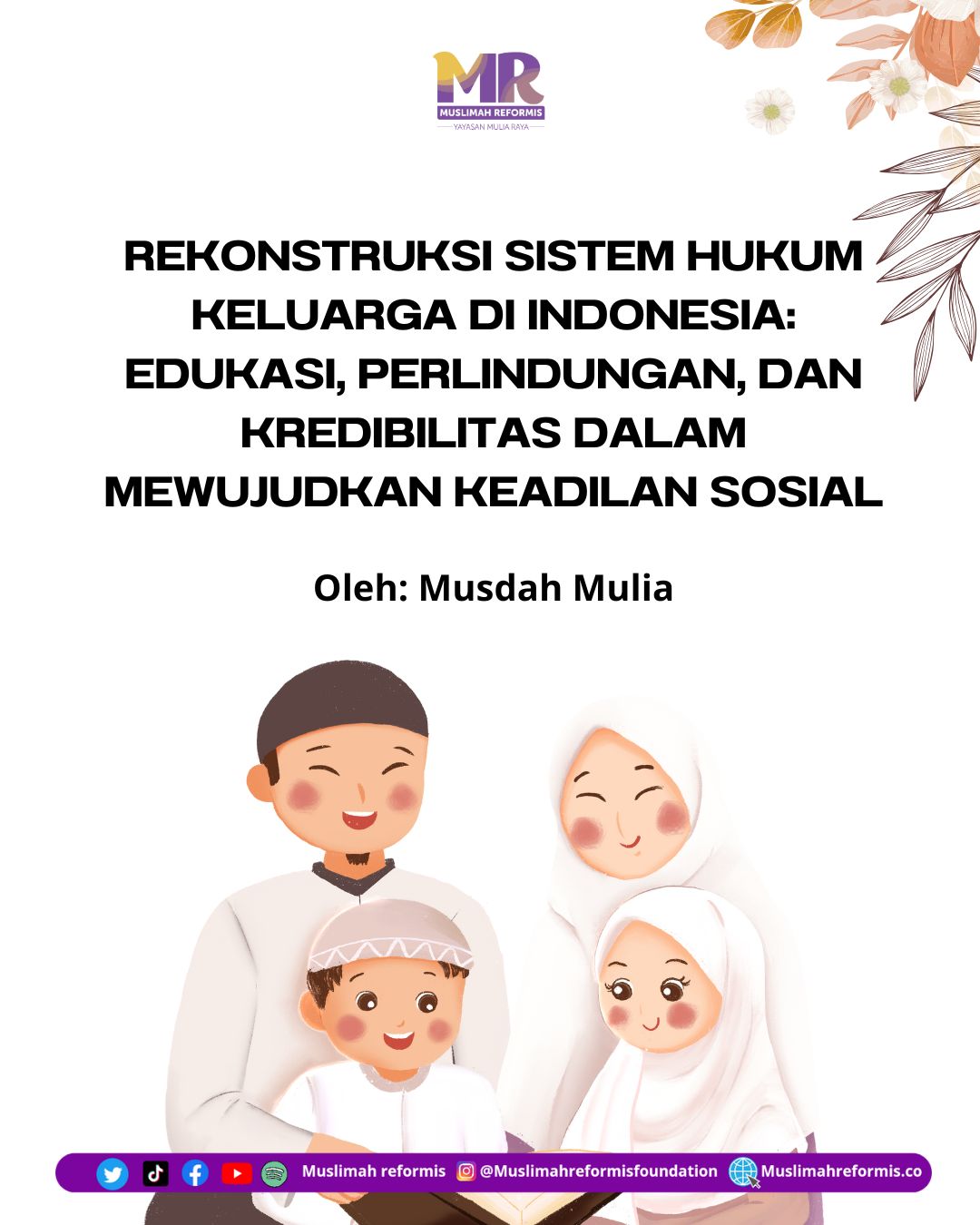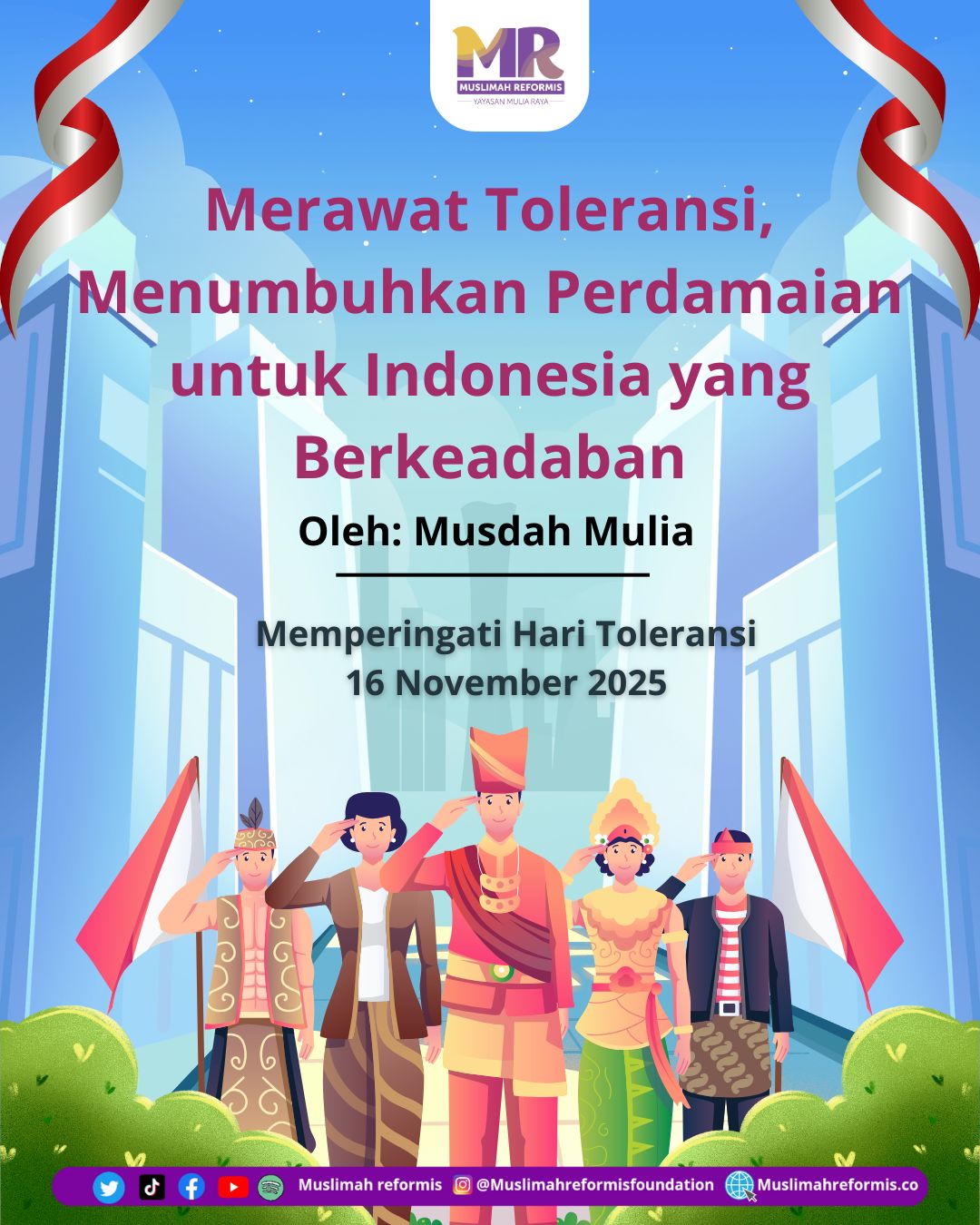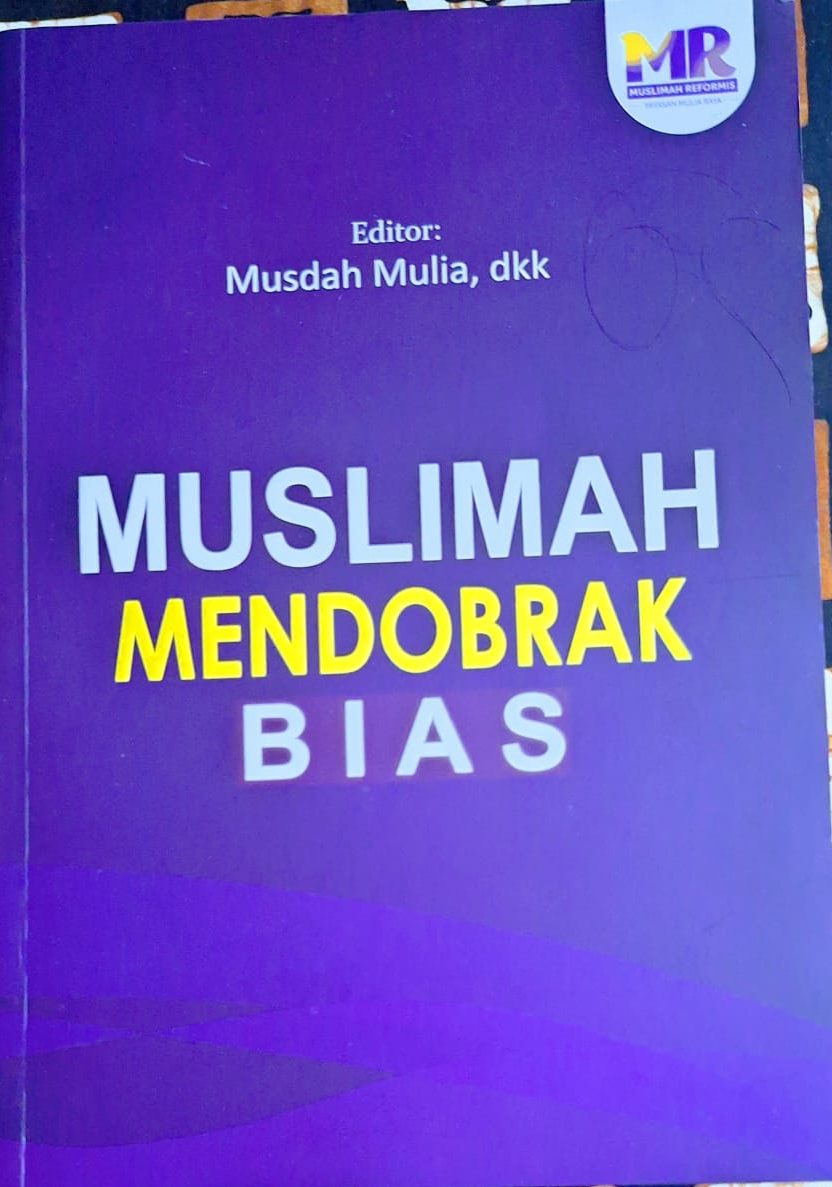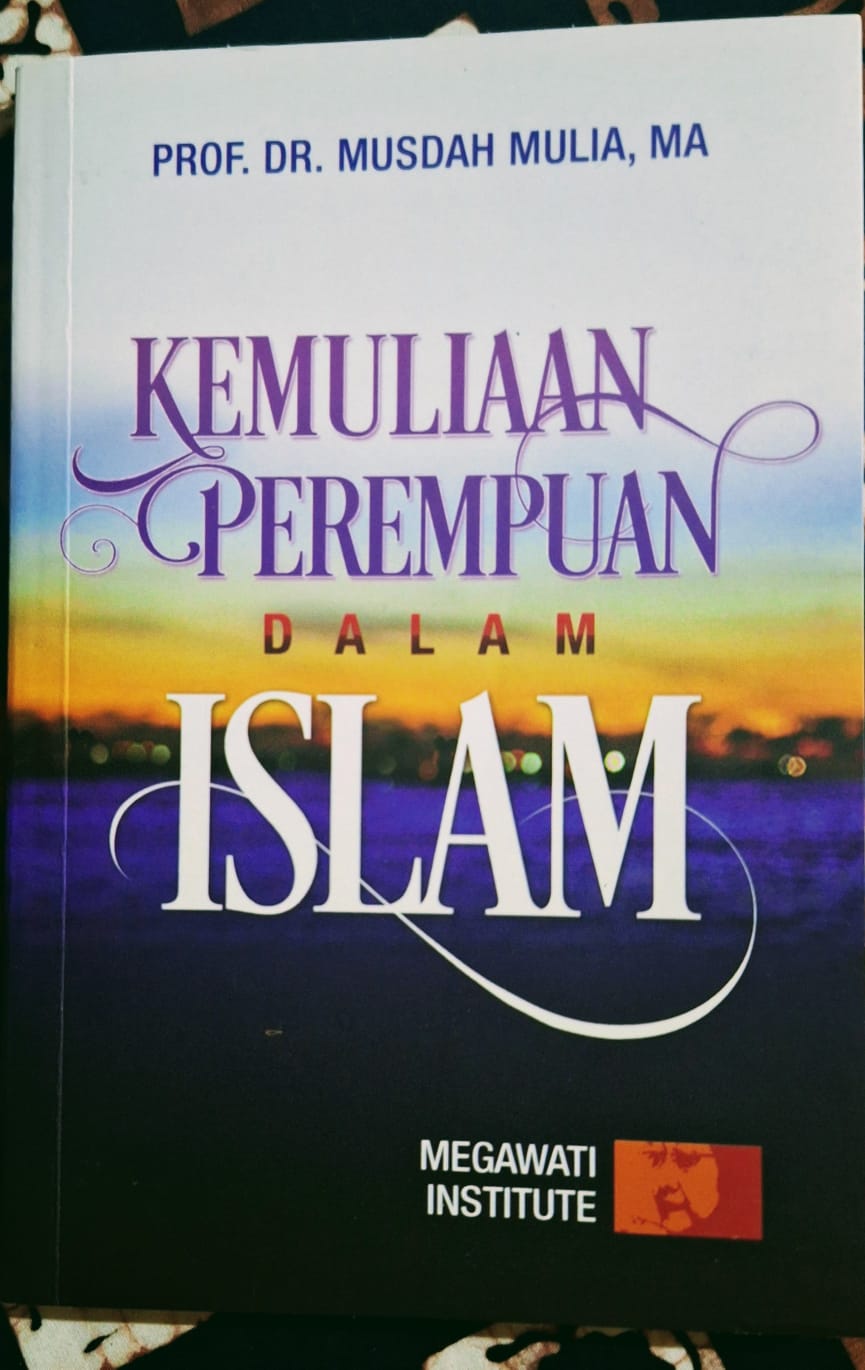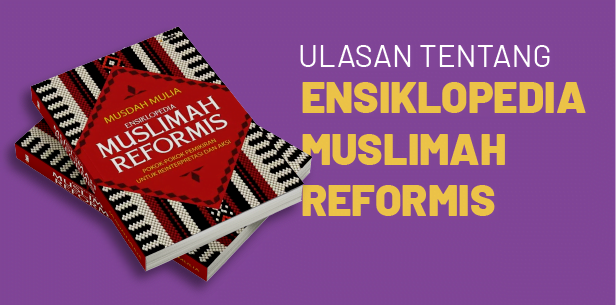Oleh: Musdah Mulia
1.Kondisi aktual sistem hukum keluarga di Indonesia.
Sistem hukum keluarga di Indonesia hingga kini masih berbasis pada dualisme hukum, yakni: Pertama, Hukum Islam, yang diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI, 1991) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019), berlaku bagi warga negara Muslim. Kedua, Hukum Sipil (KUHPerdata), yang mengatur perkawinan dan keluarga bagi warga non-Muslim, masih mengacu pada sistem hukum kolonial Belanda. Selain itu, hukum adat masih hidup dan diterapkan di berbagai komunitas, terutama dalam urusan pewarisan, perkawinan adat, dan perwalian. Dualisme ini menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum dan sering kali mengakibatkan diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan dan anak.
Kondisi aktual sistem hukum keluarga di Indonesia menunjukkan ketegangan antara nilai religius, adat, dan prinsip HAM modern. Meskipun ada kemajuan melalui reformasi hukum dan advokasi perempuan, sistem ini masih belum sepenuhnya emansipatoris. Diperlukan langkah serius untuk membangun hukum keluarga yang egaliter, plural, dan berkeadilan sosial.
Hukum keluarga di Indonesia berfokus pada isu-isu berikut:
- Perkawinan: sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat negara. Namun, masih ada praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan perkawinan anak, yang berdampak buruk terhadap hak perempuan.
- Poligami: diatur ketat dalam UU dan KHI, tapi praktiknya masih ditemukan, terutama di daerah dengan legitimasi sosial tinggi.
- Perceraian: hanya bisa dilakukan di pengadilan, tetapi perempuan sering menghadapi hambatan prosedural dan sosial.
- Hak Asuh Anak dan Nafkah: masih bias terhadap posisi ayah, meski kini semakin banyak putusan progresif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.
Dari aspek kelembagaan juga terjadi dualisme, yakni Pengadilan Agama berwenang untuk keluarga Muslim, sedangkan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Secara umum, reformasi kelembagaan telah memperkuat peran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, tetapi masih ada tantangan berupa: Inkonsistensi putusan antar daerah, Rendahnya pemahaman keadilan gender sebagian hakim, dan Minimnya akses bantuan hukum bagi perempuan miskin.
Hukum keluarga kita masih menghadapi sejumlah tantangan aktual sebagai berikut:
- Ketimpangan gender struktural: Hukum masih memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai istri yang patuh.
- Nikah siri dan poligami tanpa izin masih marak, menyebabkan perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum.
- Ketiadaan undang-undang khusus tentang hukum keluarga nasional yang komprehensif; yang ada masih fragmentaris dan sektoral.
- Minimnya harmonisasi antar sistem hukum (agama, adat, negara) yang menimbulkan tumpang tindih aturan.
- Kurangnya integrasi antara hukum dan kebijakan sosial, misalnya dukungan negara terhadap keluarga miskin, pekerja perempuan, dan anak tunggal.
Reformasi dan Pengaruh Gerakan Perempuan: Para akademisi dan aktivis hukum gender mendorong agar sistem hukum keluarga Indonesia diarahkan menjadi:
- Berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
- Mengakui keberagaman sistem keluarga (monogami, keluarga tunggal, adopsi, dll.);
- Integratif dan inklusif, tidak diskriminatif terhadap minoritas agama maupun gender;
- Berorientasi pada perlindungan anak dan perempuan, bukan semata pada legalitas perkawinan.
Perkembangan terakhir melahirkan sejumlah pembaruan sebagai berikut.
- Kenaikan usia minimum perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki (UU No. 16/2019) merupakan capaian besar hasil advokasi gerakan perempuan.
- Muncul wacana revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih adil gender, tetapi resistensi dari kalangan konservatif masih kuat.
- Pendekatan baru berbasis hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender mulai diadopsi, baik dalam pelatihan hakim maupun kebijakan nasional.
- Permasalahan kredibilitas hukum keluarga
Kredibilitas hukum keluarga merujuk pada tingkat kepercayaan publik terhadap hukum keluarga, apakah hukum tersebut adil dan rasional, konsisten dan dapat ditegakkan, serta relevan dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip kemanusiaan. Permasalahan kredibilitas muncul ketika hukum kehilangan otoritas moral dan legitimasi sosial, karena dianggap tidak lagi mencerminkan keadilan substantif.
Masalah kredibilitas ini muncul karena sejumlah faktor: Pertama, adanya ketidakharmonisan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Indonesia belum memiliki hukum keluarga nasional yang terpadu. Akibatnya, warga negara yang berbeda agama tunduk pada sistem hukum yang berbeda: KHI bagi Muslim, KUHPerdata bagi non-Muslim, dan hukum adat di komunitas tertentu. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus perkawinan campur, pewarisan lintas agama, dan perceraian beda agama. Akibatnya, publik kerap memandang hukum keluarga tidak konsisten dan diskriminatif, sehingga kepercayaannya menurun. Sebagai contoh, Perkawinan antaragama tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 1/1974, sehingga banyak pasangan mencari “celah hukum” melalui pencatatan di luar negeri atau penyesuaian agama formal.
Kedua, bias gender dalam Substansi Hukum. Banyak norma hukum keluarga, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih berpihak pada laki-laki. Misalnya, Pasal 79–83 KHI, menyebut laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang wajib taat. Selain itu, Poligami tetap dilegalkan, dan perempuan hanya diberi hak cerai dalam kondisi tertentu. Hal ini menimbulkan krisis kredibilitas moral, karena hukum dianggap melegitimasi ketidakadilan gender dan bertentangan dengan prinsip konstitusi (Pasal 28D & 28I UUD 1945) tentang kesetaraan warga negara. Menurut hemat saya, hukum seperti ini mencerminkan tafsir agama yang statis dan maskulin, bukan ajaran Islam yang menjunjung keadilan dan rahmah.
Ketiga, ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik sosial. Meskipun hukum melarang perkawinan anak dan poligami tanpa izin, praktik tersebut tetap terjadi di masyarakat. Banyak perkawinan siri tidak tercatat, mengakibatkan perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga tidak efektif menegakkan nilai moral yang diklaimnya sendiri. Akibatnya, hukum dianggap “berbicara di atas kertas”, bukan mencerminkan realitas sosial.
Keempat, Kelemahan dalam Penegakan dan Aparatur Hukum. Masih terdapat inkonsistensi putusan pengadilan agama, bahkan terhadap kasus serupa di wilayah berbeda. Sebagian hakim belum memiliki sensitivitas gender dan HAM yang cukup dalam menafsirkan teks hukum. Minimnya akses bantuan hukum membuat perempuan miskin sulit memperjuangkan haknya. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa hukum keluarga tidak adil bagi pihak lemah dan cenderung berpihak pada laki-laki atau pihak berdaya.
Kelima, Politik dan Ideologi dalam Regulasi. Reformasi hukum keluarga sering terhambat oleh kekuatan konservatif, baik di parlemen maupun ormas keagamaan. Usulan pembaruan (misalnya revisi KHI atau UU Perkawinan berbasis kesetaraan gender) sering dituduh “liberal” atau “anti-Islam”. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum keluarga bukan lagi produk rasional dan moral, tetapi arena pertarungan ideologis. Dalam kerangka Fatima Mernissi, ini disebut sebagai politik pengetahuan, di mana tafsir agama dikontrol oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan patriarkal.
Permasalahan kredibilitas hukum keluarga di Indonesia bersifat struktural dan epistemologis: hukum masih dikuasai tafsir patriarkal, tidak responsif terhadap realitas sosial, dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan gender. Maka, upaya memulihkan kredibilitasnya bukan sekadar memperbarui pasal-pasal, tetapi mereformasi cara berpikir tentang hukum itu sendiri dari alat kekuasaan menuju instrumen kemanusiaan dan kesalingan.
- PeranEdukasi Hukum dalam Konteks Hukum Keluarga
Edukasi hukum (legal education) dalam konteks hukum keluarga tidak hanya berarti pendidikan bagi calon hakim atau advokat, tetapi mencakup: Pendidikan hukum formal di perguruan tinggi; Pendidikan hukum profesional bagi aparatur negara dan pengadilan; Pendidikan hukum masyarakat (legal literacy) agar warga memahami hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, edukasi hukum adalah proses transformasi kesadaran hukum dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi pemahaman kritis atas makna keadilan dalam relasi keluarga, gender, dan sosial.
Tujuan edukasi tersebut, antara lain meningkatkan kesadaran dan literasi hukum keluarga. Banyak persoalan keluarga, seperti perkawinan anak, nikah siri, poligami tanpa izin, atau perceraian sepihak muncul karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.
Edukasi hukum berperan untuk: Menjelaskan prosedur hukum keluarga (pencatatan, perceraian, waris, hak asuh, dll.); Menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban dalam keluarga; Mengurangi praktik-praktik tidak sah yang merugikan perempuan dan anak. Contohnya, Program “Bimbingan Perkawinan” dari Kementerian Agama dapat menjadi ruang edukatif bila tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menekankan hak perempuan, tanggung jawab suami-istri, dan kesetaraan gender.
Selain itu, edukasi ini juga dimaksudkan untuk menjembatani hukum dan budaya masyarakat. Hukum keluarga selalu berhadapan dengan nilai-nilai sosial dan adat lokal.
Edukasi hukum berfungsi menjembatani: Nilai keagamaan dan tradisi lokal, Prinsip hukum negara dan kesadaran masyarakat, dan Norma adat dan hak konstitusional warga. Dengan pendekatan edukatif, hukum tidak lagi dipersepsi sebagai “alat negara”, melainkan panduan moral bersama untuk hidup keluarga yang harmonis dan berkeadilan.
Sayangnya, dalam proses edukasi ini ditemukan sejumlah hambatan aktual seperti: Kurikulum hukum yang masih patriarkal, pembelajaran hukum keluarga di banyak universitas masih berorientasi pada teks klasik tanpa kritik sosial. Kurangnya integrasi gender dan HAM dalam pelatihan aparatur peradilan. Minimnya program literasi hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dominasi tafsir konservatif dalam materi bimbingan perkawinan dan penyuluhan agama. Ketimpangan akses informasi hukum antara laki-laki dan perempuan.
Edukasi hukum memainkan peran sentral dan strategis dalam sistem hukum keluarga Indonesia.
Ia menjadi jembatan antara hukum dan keadilan sosial, antara teks dan konteks, serta antara negara dan rakyat.Tanpa edukasi hukum yang kritis, humanis, dan berbasis kesetaraan, sistem hukum keluarga akan tetap stagnan dan kehilangan kredibilitas moralnya. Namun dengan edukasi hukum yang emansipatoris, hukum keluarga dapat menjadi instrumen pembebasan, bukan pembatasan sejalan dengan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
- Rekonstruksi regulasi hukum keluarga
Sejumlah faktor menghendaki segera dilakukan upaya rekonstruksi. Dualisme hukum (agama–negara–adat) menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi. KHI dan UU Perkawinan masih bias gender: konsep kepala keluarga, poligami, talak sepihak, dan posisi istri yang subordinatif. Perubahan sosial: meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi ekonomi, dan pluralitas keluarga modern tidak terakomodasi. Tuntutan HAM dan konstitusi: Pasal 28D, 28E, 28I UUD 1945 menegaskan kesetaraan tanpa diskriminasi gender. Krisis kredibilitas moral: hukum keluarga kerap dianggap tidak adil dan tidak relevan dengan realitas masyarakat.
Rekonstruksi hukum keluarga harus berlandaskan pada empat prinsip utama seperti tergambar dalam matriks berikut:
| Prinsip | Makna Substantif |
| Keadilan (al-‘adl) | Menghapus semua bentuk subordinasi dan ketimpangan gender. |
| Kesalingan (al-mubādalah) | Relasi suami–istri sebagai mitra setara, bukan hierarki. |
| Kemaslahatan (al-maṣlaḥah) | Hukum harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, perempuan, dan keluarga. |
| Hak Asasi dan Konstitusionalitas | Setiap regulasi harus sejalan dengan UUD 1945 dan konvensi internasional seperti CEDAW. |
Subyek yang dilindungi dalam hukum keluarga meliputi:
a. Perempuan: masih banyak perempuan yang tidak memahami hak hukumnya dan tidak memiliki akses bantuan hukum saat terjadi perceraian atau kekerasan. Untuk itu, perlu penyadaran bahwa mereka punya hak sebagai berikut: Hak untuk menentukan pasangan dan usia perkawinan tanpa paksaan. Hak atas kesetaraan posisi dalam rumah tangga, baik ekonomi maupun pengambilan keputusan. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi (UU KDRT). Hak untuk bekerja dan berpendidikan tanpa diskriminasi. Hak atas harta bersama (gono-gini) secara adil.
b. Anak: Data Komnas Anak menunjukkan meningkatnya kekerasan terhadap anak di ranah domestik, menandakan lemahnya fungsi perlindungan hukum yang preventif. Anak memiliki hak-hak asasi berikut. Hak atas identitas dan status hukum yang sah (akta kelahiran, pengakuan ayah-ibu). Hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Hak untuk tidak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi dalam keluarga. Hak untuk tetap mendapat kasih sayang dan dukungan meski orang tuanya bercerai.
c. Suami dan Anggota Keluarga Lain: Hak suami atas perlakuan setara dan tanggung jawab bersama dalam ekonomi dan pengasuhan. Hak orang tua lanjut usia atas penghormatan dan dukungan dari anak-anaknya (nilai yang juga dilindungi hukum adat dan moral Islam).
Arah Rekonstruksi Substansi Regulasi
a. Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Tegaskan monogami sebagai prinsip dasar; poligami hanya diperbolehkan atas dasar kemanusiaan luar biasa, bukan hak laki-laki.
- Hapus klausul “suami kepala keluarga” dan “istri mengurus rumah tangga”.
- Tambahkan pasal mengenai kesetaraan tanggung jawab ekonomi dan pengasuhan.
- Perkuat aturan perlindungan terhadap perkawinan anak, kekerasan domestik, dan perceraian sepihak.
- Akui perkawinan lintas agamadalam bingkai perlindungan konstitusional.
b. Reformasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lakukan ijtihad kontekstualterhadap pasal-pasal yang bias gender.
- Ganti paradigma “hak dan kewajiban suami-istri” menjadi “kesepakatan dan kemitraan rumah tangga.”
- Perluas penafsiran waris berbasis maqāṣid al-syarī‘ahagar perempuan memiliki hak ekonomi proporsional dengan tanggung jawabnya.
- Tambahkan bab khusus tentang hak anak, adopsi, dan perlindungan korban kekerasan rumah tangga..
c. Integrasi Hukum Adat dan Pluralisme Keluarga
- Akui keberagaman bentuk keluarga di Indonesia (keluarga tunggal, adopsi, keluarga lintas budaya).
- Integrasikan nilai-nilai adat yang sejalan dengan HAM ke dalam hukum nasional.
- Bentuk Peraturan Pemerintahatau Perda adaptif yang menghormati kearifan lokal tanpa melanggar kesetaraan gender.
d. Harmonisasi dengan Hukum Internasional
- Sinkronkan regulasi nasional dengan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)dan CRC (Convention on the Rights of the Child).
- Pastikan hukum keluarga menjamin non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan sosial.
Rekonstruksi tidak akan berhasil tanpa perubahan epistemologi hukum Islam. Untuk itu, perlu membuka ruang bagi ijtihad perempuan dan akademisi progresif dalam merumuskan regulasi; Mengembangkan hermeneutika kontekstual dalam tafsir hukum keluarga; Mengganti paradigma “fiqh klasik” dengan “fiqh emansipatoris” yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum.
Rekonstruksi regulasi hukum keluarga Indonesia adalah proyek moral dan kebangsaan: Bukan sekadar mengubah teks hukum, tetapi mengubah cara berpikir tentang keluarga, kesetaraan, dan keadilan. Ia harus berdiri di atas tiga fondasi: teologi tauhid yang egaliter, konstitusi yang menjamin hak asasi, dan realitas sosial yang plural. Membangun hukum keluarga yang adil adalah jalan menuju masyarakat berperadaban, di mana laki-laki dan perempuan berjalan sejajar, bukan saling menundukkan.”
5.Bagaimana perlindungan hak dalam hukum keluarga?
Perlindungan hak dalam hukum keluarga berarti memastikan bahwa setiap individu, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya memperoleh: Kesetaraan di hadapan hukum; Perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran; Akses terhadap keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga Dengan kata lain, hukum keluarga tidak hanya mengatur tata hubungan privat, tetapi juga melindungi hak-hak dasar manusia di dalam keluarga.
Landasan Yuridis Perlindungan Hak
| Landasan | Isi Pokok |
| UUD 1945 Pasal 28A–28I | Menjamin hak hidup, hak keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. |
| UU No. 1 Tahun 1974 (jo. UU No. 16/2019) | Mengatur hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anak, dan pembatasan usia perkawinan. |
| UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT | Menjamin hak perempuan dan anak bebas dari kekerasan domestik. |
| UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak | Menjamin hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. |
| UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM | Menegaskan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. |
| CEDAW & CRC (Konvensi Internasional) | Menjadi dasar moral dan hukum bagi penghapusan diskriminasi gender dan perlindungan anak. |
Subyek yang dilindungi dalam hukum keluarga meliputi:
a. Perempuan: masih banyak perempuan yang tidak memahami hak hukumnya dan tidak memiliki akses bantuan hukum saat terjadi perceraian atau kekerasan. Untuk itu, perlu penyadaran bahwa mereka punya hak sebagai berikut: Hak untuk menentukan pasangan dan usia perkawinan tanpa paksaan. Hak atas kesetaraan posisi dalam rumah tangga, baik ekonomi maupun pengambilan keputusan. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi (UU KDRT). Hak untuk bekerja dan berpendidikan tanpa diskriminasi. Hak atas harta bersama (gono-gini) secara adil.
b. Anak: Data Komnas Anak menunjukkan meningkatnya kekerasan terhadap anak di ranah domestik, menandakan lemahnya fungsi perlindungan hukum yang preventif. Anak memiliki hak-hak asasi berikut. Hak atas identitas dan status hukum yang sah (akta kelahiran, pengakuan ayah-ibu). Hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Hak untuk tidak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi dalam keluarga. Hak untuk tetap mendapat kasih sayang dan dukungan meski orang tuanya bercerai.
c. Suami dan anggota keluarga lain: Hak suami atas perlakuan setara dan tanggung jawab bersama dalam ekonomi dan pengasuhan. Hak orang tua lanjut usia atas penghormatan dan dukungan dari anak-anaknya (nilai yang juga dilindungi hukum adat dan moral Islam)
6. Implementasi putusan dan penegakan hukum keluarga yang adil
Implementasinya berart, Mampu menjalankan putusan pengadilan, prosedur hukum, dan mekanisme perlindungan keluarga dengan berlandaskan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Artinya, aparat hukum (hakim, panitera, jaksa, polisi, KUA, lembaga sosial, dan pemerintah daerah) harus memastikan hak-hak perempuan, anak, dan pihak lemah benar-benar terlindungi, bukan hanya menjalankan teks hukum secara kaku.
Implementasi dan penegakan hukum keluarga yang adil adalah puncak dari reformasi hukum nasional yang beradab. Keadilan keluarga tidak lahir hanya dari bunyi undang-undang, tetapi dari berbagai faktor berikut. a) Hakim yang berperspektif kesetaraan, b) Eksekusi yang efektif, c) Mekanisme perlindungan yang nyata, dan d) Partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaannya.
Beberapa problem struktural masih menghambat keadilan dalam praktik:
- Bias gender di lembaga peradilan agama dan masyarakat.
Banyak putusan masih berpihak pada suami atau kepala keluarga laki-laki. - Dualisme hukum dan tafsir konservatif.
Putusan sering hanya berdasarkan KHI 1991 tanpa mempertimbangkan prinsip HAM atau maqāṣid al-syarī‘ah. - Keterbatasan akses hukum bagi perempuan dan anak.
Terutama di daerah terpencil, proses hukum sulit dijangkau secara ekonomi dan geografis. - Tidak adanya mekanisme eksekusi putusan yang efektif.
Misalnya, nafkah anak atau harta gono-gini sulit ditagih setelah perceraian. - Kurangnya sinergi antar-lembaga.
Pengadilan Agama, Kemenag, dan Dinas Sosial sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum Keluarga
| Prinsip | Makna dan Implementasi |
| Keadilan Substantif | Hakim wajib menafsirkan hukum sesuai konteks sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar bunyi teks. |
| Kesetaraan Gender | Tidak boleh ada putusan yang menguntungkan satu pihak hanya karena jenis kelamin. |
| Perlindungan Pihak Lemah | Anak, perempuan, lansia, dan disabilitas harus menjadi prioritas perlindungan. |
| Kepastian dan Efektivitas Hukum | Putusan harus dapat dijalankan secara nyata dengan mekanisme eksekusi yang jelas. |
| Aksesibilitas dan Partisipasi | Semua warga harus mudah mengakses layanan hukum, bantuan hukum, dan proses peradilan yang transparan. |
7.Penguatan peran lembaga pendidikan dan organisasi sosial
| Lembaga | Peran dalam Implementasi dan Penegakan |
| Pengadilan Agama/Negeri | Mengadili perkara perkawinan, perceraian, waris, dan hak asuh anak. |
| KUA (Kantor Urusan Agama) | Melakukan pencatatan nikah dan memberikan penyuluhan pranikah berbasis kesetaraan. |
| KemenPPPA & Komnas Perempuan | Memberikan perlindungan dan advokasi terhadap korban diskriminasi dan KDRT. |
| LBH & P2TP2A | Memberikan bantuan hukum gratis, konseling, dan pendampingan bagi korban. |
| Polisi & Jaksa | Menegakkan hukum pidana keluarga (terutama KDRT dan penelantaran anak). |
| Lembaga Sosial & Adat | Mendukung reintegrasi sosial dan mediasi berbasis nilai lokal yang sejalan dengan HAM. |
Penguatan Peran Lembaga Pendidikan
| Tingkatan | Strategi dan Bentuk Penguatan | Tujuan |
| Sekolah Dasar & Menengah | Integrasi nilai kesetaraan, anti-kekerasan, dan pendidikan karakter dalam kurikulum Pancasila dan agama. | Menanamkan nilai adil gender dan saling menghormati sejak dini. |
| Madrasah & Pesantren | Pengembangan kurikulum fiqh keluarga berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dan keadilan gender. | Melahirkan santri dan ulama yang memahami hukum Islam progresif. |
| Perguruan Tinggi | Pendirian Pusat Studi Hukum Keluarga dan Gender di universitas Islam dan hukum. | Menghasilkan riset, rekomendasi kebijakan, dan kader akademik pembaharu hukum. |
| Pendidikan Nonformal | Kelas literasi hukum keluarga, pelatihan pranikah, dan sekolah orang tua. | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara langsung. |
Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Sunan Kalijaga telah mengembangkan modul “Hukum Keluarga Berkeadilan Gender” untuk calon penghulu dan mahasiswa hukum Islam.
Penguatan Peran Organisasi Sosial dan Keagamaan
| Jenis Organisasi | Strategi dan Kontribusi | Dampak yang Diharapkan |
| Ormas Keagamaan (NU, Muhammadiyah, dll.) | Menyusun fatwa dan panduan keluarga adil gender, mengadakan majelis taklim yang menanamkan nilai kesalingan (mubādalah). | Meningkatkan penerimaan sosial terhadap tafsir Islam progresif. |
| Organisasi Perempuan (Aisyiyah, Fatayat, Muslimat, Nasyiatul Aisyiyah, Rahima, dll.) | Advokasi hukum, pelatihan kader perempuan, dan pendampingan korban kekerasan. | Menguatkan posisi perempuan sebagai subjek hukum dan agen perubahan. |
| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | Menyediakan layanan hukum gratis, konseling keluarga, dan pendidikan masyarakat. | Memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan. |
| Komunitas Adat dan Lokal | Mengintegrasikan nilai lokal (gotong royong, musyawarah) dengan prinsip kesetaraan gender. | Menumbuhkan keadilan keluarga berbasis kearifan lokal. |
| Media dan Organisasi Pemuda | Kampanye digital dan kreatif mengenai hak-hak keluarga dan kesetaraan gender. | Mengubah opini publik dan menekan budaya kekerasan domestik. |
Rekomendasi Implementatif
- Program Nasional Edukasi Hukum Keluarga: melibatkan sekolah, pesantren, kampus, dan ormas keagamaan.
- Pelatihan Kader Adil Gender di Ormas dan Komunitas: membentuk fasilitator lokal untuk menyebarkan nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.
- Sekolah Pranikah berbasis HAM dan Maqāṣid Syariah: wajib bagi calon pasangan, difasilitasi oleh KUA bekerja sama dengan LSM.
- Gerakan Literasi Digital Hukum Keluarga: kampanye hak keluarga dan anti-KDRT melalui media sosial dan platform daring.
- Integrasi Riset Akademik dengan Advokasi Sosial: hasil penelitian kampus diterapkan dalam kegiatan ormas dan lembaga layanan masyarakat.
- Studi kasus dan Best Practicing
- Kasus: Pengadilan Agama Cianjur dan Sistem E-Court Cerai Gugat. Fokus: Akses keadilan bagi perempuan pedesaan. Praktik Baik: Pengadilan Agama Cianjur menjadi pelopor layanan e-court cerai gugat bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin yang sulit hadir langsung di pengadilan. Sistem ini bekerja sama dengan LBH APIK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, menyediakan pendampingan hukum dan psikologis. Dampak positif: proses lebih cepat, biaya lebih ringan, dan mengurangi tekanan sosial terhadap perempuan yang menggugat cerai. Pelajaran: Digitalisasi hukum bisa memperluas akses keadilan, asal diiringi pendampingan sosial dan edukasi hukum di tingkat akar rumput.
- Kasus: Putusan MA No. 22/Pdt.G/2017/PA.Mdn (Mahkamah Agung, 2018). Fokus: Perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat Isi Putusan: Mahkamah Agung mengakui status hukum anak hasil perkawinan siri setelah diuji dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Dampak: Membuka jalan bagi perlindungan hukum anak-anak dalam keluarga non-formal atau perkawinan tidak tercatat. Menggeser paradigma dari legal-formal menuju keadilan substantif. Pelajaran: Hak anak harus ditempatkan di atas formalitas hukum perkawinan orang tua.
- Kasus: Program Mediasi Restoratif di Pengadilan Agama Yogyakarta. Fokus: Pencegahan perceraian dan keadilan relasional. Praktik Baik: Pengadilan bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga dan LSM Rifka Annisa melakukan mediasi berbasis restorative justice, bukan sekadar menengahi, tapi juga mendidik pasangan tentang kesetaraan dan komunikasi sehat. Bila perceraian tak terhindarkan, mediasi memastikan hak nafkah dan asuh anak disepakati adil. Pelajaran: Pendekatan edukatif dan psikologis memperkuat fungsi pengadilan sebagai ruang keadilan sosial, bukan sekadar lembaga formal.
- Kasus: Advokasi “Gerakan Stop Perkawinan Anak” (Koalisi 18+). Fokus: Reformasi usia minimum perkawinan. Praktik Baik: Koalisi organisasi perempuan, akademisi, dan lembaga agama berhasil mendorong amandemen UU Perkawinan No. 1/1974 menjadi UU No. 16/2019, menaikkan usia kawin perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Proses ini melibatkan pendekatan agama, budaya, dan HAM. Menjadi contoh sinergi masyarakat sipil, negara, dan lembaga pendidikan.Pelajaran: Pembaruan hukum keluarga efektif jika diiringi gerakan sosial berbasis kesadaran publik dan data lapangan.
- Kasus: Putusan MA No. 69/PK/AG/2015 tentang Pembagian Harta Bersama. Fokus: Keadilan ekonomi bagi perempuan pasca-cerai Isi Putusan: MA menegaskan istri berhak atas separuh harta bersama meski tidak memiliki penghasilan tetap, karena kontribusi domestik juga bernilai ekonomi. Dampak: Meneguhkan prinsip keadilan substantif gender. Dijadikan rujukan bagi banyak hakim agama untuk menafsirkan konsep syirkah(kerja sama) dalam rumah tangga secara setara. Pelajaran: Interpretasi progresif teks hukum Islam dapat menghasilkan keadilan sosial tanpa menafikan prinsip syariah.
- Kasus: KUA Ramah Perempuan dan Anak di Jawa Timur dan NTB. Fokus: Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak. Praktik Baik: KUA bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan edukasi pranikah berbasis kesetaraan gender dan hak anak. Program ini menurunkan angka dispensasi nikah dan meningkatkan kesadaran hukum keluarga di tingkat komunitas. Pelajaran: Lembaga agama bisa menjadi agen utama transformasi nilai keadilan gender jika dibekali pelatihan sensitif gender dan HAM.
Praktik-praktik terbaik tersebut menunjukkan bahwa: a) Reformasi hukum keluarga tidak hanya lewat legislasi, tetapi juga lewat inovasi kelembagaan, putusan progresif, dan pendidikan sosial-hukum. b)Kolaborasi antara pengadilan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan. c) Arah terbaik hukum keluarga Indonesia ke depan adalah membangun sistem hukum keluarga yang partisipatif, berkeadilan gender, dan berbasis nilai kemanusiaan universal.
Rekomendasi kebijakan dan langkah strategis ke depan.
1. Reformasi Regulasi yang Holistik dengan melakukan hal-hal berikut. Menyusun Undang-Undang Hukum Keluarga Nasional yang komprehensif dan lintas agama, agar tidak lagi terfragmentasi antara hukum Islam, hukum perdata, dan adat. Memasukkan prinsip kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap keragaman keluarga dalam batang tubuh undang-undang. Meninjau ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar selaras dengan nilai-nilai HAM, maqashid syariah (kemaslahatan), dan keadilan substantif.
2. Penguatan Perspektif Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum. Di antaranya melalui: Melatih hakim, mediator, dan aparat peradilan agama maupun sipil untuk memahami pendekatan keadilan berbasis gender, anak, dan kemanusiaan. Mendorong praktik mediasi restoratif yang menekankan solusi damai dan perlindungan hak, bukan sekadar penyelesaian formal perkara.
3. Digitalisasi dan Akses Keadilan: Perluasan layanan hukum digital (e-court, konsultasi daring, e-legal aid) hingga ke daerah terpencil. Menjamin akses bagi perempuan miskin melalui subsidi layanan hukum, posbakum berbasis komunitas, dan mobile court.
4. Integrasi Hukum dengan Kebijakan Sosial: Negara perlu menghubungkan hukum keluarga dengan program sosial seperti bantuan nafkah anak, jaminan bagi ibu tunggal, dan perlindungan perempuan korban KDRT. Mengintegrasikan data hukum keluarga dengan data sosial BPS dan BKKBN untuk perencanaan pembangunan keluarga yang adil dan sejahtera.
Membangun sistem hukum keluarga Indonesia yang adil dan kredibel
Membangun sistem hukum keluarga Indonesia yang adil dan kredibel memerlukan: Transformasi nilai, institusi, dan kesadaran publik. Regulasi harus diperbarui, pendidikan hukum diperkuat, dan masyarakat diberdayakan agar hukum keluarga menjadi ruang emansipasi sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar pengendalian moral atau kekuasaan patriarki.
DAFTAR PUSTAKA UTAMA
- Mulia, Musdah (2005). Islam Menggugat Poligami.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ——————- (2019). Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi.Jakarta: Dian Rakyat / BACA.
- Wadud, A. (1999). Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective.New York: Oxford University Press.
- Mernissi, F. (1991). The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam.Reading, MA: Addison-Wesley.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan No. 69/PK/AG/2015 tentang Pembagian Harta Bersama.Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).Jakarta: Departemen Agama RI.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. (2020). Keluarga Sakinah: Panduan Bimbingan Pra Nikah Berperspektif Gender.Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing.
unduh file disini