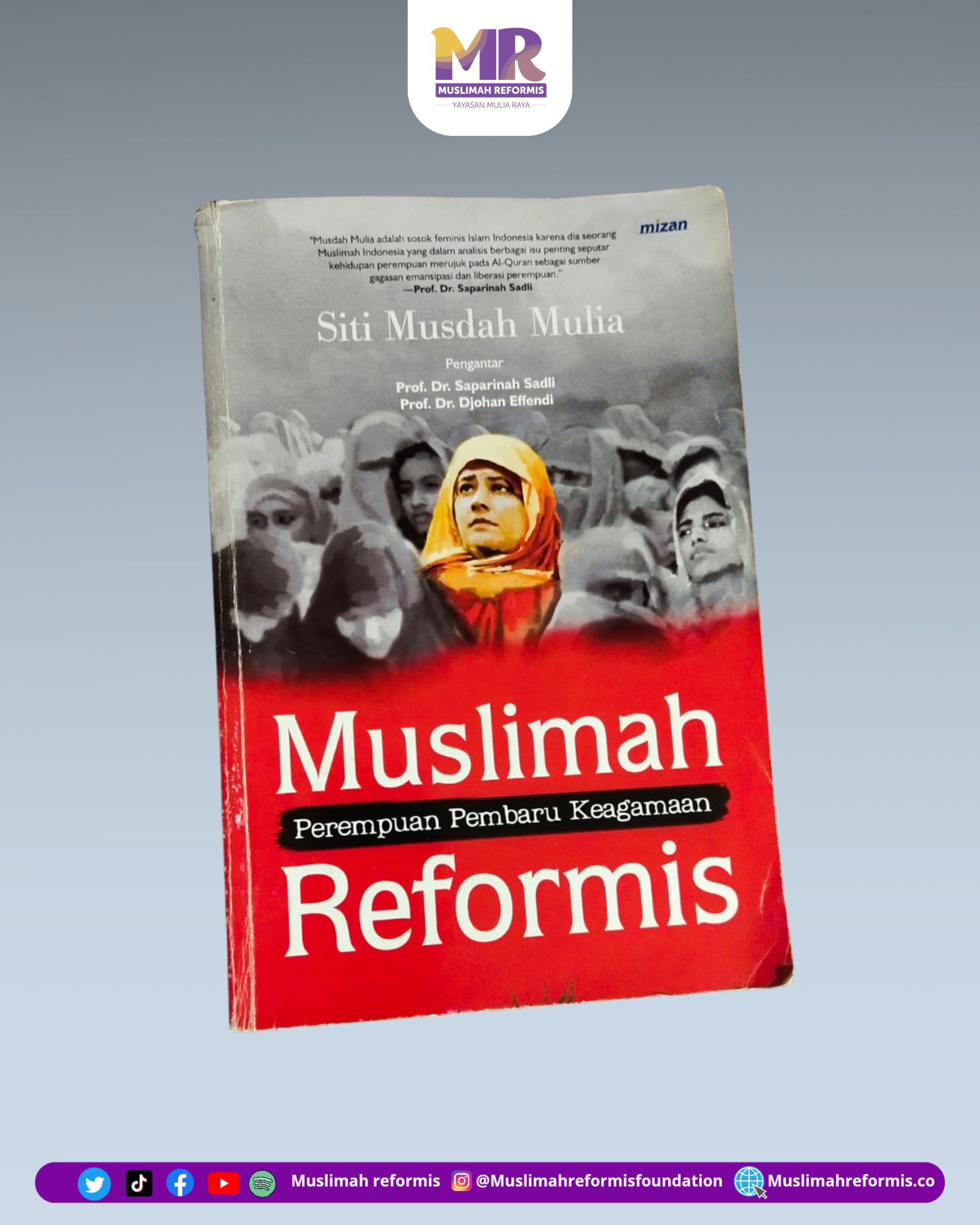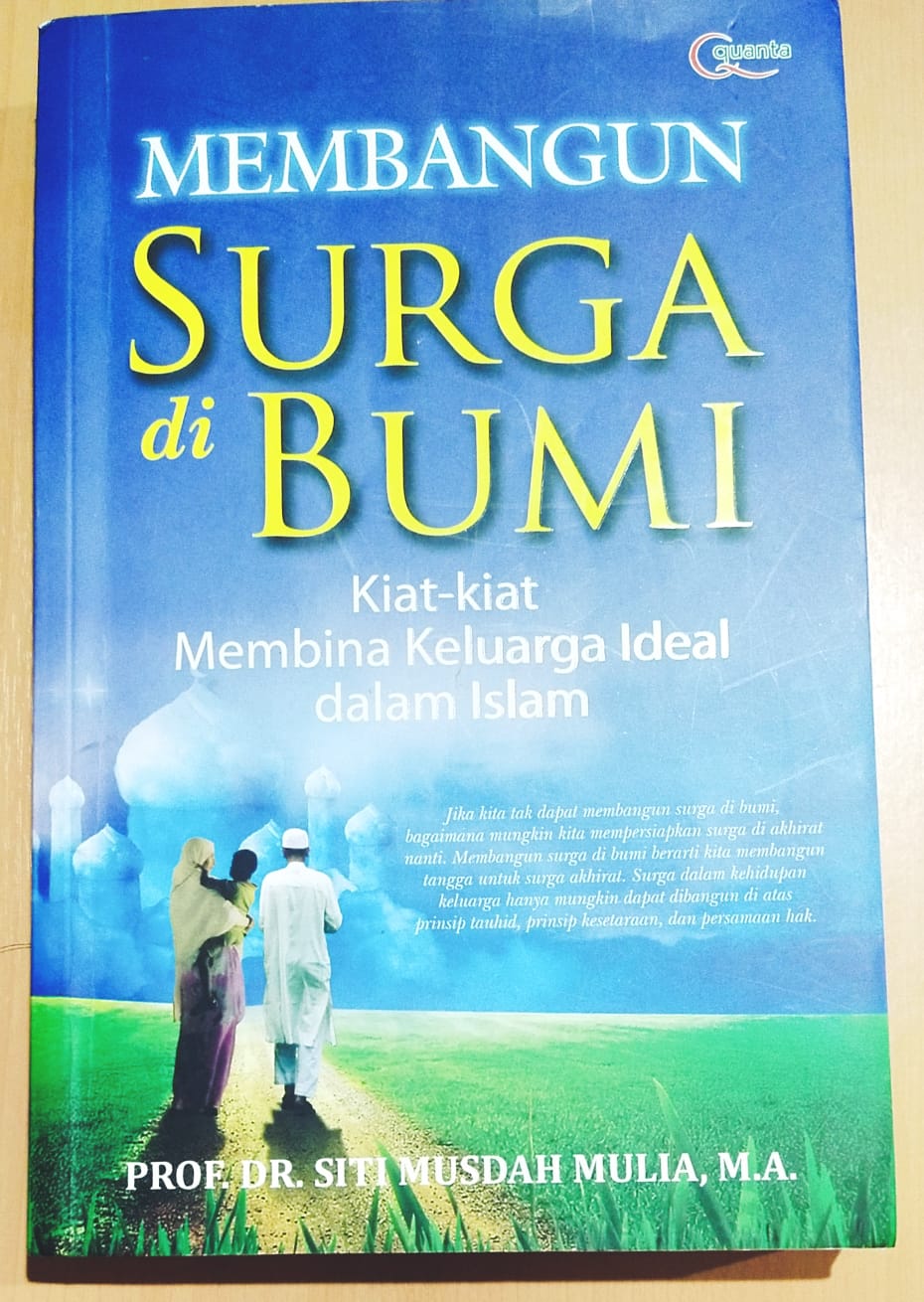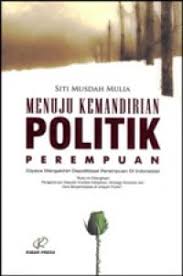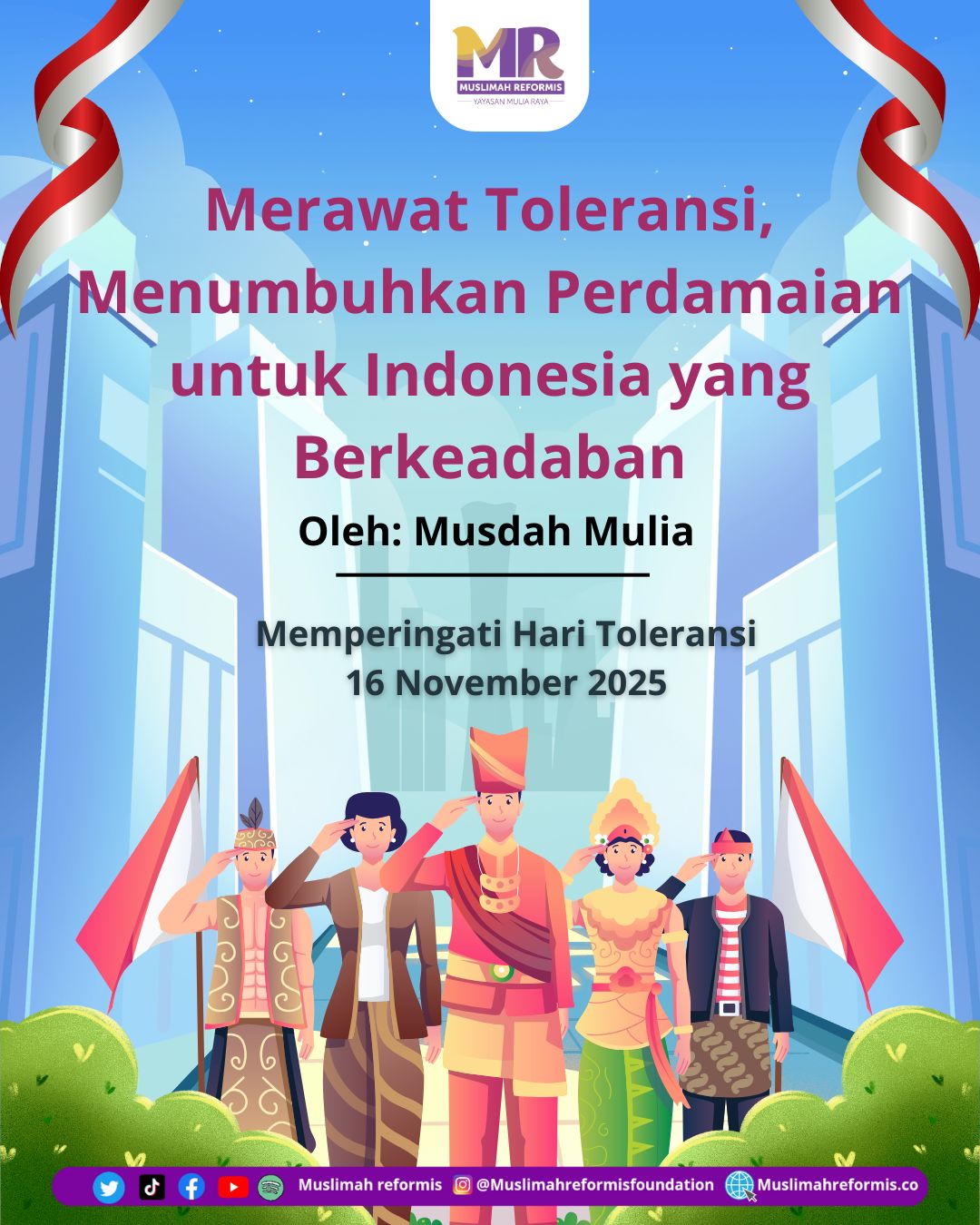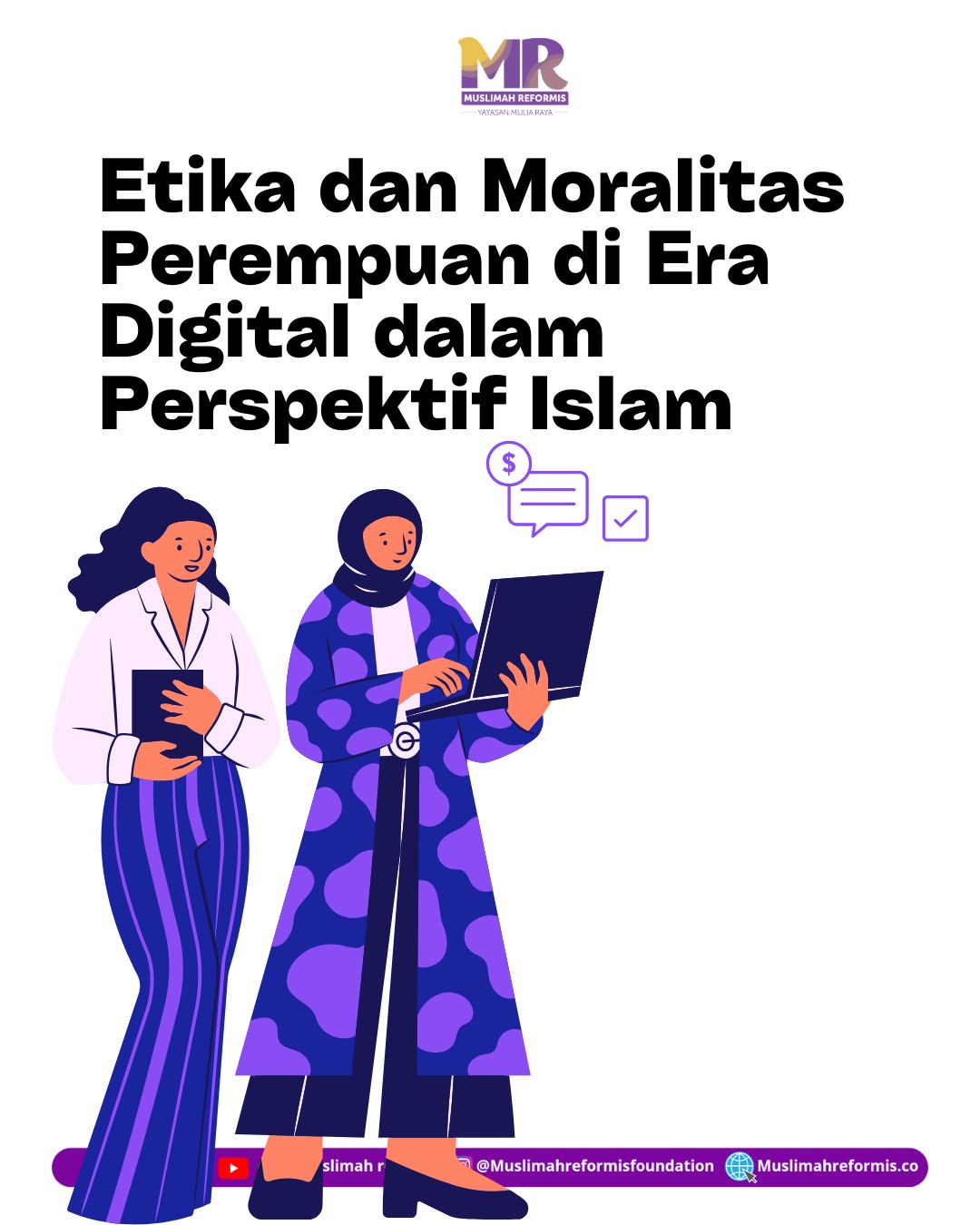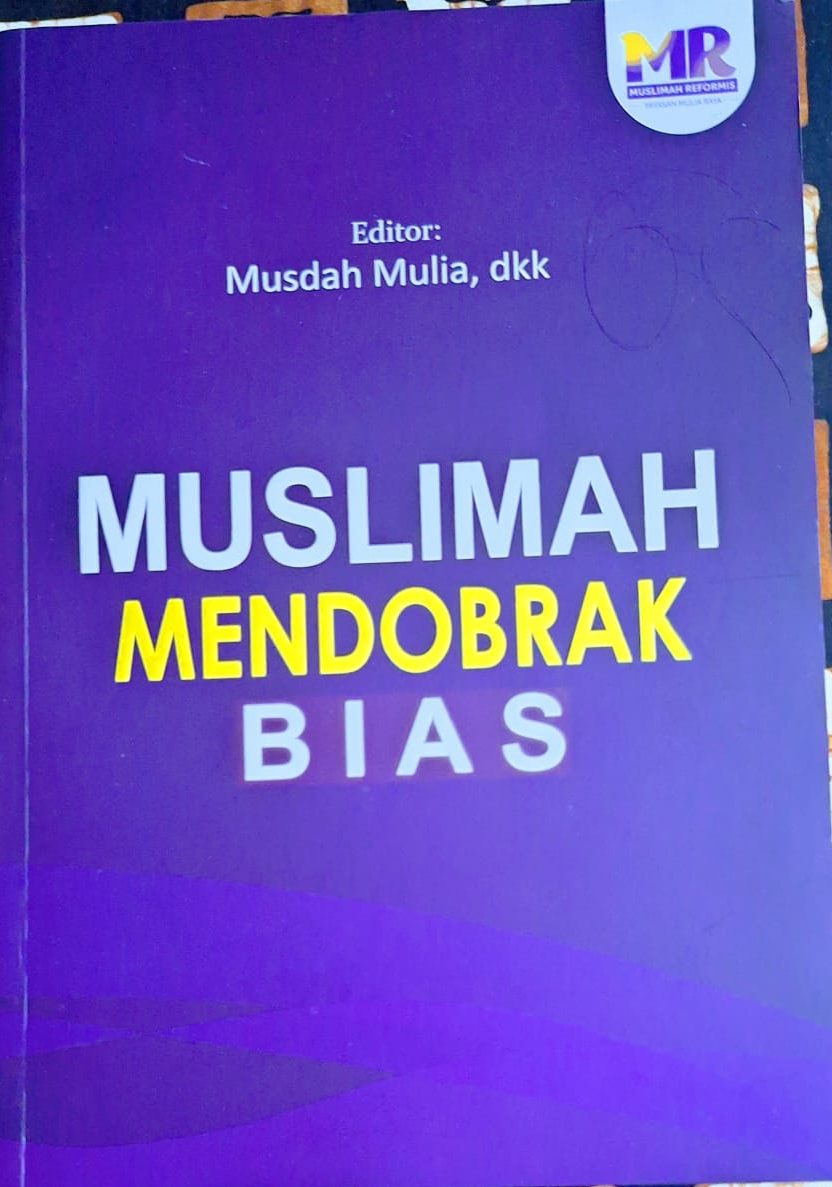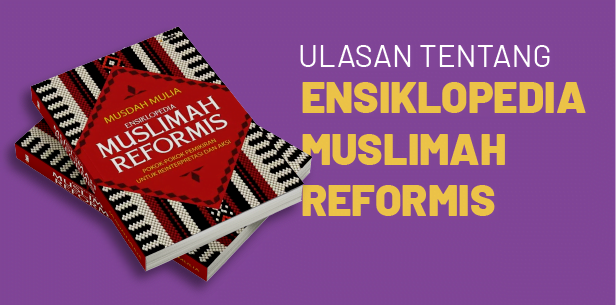(Pendiri Rumah Kajian Filsafat Makassar, Pembina Komunitas Literasi Perempuan Makassar)
Untuk pemesanan buku melalui pengembaraanpikiran.blogspot.com
Perjalanan Lintas Batas bukan sekadar judul. Tetapi lebih sebagai kesaksian. Kesaksian seorang perempuan, cendekia, dan pejuang yang berjalan menembus sunyi meski tubuh terluka, pikiran yang mengendap, dan hati yang masih percaya bahwa iman dan cinta bisa menjembatani segala yang koyak. Buku ini bukan sekadar refleksi, tetapi lebih sebagai doa panjang yang dirangkai dalam narasi yang jujur, halus, dan tajam.
Prof. Musdah menulis buku ini, bukan dari menara gading akademik, tetapi dari lorong-lorong perjuangan. Dari ruang-ruang dialog antar-iman yang hangat meski tegang, dari sunyi perempuan yang disalahpahami oleh tafsir yang kaku, dari perjalanan ke negeri jauh sambil membawa pesan-pesan cinta yang kadang ditertawakan. Buku ini, lebih seperti mosaik yang hidup. Setiap fragmen kisahnya adalah potongan cermin yang memantulkan keberanian melintasi batas. Bukan batas geografis semata, tetapi juga batas batin, budaya, bahkan tafsir. Ia lebih seperti doa yang ditulis dengan tinta keberanian.
Diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2023, buku ini terdiri atas rangkaian esai reflektif yang membentang melintasi ruang, budaya, dan keyakinan. Disusun dalam bentuk semi-memoar, yang tidak terikat oleh sistematika akademik yang kaku. Tetapi justru dari situ, narasinya lebih mengalir bebas dan personal, mengajak pembaca berjalan bersama untuk menyelami pergulatan batin.
Ada satu kisah dalam buku ini yang masih terngiang, bahkan setelah halamannya ditutup. Sebuah forum antar-iman di sebuah negara mayoritas non-Muslim, di mana Prof. Musdah berdiri di tengah keraguan, bukan karena orang luar, tetapi dari sesama umat Islam sendiri. Di sana, Prof. Musdah tak hanya bicara, tetapi menyentuh: tentang perdamaian, keadilan, dan cinta. Di akhir forum, seorang perempuan Yahudi memeluknya sambil berbisik, “Tuhan kita mungkin disebut dengan nama yang berbeda, tetapi cinta yang kamu bawa membuatku merasa pulang.”
Tubuh perempuan bukan hanya menjadi bingkai identitas, tetapi juga ladang tafsir. Dalam sejarah yang panjang, tubuh perempuan kerap diposisikan sebagai sumber keraguan, bahkan dosa. Tetapi dalam buku ini, tubuh hadir sebagai tempat yang dimuliakan, tempat Tuhan bekerja secara halus melalui pengalaman batin yang kompleks.
Prof. Musdah mengajak kita untuk melihat ulang bagaimana tubuh seringkali menjadi medan kuasa moral dan agama, bahkan ia tak ragu menantang tatanan yang telah membungkam suara perempuan selama berabad-abad. Prof. Musdah mengajak pembaca untuk berpikir ulang, bahkan atas hal-hal yang selama ini kita anggap telah pasti dan final.
Ketika Prof. Musdah bicara tentang menjadi ibu, santri, istri, dan perempuan yang berpikir di tengah tradisi keagamaan yang konservatif, sebenarnya ia sedang membentangkan fragmen luka yang tak sepenuhnya bersifat personal. Ini luka kolektif. Luka perempuan yang dibentuk oleh tafsir-tafsir yang seolah pasti, padahal dibaca dari satu sisi sejarah. Prof. Musdah mengingatkan kita untuk bertanya: mengapa keadilan terasa jauh dalam ruang-ruang tafsir agama? Mengapa kita menuhankan teks, tetapi sambil mengabaikan konteks?
Prof. Musdah percaya, bahwa ayat-ayat Tuhan tidak pernah diskriminatif. Yang bias adalah mata kita, dan yang cacat adalah tafsir yang kita pelihara tanpa jeda permenungan. Karena itu, ia menulis bukan untuk menyalahkan, tetapi lebih untuk menyibak. Membuka tirai yang menutupi kelembutan Islam itu sendiri. Sebuah agama yang lahir dari rahmat, dan bukan ancaman. Sebuah jalan spiritual yang seharusnya membebaskan, dan bukan mengurung.
Dalam narasi lintas iman, kita sering menemukan pergulatan batin. Bahwa berdialog dengan yang berbeda tak semudah membalikkan tangan. Ada rasa takut, ada penghakiman, ada pula isolasi dari lingkungan sendiri. Tetapi Prof. Musdah menapaki semua itu dengan langkah kecil yang pasti. Ia tidak bicara toleransi sebagai jargon, tetapi sebagai ruang batin. Ruang untuk menampung yang lain, dan bukan menolak. Ia tak sedang membela label tertentu. Ia sedang menjaga sesuatu yang lebih luhur, yaitu martabat manusia dan keluhuran iman. Setiap perjumpaan dengan yang berbeda, bagi Prof. Musdah adalah latihan untuk benar-benar mencintai dengan tulus.
Agama bukan untuk membangun benteng, tetapi jembatan. Dalam perjalanannya, Prof. Musdah telah membuktikan bahwa keyakinan yang kuat tak berarti menutup diri. Justru sebaliknya, keyakinan yang matang membuka hati, mengajak berdialog, bahkan dengan mereka yang paling berbeda. Ia mengingatkan kita, bahwa iman tanpa cinta hanyalah kerangkeng sunyi. Dan cinta tanpa keberanian tak akan mampu melintasi apa pun.
Dalam konteks tafsir gender, buku ini adalah suluh. Ia mempersoalkan cara tafsir lama dalam membingkai perempuan sebagai pihak kedua, objek, atau bahkan beban. Dalam pengalaman menjadi bagian dari tim perumus hukum Islam yang lebih adil gender, Prof. Musdah menunjukkan bahwa perjuangan membebaskan bukan sekadar tentang hak, tetapi lebih tentang cara berpikir. Tentang membongkar ulang narasi lama yang sudah mapan tetapi tak selalu adil. Ia tidak hanya menawarkan narasi tandingan, tetapi juga menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik, sebagai cara lain dalam memahami nilai-nilai ilahiah itu sendiri.
Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Luce Irigaray (1930), filsuf perempuan asal Belgia, yang mempertanyakan struktur bahasa dan representasi perempuan dalam wacana maskulin. Irigaray menegaskan bahwa perempuan selama ini tidak hanya dibungkam dalam praktik, tetapi juga dalam simbol dan bahasa. Buku ini berbicara dalam kerangka serupa, bahwa untuk membebaskan perempuan, kita tak cukup dengan memberi akses. Kita perlu menata ulang cara kita memaknai tubuh, relasi, bahkan wahyu. Membebaskan perempuan berarti membebaskan cara kita dalam memaknai dunia.
Dalam konteks pemikiran Islam, refleksi ini juga berkaitan dengan warisan gagasan Fatima Mernissi (1940–2015). Dalam banyak karyanya, Mernissi menunjukkan bahwa dominasi patriarki dalam dunia Muslim bukan berasal dari Islam itu sendiri, tetapi dari konstruksi sosial-budaya yang mengklaim berbicara atas nama Islam.
Mernissi membedah bagaimana hadis-hadis yang menyingkirkan perempuan dari ruang publik sering kali berasal dari otoritas yang problematik dan bias gender. Pandangan ini selaras dengan upaya Prof. Musdah yang terus menggugat cara agama digunakan untuk membatasi perempuan. Melalui pendekatan Mernissi, kita diajak melihat bahwa pembebasan perempuan Muslim bukanlah tindakan melawan iman, tetapi justru cara kembali pada esensi spiritual Islam yang lebih adil dan manusiawi.
Prof. Musdah tidak sedang melawan teks, tetapi ingin membebaskan teks dari penjara pembacaan yang sempit. Baginya, Islam adalah energi cinta yang terus bertransformasi, dan bukan doktrin yang membatu. Maka ia dengan tegas menolak logika poligami yang membelenggu, menggugat makna ketaatan yang merendahkan, lalu menyuarakan bahwa perempuan bukan hanya berhak ditafsirkan, tetapi juga menafsir. Di titik ini, buku ini menyingkap bahwa perlawanan yang paling kuat adalah yang dilakukan dalam keheningan, melalui narasi yang memanusiakan.
Apa yang tertulis dalam buku ini tidak lahir dari ruang steril. Ia berasal dari ruang pertemuan, debat, dan kegelisahan yang panjang. Di banyak forum internasional yang didatangi, Prof. Musdah bukan hanya membawa suara perempuan, tetapi juga membawa wajah Islam yang teduh. Ia menjawab keraguan dunia akan Islam dan feminisme bukan dengan teori rumit, tetapi dengan kesaksian hidup, bahwa seorang perempuan bisa taat dan kritis, bisa religius dan bebas, bisa mencintai agama tanpa kehilangan nalar. Dalam dirinya, iman dan rasionalitas berpadu tanpa saling menegasikan.
Narasi ini bukan perlawanan yang bising. Ia tidak menghardik, tetapi memeluk. Kalimat-kalimat yang ditulisnya tak meloncat, melainkan mengalir, mengajak pembaca mengikuti gelombang kecil yang terus menyusup, hingga ke relung batin terdalam. Bahasa dalam buku ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lebih seperti ruang penyembuhan. Ia seperti selimut bagi mereka yang lelah ditolak hanya karena berbeda membaca. Sebuah bentuk kelembutan yang lahir dari keberanian. Sebuah cara berbicara yang tidak mencederai, tetapi juga tidak tunduk pada ketakutan.
Buku ini tidak sekadar bicara Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai pengalaman eksistensial. Ia menyingkap bagaimana iman bukan sekadar akumulasi hafalan, tetapi lebih sebagai pergulatan rasa, refleksi sosial, dan perjalanan batin yang panjang. Iman sebagai keputusan yang lahir dari perjumpaan, dari luka, dari pencarian yang tak selalu mudah. Juga mengajak kita untuk menyelami Islam bukan sebagai sistem hukum semata, tetapi lebih sebagai laku mencintai yang terus tumbuh. Islam sebagai ruang yang memungkinkan perempuan menjadi utuh dalam berpikir, merasa, mencinta, dan menafsir.
Dalam pengertian spiritualitas, buku ini menyentuh akar terdalam dari pencarian manusia, yaitu kerinduan akan Tuhan yang tidak menindas. Spiritualitas yang dihadirkan bukan yang retoris, tetapi yang melembutkan batin. Ia mengingatkan kita pada jalur para pecinta Tuhan, jalan para sufi, yang percaya bahwa makna terdalam dari keberagamaan adalah kehadiran batin yang utuh. Di tengah dunia yang terlalu bising, spiritualitas yang diam bisa menjadi revolusi yang sunyi.
Tentu, tidak semua bagian buku ini sempurna. Ada bagian-bagian yang mungkin terasa terlalu personal atau terlalu padat bagi sebagian pembaca. Beberapa argumen bisa diperkuat dengan pendekatan sistematis. Tetapi justru dalam kekurangan itulah, buku ini menjadi manusiawi. Ia lebih jujur, dan tidak menawarkan kebenaran tunggal, tetapi mengajak pembaca untuk berdialog. Ia tidak menyuguhkan doktrin, tetapi lebih membuka ruang untuk berpikir bersama.
Pada akhirnya, membaca buku ini seperti menempuh perjalanan batin. Kita tidak hanya membaca gagasan, tetapi juga menyelami keberanian. Keberanian seorang perempuan yang tidak ingin mewariskan kepatuhan buta kepada anak-anaknya, tetapi keberanian untuk berpikir, mencinta, dan bertindak atas nama kebenaran. Keberanian untuk mempercayai bahwa cinta adalah energi spiritual yang bisa memulihkan dunia yang kian retak.
Bagi saya, buku ini ibarat undangan. Bukan undangan untuk memberontak, tetapi lebih untuk bertumbuh. Untuk menyeberangi luka, melampaui batas, dan memeluk kemungkinan-kemungkinan yang lebih luhur. Ia menyalakan cahaya kecil di tengah gelapnya wacana keagamaan yang kadang begitu maskulin dan bising. Dan cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Di antara lembarnya, terselip suara perempuan yang selama ini tersembunyi, lirih, tetapi menghunjam.
Dunia kita yang semakin bising hari ini, buku ini menjadi ruang hening yang menyembuhkan. Kita sebagai pembaca, adalah peziarah yang diajak untuk ikut melintasi batas. Bukan hanya geografis, tetapi juga batiniah, spiritual, dan moral. Kita diminta bukan hanya membaca, tetapi menyimak dengan hati, dengan keberanian, dengan kesediaan untuk berubah. Sebuah warisan yang barangkali, lebih suci dari sekadar dogma. Sebuah karya yang mengajarkan kita bahwa melintasi batas bukan hanya tindakan intelektual, tetapi juga spiritual.
Biografi penulis
Sitti Nurliani Khanazahrah, M.Ag. adalah seorang penulis dan juga staf pengajar UIN Alauddin Makassar. Ia juga menjadi Pendiri Rumah Kajian Filsafat Makassar dan juga Pembina Komunitas Literasi Perempuan Makassar. Saat ini, ia aktif menjadi pegiat literasi dan filsafat. Buah kepiawaiannya dalam menulis sudah diterbitkan menjadi beberapa buku, yaitu 1) Subaltern, dan Literasi Urbanitas 2) Mengubah Rasa Menjadi Aksara 3) Model Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Sulawesi Selatan. Tulisan lainnya dapat ditemui di pengembaraanpikiran.blogspot.com