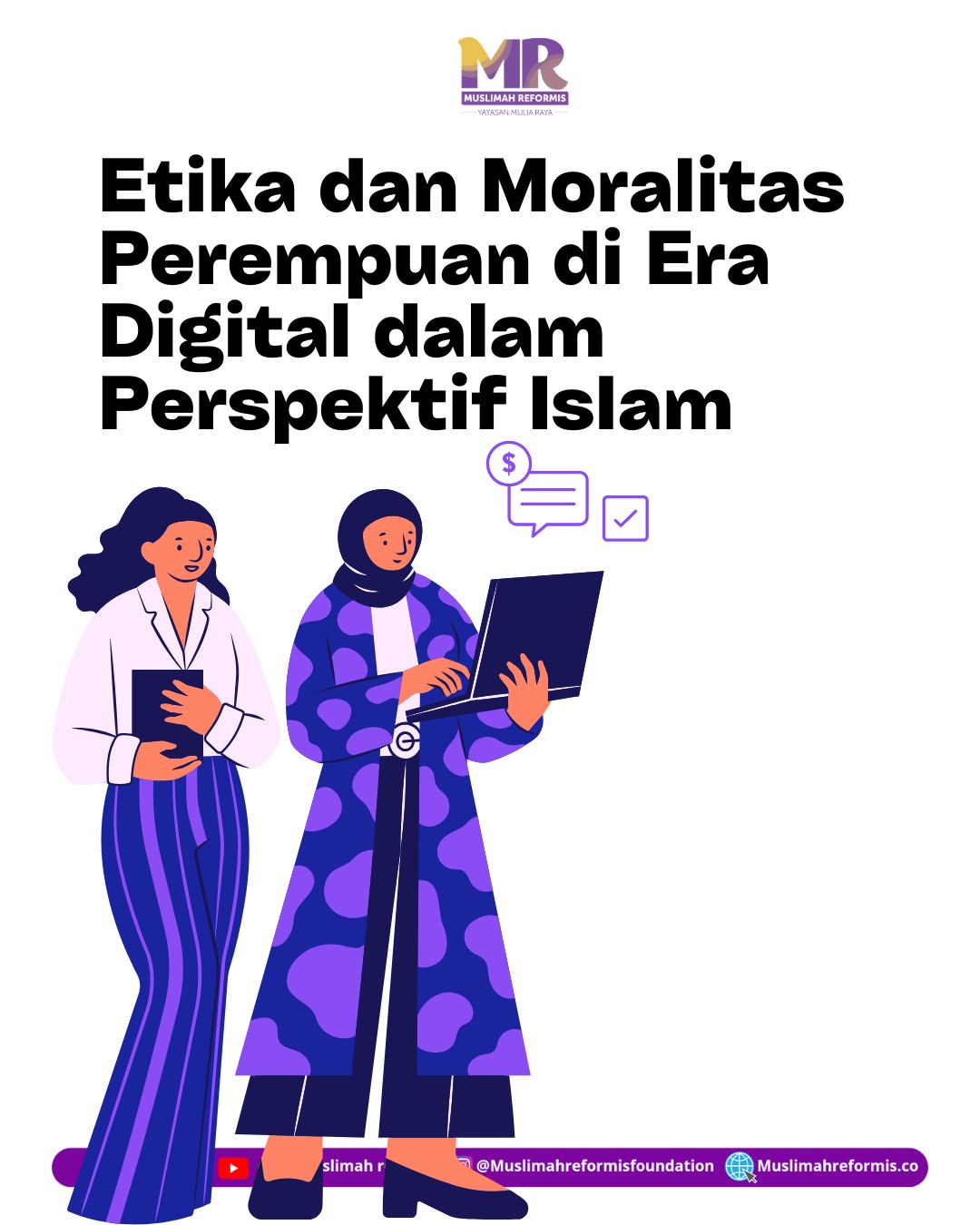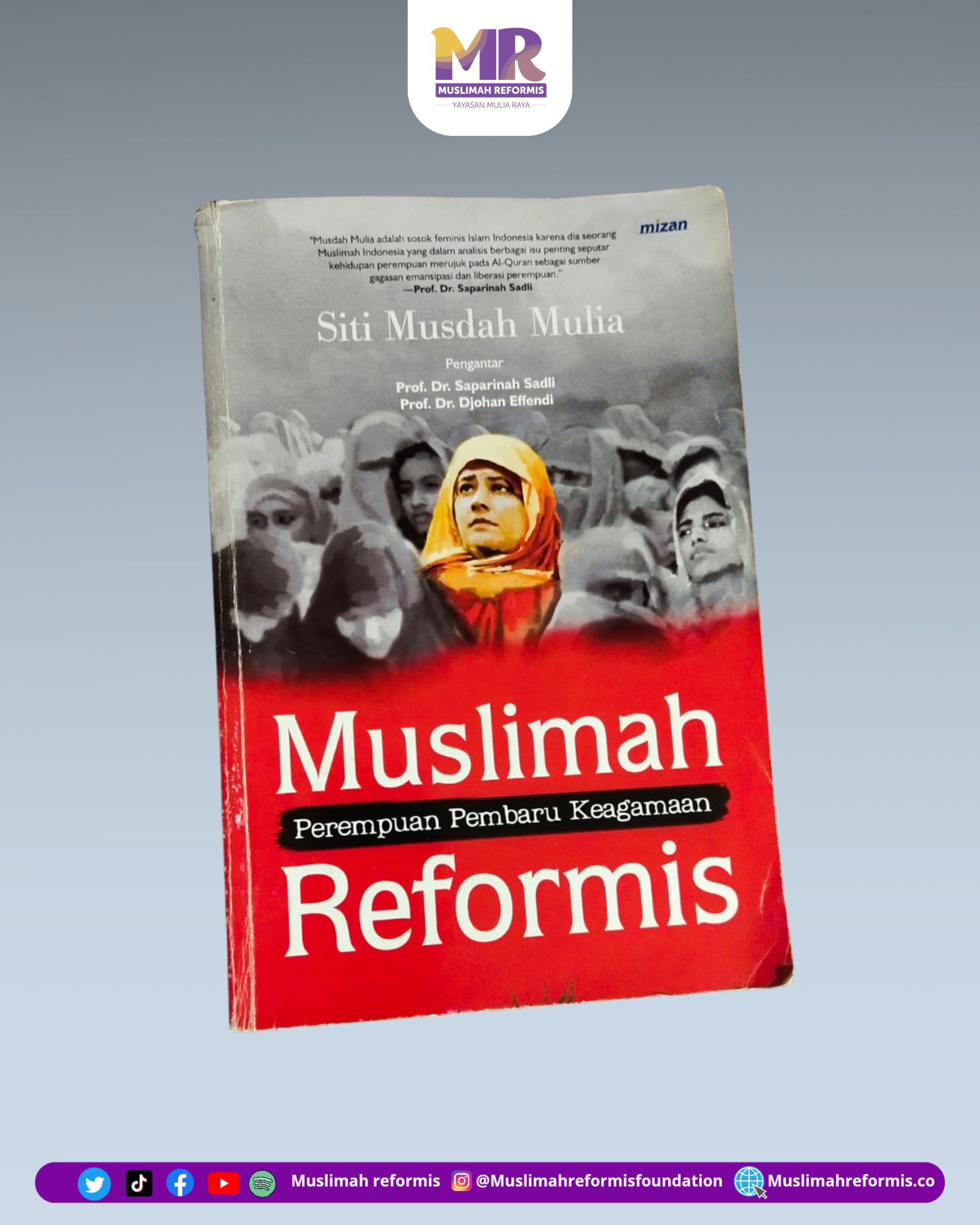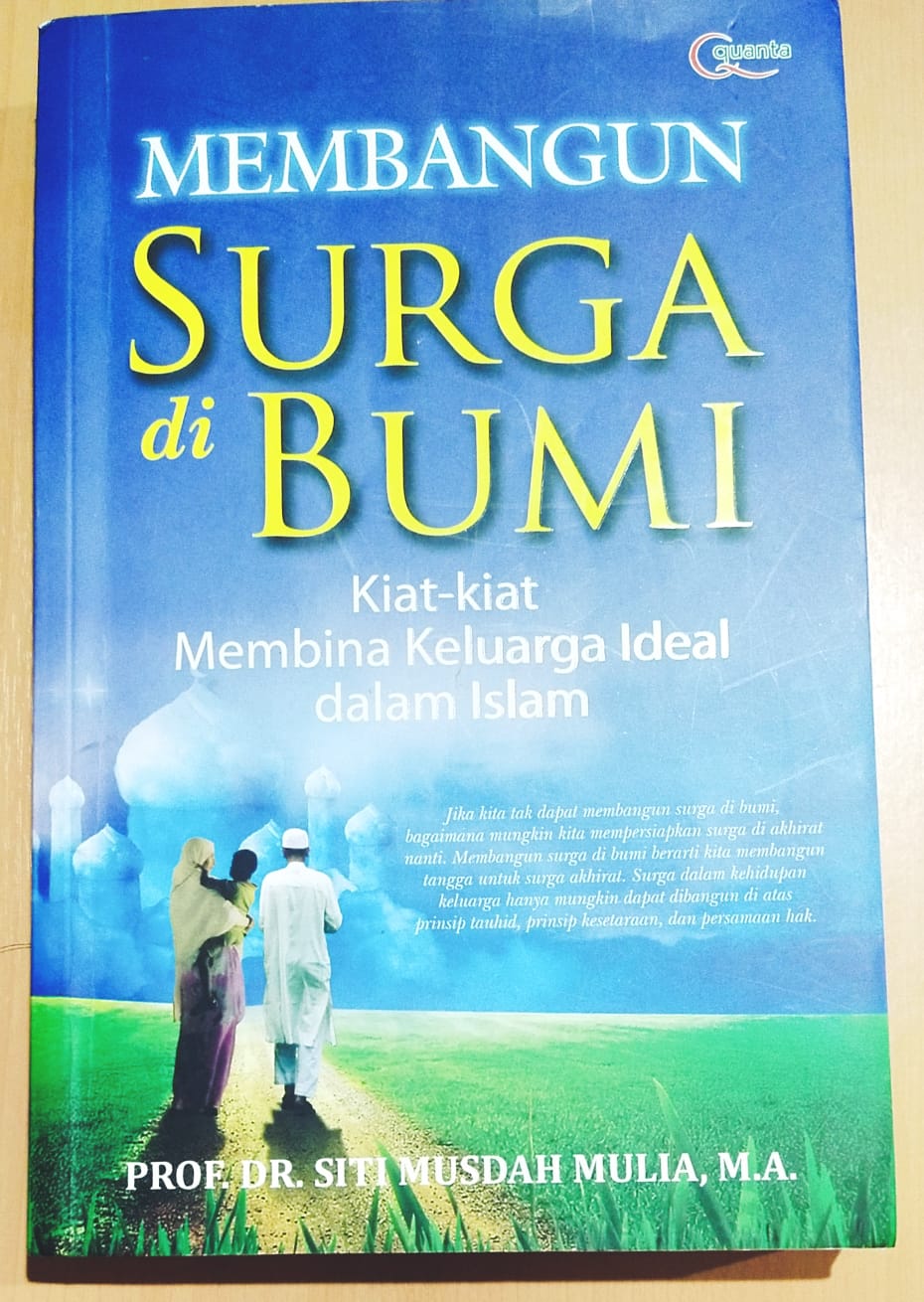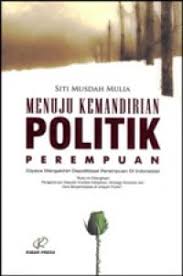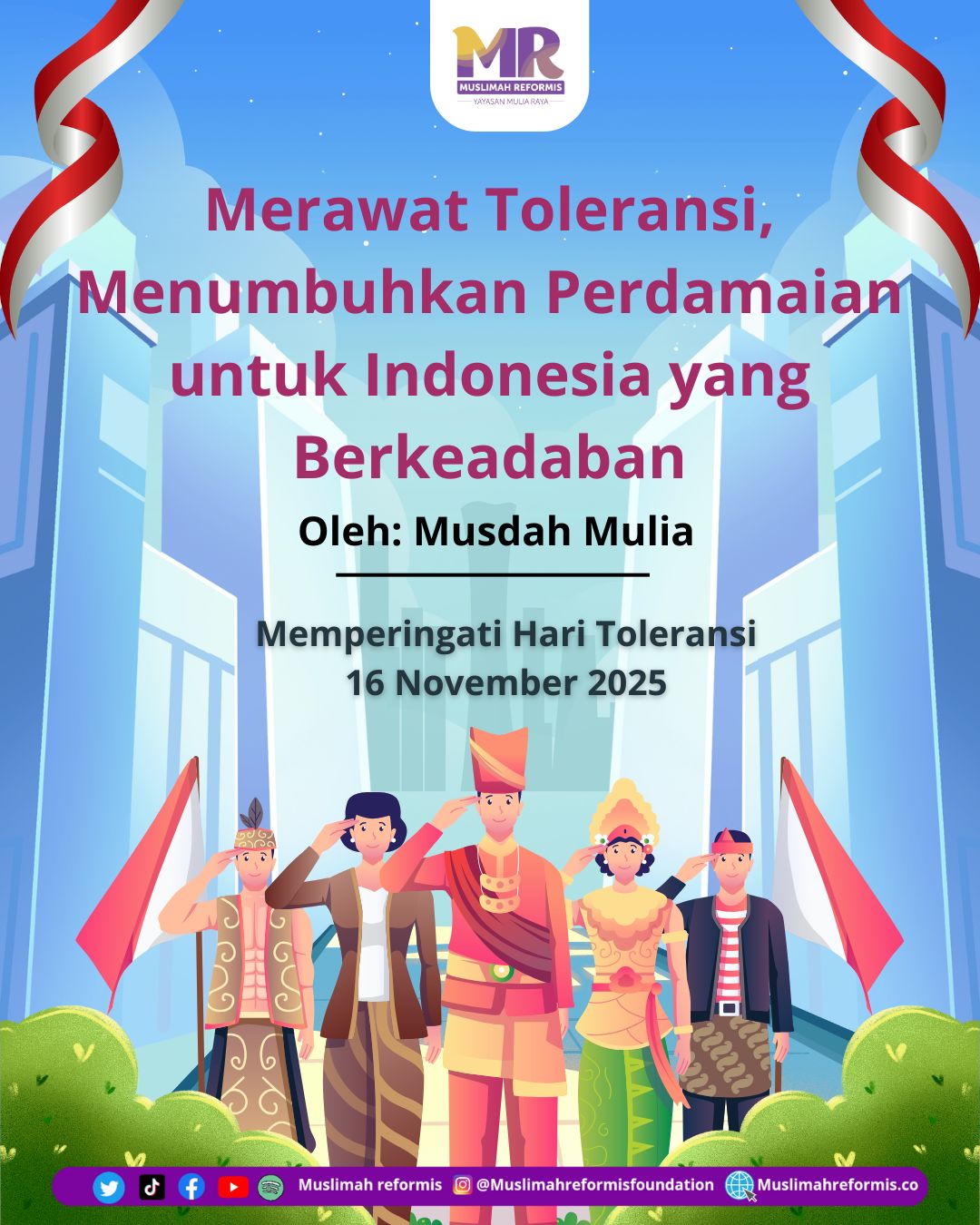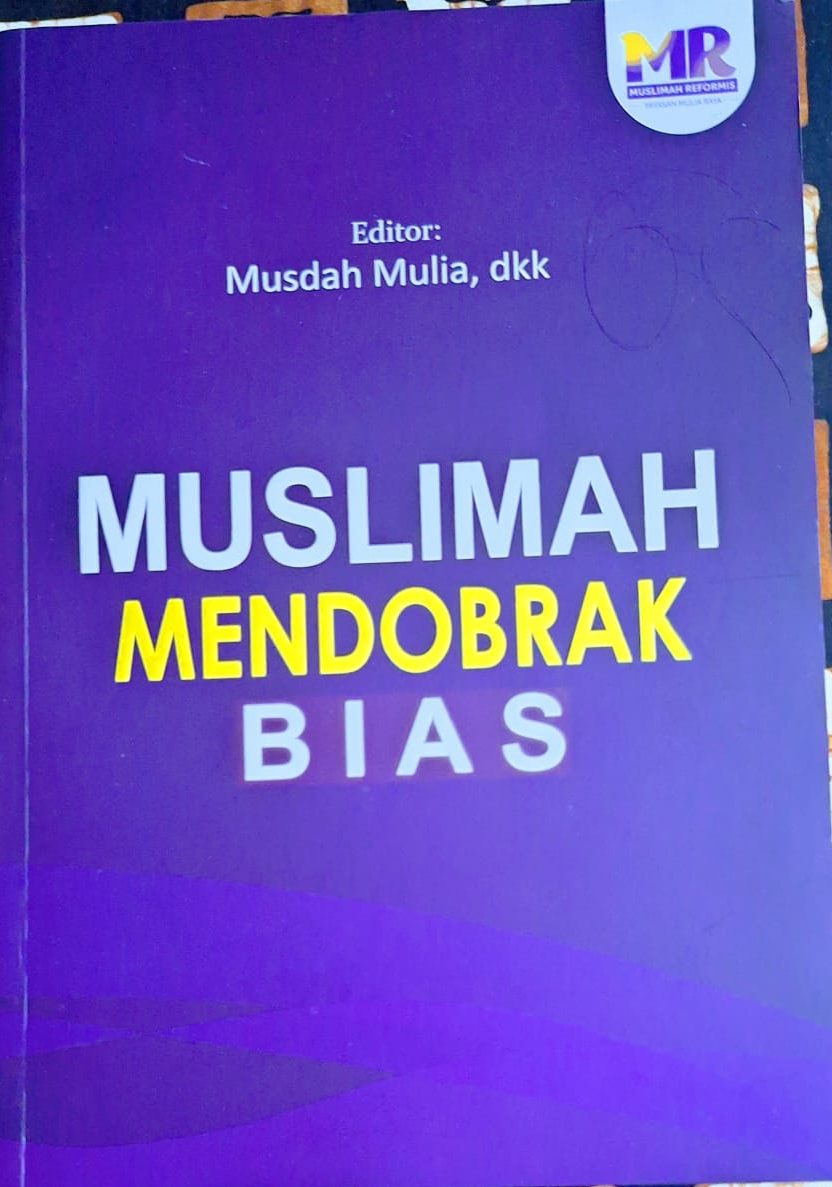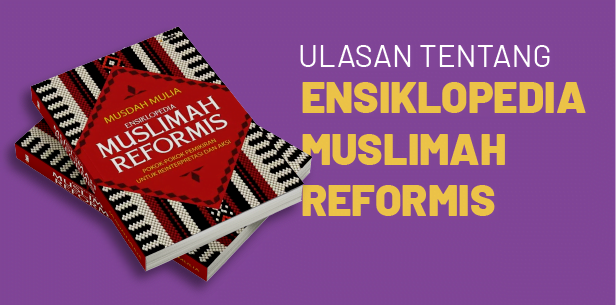Oleh: Musdah Mulia
Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Bagi perempuan, era digital membuka ruang luas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan dakwah. Namun, di sisi lain, dunia digital juga menghadirkan tantangan etis dan moral yang tidak ringan, seperti penyebaran hoaks, budaya konsumtif, eksploitasi tubuh perempuan, dan degradasi nilai kesopanan. Dalam konteks inilah ajaran Islam tentang akhlaq (etika dan moralitas) menjadi sangat relevan untuk dijadikan pedoman hidup.
Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia yang memiliki kehormatan (karamah) dan tanggung jawab moral yang sama dengan laki-laki. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat [49]:13 bahwa kemuliaan manusia di sisi-Nya ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin, status sosial, atau popularitas digital. Ketakwaan di era digital berarti menjaga perilaku online agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab sosial. Dalam hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah saw. menegaskan bahwa “barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam” sebuah prinsip etika komunikasi yang sangat relevan untuk mengontrol ucapan, komentar, dan unggahan di media sosial.
Etika digital dalam Islam menuntut perempuan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana kemaslahatan, bukan pencitraan semata. Moralitas perempuan Muslim hendaknya tercermin dalam cara berpakaian, berinteraksi, dan berpendapat di ruang maya dengan penuh kesadaran spiritual. Islam tidak melarang perempuan tampil aktif di dunia digital, tetapi menekankan prinsip haya’ (malu dalam arti positif), yaitu kesadaran moral untuk tidak menurunkan martabat diri dan orang lain. Dengan demikian, perempuan beretika digital berarti perempuan yang menjunjung nilai ta’dib (pendidikan moral), amanah (tanggung jawab), dan adl (keadilan) dalam setiap aktivitas daringnya.
Selain itu, perempuan Muslim perlu mengembangkan literasi digital spiritual, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi dengan nilai-nilai Qur’ani. Prinsip maslahah (kebaikan bersama) harus menjadi orientasi utama. Konten yang diunggah sebaiknya membawa manfaat, mengedukasi, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan. Dalam perspektif maqasid al-shari‘ah, penggunaan teknologi yang menegakkan nilai hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-din (menjaga iman) menjadi bentuk aktualisasi moralitas Islam di dunia digital.
Dengan demikian, etika dan moralitas perempuan di era digital bukan sekadar soal perilaku pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Islam mendorong perempuan untuk menjadi subjek aktif dalam transformasi digital yang bermartabat, membawa pesan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang di tengah derasnya arus globalisasi nilai. Di tangan perempuan beretika dan beriman, dunia digital dapat menjadi ruang dakwah dan pembebasan, bukan arena degradasi moral.
Kemajuan teknologi digital telah mengubah lanskap sosial dan keagamaan secara radikal. Ruang maya kini menjadi arena baru bagi perempuan Muslim untuk menegosiasikan identitas, peran sosial, serta posisi teologis mereka dalam masyarakat. Namun, di balik peluang yang luas, era digital juga membawa tantangan serius terhadap nilai-nilai etika dan moralitas Islam. Tantangan-tantangan tersebut muncul karena pertemuan antara globalisasi budaya digital yang liberal dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip keseimbangan (tawazun) dan kemaslahatan (maslahah).
Dalam konteks Islam dan etika moralitas perempuan, tantangan perempuan di era digital bersifat multidimensi, mencakup aspek moral, sosial, psikologis, dan bahkan teologis. Adapun tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi perempuan Muslim di tengah arus digitalisasi global adalah:
- Objektifikasi dan Komodifikasi Tubuh Perempuan
Media digital seringkali memperlakukan tubuh perempuan sebagai objek visual yang dikomodifikasi melalui algoritma media sosial dan ekonomi perhatian (attention economy). Fenomena ini melahirkan budaya selfie, body shaming, dan tekanan terhadap standar kecantikan tertentu yang tidak realistis. Dalam Islam, tubuh perempuan bukan objek konsumsi publik, tetapi bagian dari martabat yang harus dijaga (karamah insaniyyah). Selain itu, fenomena ini menciptakan tekanan psikologis dan menormalisasi eksploitasi tubuh sebagai alat pencitraan diri. Dalam perspektif Islam, tubuh perempuan bukan milik publik, melainkan amanah yang harus dijaga. Al-Qur’an menegaskan pentingnya haya’ (rasa malu dalam arti kesadaran moral) sebagai benteng spiritual yang melindungi kehormatan diri (QS. An-Nur [24]:30–31). Musdah Mulia (2019) menegaskan bahwa moralitas Islam harus dimaknai sebagai penghargaan terhadap martabat manusia (karamah insaniyyah), bukan kontrol atas tubuh perempuan.
2. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Fenomena cyberbullying, doxing, dan revenge porn menunjukkan bentuk kekerasan baru yang melanggar prinsip hurmah al-insan (kehormatan manusia). Banyak perempuan menjadi korban penyebaran foto pribadi tanpa izin, fitnah daring, dan pelecehan di media sosial. Fenomena ini tidak hanya melukai secara psikologis tetapi juga mencederai harga diri dan martabat perempuan dan keluarganya. Dalam perspektif Islam, hal ini termasuk perbuatan zulm (kezaliman) dan melanggar prinsip amanah serta hurmah al-insan (kehormatan manusia).
Islam melarang segala bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:12 agar manusia menjauhi prasangka, ghibah, dan pelanggaran etika sosial. Ziba Mir-Hosseini (2015) menyoroti bahwa patriarki digital melanggengkan kekerasan simbolik terhadap perempuan melalui kontrol narasi keagamaan dan sosial yang tidak adil. Karena itu, perlindungan perempuan di ruang digital bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga persoalan moral keagamaan.
3. Krisis Identitas dan Eksistensi Virtual
Media sosial menciptakan budaya pembandingan terus-menerus (comparison culture), yang dapat menimbulkan krisis identitas, kecemasan, dan kehilangan orientasi moral. Dalam Islam, nilai diri seseorang tidak diukur oleh pengakuan sosial, melainkan oleh ketulusan (ikhlas) dan amal saleh. Tantangan ini menuntut pembentukan literasi spiritual digital agar perempuan tetap berakar pada nilai-nilai Qur’ani di tengah godaan popularitas maya.
Budaya digital sering melahirkan krisis identitas bagi perempuan Muslim, karena dunia maya menuntut tampil sempurna dan populer. Media sosial menciptakan ilusi nilai diri yang diukur oleh likes dan followers, bukan oleh integritas moral. Dalam perspektif Islam, nilai diri manusia ditentukan oleh taqwa dan ikhlas (QS. Al-Hujurat [49]:13). Amina Wadud (1999) menekankan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai subjek etis, bukan objek sosial, sehingga perempuan harus menegaskan eksistensinya melalui kontribusi moral, bukan penampilan visual.
4. Beban Ganda: Domestik dan Digital
Era digital juga memperluas beban kerja perempuan. Selain tanggung jawab domestik, perempuan kini dituntut untuk aktif di ruang publik digital. Ketimpangan ini menciptakan kelelahan emosional dan burnout spiritual. Prinsip tawazun dalam Islam (QS. Al-Qashash [28]:77) menuntut keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan spiritual. Oleh karena itu, etika digital Islam harus memampukan perempuan untuk berpartisipasi aktif tanpa kehilangan keseimbangan hidup dan makna ibadah dalam setiap aktivitasnya.
5. Disinformasi dan Krisis Etika Informasi
Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah maraknya disinformasi keagamaan. Banyak konten Islam yang menyebarkan tafsir sempit dan misoginis tanpa dasar ilmiah. Dalam hal ini, ajaran tabayyun (klarifikasi informasi) sebagaimana disebut dalam QS. Al-Hujurat [49]:6 menjadi pedoman penting. Perempuan perlu memperkuat tafaqquh fi al-din (pemahaman mendalam tentang agama) agar tidak mudah dimanipulasi oleh narasi patriarkal yang dibungkus simbol religiusitas.
6. Representasi Perempuan dalam Diskursus Digital Islam
Ruang digital keislaman masih didominasi oleh narasi laki-laki. Perempuan seringkali menjadi objek tafsir, bukan subjek penafsir. Tantangan ini menuntut perempuan Muslim menjadi mufassirah digital yang berani menghadirkan tafsir yang berperspektif keadilan dan kemanusiaan. Menurut Amina Wadud (2006), kehadiran perempuan dalam wacana keagamaan digital adalah langkah penting menuju kesetaraan epistemologis dalam Islam. Di sinilah perempuan tidak hanya menjadi penerima ajaran, tetapi juga penafsir aktif atas teks suci dan realitas sosialnya. Tentu dengan menghadirkan wacana Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan berkeadilan gender.
7. Eksploitasi Spiritualitas Perempuan
Fenomena influencer hijrah dan ustazah selebgram menunjukkan bagaimana spiritualitas perempuan kadang direduksi menjadi komoditas konsumsi. Kesalehan dipamerkan secara visual tanpa kedalaman moral. Seyyed Hossein Nasr (2010) mengingatkan bahwa modernitas digital mengancam spiritualitas manusia karena menekankan citra, bukan substansi. Islam mengajarkan bahwa ikhlas dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) adalah inti dari moralitas sejati, bukan performa religius di ruang maya. Agama direduksi menjadi gaya hidup visual, bukan pengalaman batin yang mendalam. Islam menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, antara simbol dan substansi. Tantangan bagi perempuan Muslim ialah menampilkan spiritualitas yang autentik dan etis, bukan sekadar performatif, atau pencitraan.
Strategi Penguatan Etika dan Moralitas Perempuan di Era Digital
Perubahan sosial yang ditandai oleh ekspansi teknologi digital menuntut respons teologis dan etis yang lebih kreatif. Islam sebagai agama yang shalih likulli zaman wa makan (relevan bagi setiap ruang dan waktu) memiliki potensi besar untuk menuntun manusia agar tidak kehilangan arah moral di tengah percepatan digitalisasi. Penguatan etika dan moralitas perempuan di era digital harus berbasis pada tiga pilar utama: pendidikan moral-spiritual, pemberdayaan epistemologis, dan penguatan struktural-sosial.
1. Pendidikan Moral-Spiritual Berbasis Nilai Qur’ani
Pendidikan merupakan fondasi utama pembentukan etika digital perempuan. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk adab (budi pekerti) dan ta’dib (kesadaran moral). Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa adab akan melahirkan kebingungan moral (Ihya’ Ulum al-Din, 2005). Maka, pendidikan Islam perlu merespons dunia digital dengan menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap aktivitas daring memiliki dimensi pertanggungjawaban di hadapan Allah (muraqabah).
Program pendidikan moral digital dapat dilakukan melalui kurikulum keagamaan yang menekankan literasi etika media, haya’ digital, dan ikhlas digital—yakni kesadaran untuk bertindak jujur, berempati, dan bertanggung jawab di ruang maya. Dalam hal ini, pendidikan perempuan menjadi kunci utama. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw., “Apabila engkau mendidik seorang laki-laki, maka engkau mendidik satu individu; apabila engkau mendidik seorang perempuan, maka engkau mendidik satu bangsa.”
2. Pemberdayaan Epistemologis dan Literasi Digital Spiritual
Musdah Mulia (2019) menegaskan bahwa pembebasan perempuan dalam Islam harus dimulai dari pembebasan epistemologi, yakni kemampuan perempuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi teks-teks keagamaan serta realitas sosialnya. Dalam konteks digital, pemberdayaan epistemologis berarti membekali perempuan dengan literasi digital spiritual, kemampuan membaca informasi, memverifikasi kebenaran (tabayyun), dan menilai konten berdasarkan prinsip maslahah dan adl.
Pendidikan literasi ini perlu dikembangkan oleh lembaga keagamaan, perguruan tinggi Islam, dan organisasi perempuan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama, teknologi informasi, dan etika sosial. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pengetahuan digital yang berperspektif Qur’ani.
Musdah Mulia (2013) menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam menafsirkan teks dan menulis narasi keislaman baru di ruang digital. Keaktifan ini tidak hanya memperluas representasi perempuan, tetapi juga memperkaya wacana Islam yang humanis dan egaliter.
3. Penguatan Struktural dan Sosial
Etika digital tidak dapat ditegakkan hanya melalui kesadaran individu; ia memerlukan dukungan struktural dan kebijakan publik. Negara, ulama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk membangun ekosistem digital yang berkeadilan dan bermartabat.
Pemerintah dapat berperan melalui regulasi perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender online (KBGO), penyediaan ruang digital aman, serta pelatihan literasi digital berbasis nilai agama dan kemanusiaan. Dalam hal ini, prinsip maqasid al-shari‘ah, terutama hifz al-‘ird (menjaga kehormatan) dan hifz al-nafs (menjaga keselamatan), dapat dijadikan kerangka etis dalam penyusunan kebijakan publik di bidang teknologi dan informasi (Auda, 2008).
Selain negara, lembaga keagamaan dan komunitas perempuan juga perlu menghidupkan tradisi amar ma‘ruf nahi munkar di dunia maya dengan cara-cara dialogis, edukatif, dan penuh kasih sayang. Dakwah digital harus diarahkan untuk membangun maslahah ‘ammah (kebaikan bersama), bukan memperkuat polarisasi sosial atau moral panic.
4. Sinergi Peran Ulama dan Influencer Muslimah
Ulama dan tokoh perempuan Muslim di ruang digital perlu berkolaborasi untuk membangun etika publik Islam yang relevan dengan generasi muda. Kehadiran influencer Muslimah dapat menjadi kekuatan moral apabila mereka menampilkan spiritualitas yang autentik, bukan semata pencitraan. Seyyed Hossein Nasr (2010) mengingatkan bahwa tantangan terbesar modernitas adalah kehilangan dimensi sakral dalam kehidupan manusia. Para tokoh Muslimah perlu meneguhkan kembali makna kesalehan sebagai proses tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa), bukan performa sosial.
5. Rekonstruksi Teologi Rahmatan lil ‘Alamin untuk Dunia Digital
Akhirnya, seluruh strategi di atas harus berakar pada teologi Islam yang berwawasan rahmah dan keadilan. Islam memandang teknologi bukan ancaman, tetapi amanah. Etika digital perempuan Muslim harus diarahkan pada misi kemanusiaan: menebar kasih sayang (rahmah), menegakkan keadilan (adl), dan mengupayakan kemaslahatan (maslahah).
Menurut Musdah Mulia (2013) pembaruan Islam harus berangkat dari nilai-nilai moral universal Qur’an dan diterjemahkan ke dalam konteks sosial yang baru. Untuk itu, penguatan moralitas perempuan di era digital bukan nostalgia terhadap masa lalu, melainkan aktualisasi nilai Qur’ani di ruang teknologi modern.
Refleksi Penutup
Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa moralitas perempuan Muslim di era digital tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural, epistemologis, dan spiritual. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menuntut integrasi antara etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap penggunaan teknologi. Dengan memperkuat literasi digital spiritual, perempuan dapat menjadi agen moral dan pembaharu sosial yang mengarahkan peradaban digital menuju nilai-nilai adl, rahmah, dan maslahah
Semua tantangan di atas menuntut etika digital Islam yang berakar pada nilai maslahah, adl, dan rahmah. Perempuan perlu membangun kesadaran kritis dan spiritual untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengarah moral peradaban digital. Dalam bahasa Fazlur Rahman (1982), modernitas harus diisi dengan “etika Qur’ani” agar kemajuan teknologi tidak menghapus nilai kemanusiaan.
Perempuan Muslim di era digital memikul peran ganda: sebagai penerus nilai-nilai spiritual Islam dan sebagai pelaku transformasi sosial yang kritis. Ketika perempuan mampu memadukan iman dan ilmu, spiritualitas dan teknologi, maka dunia digital akan menjadi ruang ibadah baru, tempat menebar nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang yang sejati.
Kemajuan perempuan Muslim di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kualitas iman, pengetahuan, dan kebijakan sosial. Islam menyediakan fondasi teologis yang kuat untuk membangun keseimbangan antara kemajuan dan moralitas.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ra’d [13]:11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”
Ayat ini mengandung pesan bahwa kemajuan digital harus beriringan dengan reformasi moral dan spiritual agar benar-benar menghasilkan peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban.
Referensi Pendukung
- Al-Qur’an al-Karim.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). Ihya’ Ulum al-Din.Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amina Wadud. (1999). Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective.Oxford University Press.
- Amina Wadud. (2006). Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam.Oxford: Oneworld.
- Fazlur Rahman. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.Chicago: University of Chicago Press.
- Jasser Auda. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.London: IIIT.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2015). Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition.London: Oneworld.
- Musdah Mulia. (2013). Muslimah Sejati, Bandung: Penerbit Marja’
- Musdah Mulia. (2019). Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi.Jakarta: Dian Rakyat.
- Seyyed Hossein Nasr. (2010). Islam in the Modern World.New York: HarperOne.