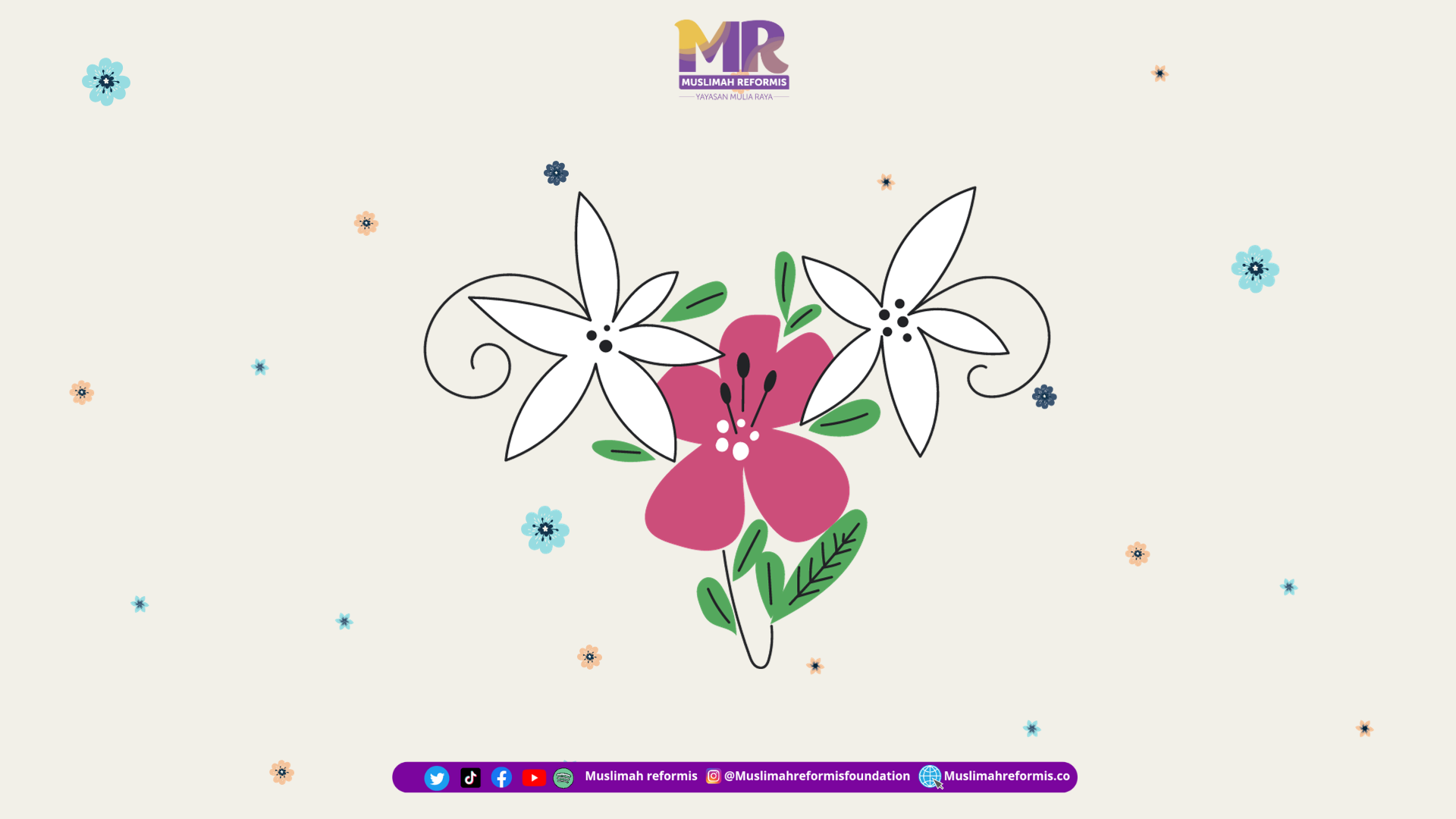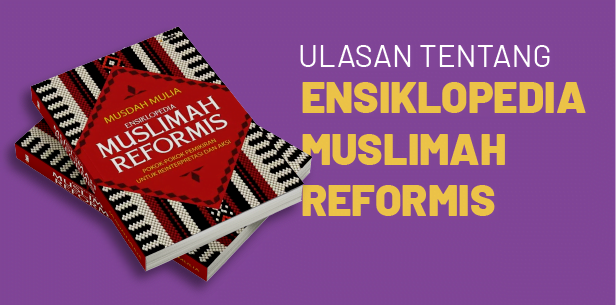Makna Halal Bihalal
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan kegiatan halal bi halal adalah berkumpulnya sejumlah orang pada suatu tempat tertentu yang diadakan setelah hari lebaran untuk saling bersalaman sebagai ungkapan maaf-memaafkan. Menarik dicatat, tradisi halal bi halal hanya dijumpai di Indonesia. Karena itu, kegiatan ini tidak dikenal di negara-negara Islam lainnya, bahkan di Arab Saudi tempat asal agama Islam. Walaupun tidak dilakukan di lingkungan masyarakat Muslim lain, namun tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya ajaran mengenai perlunya mempererat hubungan silaturahim dan saling memaafkan antarsesama manusia (Q.S an-Nur, 24:22, al-Baqarah, 2:237, dan al-Maidah, 5:13).
Sulit memastikan kapan tradisi ini muncul, tetapi yang jelas tradisi ini mulai dilembagakan di tanah air dalam bentuk upacara sekitar tahun 1940-an dan mulai berkembang luas setelah 1950-an. Kini penyelenggaraan halal bi halal dijumpai pada seluruh lapisan masyarakat Muslim, baik di lingkungan instansi negara maupun swasta, serta di lingkungan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.
Secara linguistik halal bi halal adalah kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata halal dan diantarai oleh sebuah kata penghubung. Kata halal berasal dari akar kata halla atau halala yang mengandung beberapa pengertian. Di antaranya dapat berarti ‘melepaskan ikatan’, ‘mengurai benang kusut’, ‘mencairkan kebekuan’, dan ‘menyelesaikan masalah’. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu benang merah yang merupakan esensi halal bi halal, yaitu aktivitas yang dilakukan setelah puasa Ramadhan dan setelah shalat Iedul Fitri untuk lebih mempererat hubungan silaturahim di antara sesama sehingga tidak ada lagi belenggu yang mengganggu, tidak ada lagi kebekuan dan masalah yang merintangi hubungan dan komunikasi di antara sesama.
Hakikat ‘Idulfitri
Ucapan paling populer terdengar saat `Idul Fitri dan hari-hari berikutnya adalah minal `aidin wa al-faizin kemudian disambung dengan ucapan mohon maaf lahir batin. Bagi mereka yang awam sering keliru mengartikan minal `aidin wa al-faizin dengan “mohon maaf lahir batin”. Ungkapan itu sesungguhnya merupakan penggalan dari sebuah do`a yang selengkapnya berbunyi: ja`alana llahu wa iyyakum minal `aidin wa al-faizin (Semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan).
Dari do`a tersebut ada dua konsep yang perlu dijelaskan, yakni konsep al-`aidin (orang-orang yang kembali) dan al-faizin (orang-orang yang memperoleh kemenangan). Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan ?
Pertama, konsep al-`aidin. Hari raya yang dilakukan setelah puasa Ramadhan dinamakan `Idul Fitri. Kata `id terambil dari akar kata yang bermakna “kembali” sedangkan fithr dapat berarti asal kejadian, agama yang benar, atau kesucian. Dengan demikian, `Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah. Al-`aidin adalah bentuk pelaku `id, artinya orang-orang yang kembali. Lengkapnya, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Mengapa manusia selalu diingatkan untuk kembali kepada fitrahnya atau kesucian atau kepada asal kejadiannya?
Islam mengajarkan bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Fitrah adalah suatu kesadaran mendalam akan keesaan Tuhan (tauhid) yang tertanam dalam hati tiap manusia. Fitrah inilah yang membuat manusia memiliki kecenderungan alamiah mencari kebenaran dan kebaikan sehingga manusia disebut makhluk hanif (lurus). Kesucian asal itu bersemayam dalam nurani (artinya: ‘bersifat terang’) yang merupakan pusat kedirian manusia. Karena pertimbangan fitrah kehanifan dan nuraninya itulah manusia dianggap paling pantas menjadi khalifah Tuhan di bumi.
Sejak awal, manusia telah mengakui keesaan Tuhan melalui suatu perjanjian primordial sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur`an: ‘Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan (untuk membela diri): “Kami tidak mengetahui hal itu”, atau agar kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu sedang kami hanya mengikuti perbuatan mereka”. Apakah Engkau akau menyiksa kami lantaran perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” (al-A`raf, 7:172-173)
Dengan pengakuan ini manusia meyakini bahwa hanya Tuhan lah yang menjadi tumpuan hidupnya. Tidak ada tuhan-tuhan lain yang akan menjadi sembahannya, kecuali Allah swt. Dalam realitas sehari-hari kita menyaksikan betapa banyak tuhan-tuhan baru yang menjadi sembahan manusia, di antaranya berupa uang, harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, partai politik, organisasi, serta dalam bentuk berbagai ideologi. Bahkan, tidak sedikit yang mempertuhankan agama.
Ditemukan cukup banyak ayat yang menegaskan bahwa dalam hati nurani manusia telah dituliskan perjanjian suci tersebut. Tugas para Nabi, termasuk Nabi Muhammad saw. hanyalah mengingatkan kembali akan perjanjian suci tadi. Idealnya, setiap individu harus selalu mendengarkan hati nuraninya dan mengingat perjanjian primordialnya dengan Tuhan. Setiap bentuk penyimpangan dari perjanjian ini merupakan dosa, karena itu manusia perlu bertobat. Bertobat artinya kembali, yakni kembali kepada kesucian. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat penyimpangan, melainkan manusia yang setiap kali menyimpang lalu sadar dan segera kembali bertobat sambil bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut (QS. Ali Imran, 3:135).
Kedua, konsep al-fa`izin. Kata ini merupakan bentuk plural dari al-faiz yang berarti seseorang yang memperoleh kemenangan. Kata ini dalam Al-Qur`an terulang sebanyak 29 kali dan pada umumnya menunjuk kepada pengertian pengampunan ilahi dan kenikmatan surgawi (QS. al-Hasyr, 59:20, dan Ali-Imran, 3:185). Jadi, standar yang digunakan untuk menilai keberuntungan dan kemenangan seseorang adalah pengampunan ilahi dan kenikmatan surgawi.
Barangkali gambaran al-`aidin wa al-faizin itu seperti yang dilukiskan Ibnu Sina, filosof Islam terkemuka (w. 1037 di Iran) dalam bukunya Al-Isyarat wa al-Tanbihat sebagai berikut. “Orang yang sangat arif, bebas dari ikatan raganya. Dalam dirinya tersimpan sesuatu yang tersembunyi yang hanya dia yang tahu. Dia selalu gembira dan penuh senyum karena hatinya penuh diliputi cinta kepada-Nya. Semua makhluk dilihatnya sama karena yakin bahwa hanya Allah yang Mahasuci, selain-Nya hanya makhluk Allah. Semua wajar mendapatkan rahmat, baik yang taat maupun yang bergelimang dosa. Dia tidak akan pernah mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain. Dia tidak pernah marah atau tersinggung meskipun menghadapi hal-hal yang mungkar karena jiwanya selalu diliputi rahmat dan kasih sayang. Dia melihat rahasia Allah terbentang di dalam qudrat-Nya. Jika mengajak kepada kebaikan, ia melakukannya dengan penuh kelembutan, jauh dari kekerasan. Dia sangat dermawan karena hatinya tidak terpaut lagi pada hal-hal yang bersifat kebendaan. Dia sangat pemaaf karena hatinya penuh diliputi cinta sehingga tiada tersisa ruang untuk menaruh kebencian. Dia pun tidak pendendam karena seluruh ingatannya hanya tertuju kepada Yang Mahasuci dan Mahaagung”.
Perlunya Mensucikan Jiwa
Islam secara tegas mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya suci. Hanya saja dalam perjalanan hidupnya manusia tercemar oleh berbagai dosa. Pencemaran terjadi karena dalam diri manusia ada tendensi untuk mengikuti hawa nafsu yang irasional yang senantiasa membujuknya berpaling dari fitrah kesucian. Hawa nafsu merupakan pangkal dari semua penyakit dalam kehidupan manusia, yaitu sombong, arogan, dengki, iri hati, cinta kedudukan, cinta harta, zina dan semua bentuk kekejian lainnya.
Hawa nafsu pada dasarnya adalah kecenderungan jiwa yang salah. Allah swt. berfirman: “Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini (QS. al-Mukminun, 23:71). Di kalangan sufi dikenal ungkapan: “musuh manusia yang paling berbahaya adalah nafsunya sendiri”. Ketika usai perang Badr yang terkenal sangat dahsyat itu, Nabi saw. berkata kepada para sahabatnya: “kita baru saja selesai dengan perang yang kecil menuju perang yang lebih besar”, para sahabat terperanjat dan bertanya perang apakah gerangan yang lebih dahsyat dari ini, Nabi menjawab perang melawan hawa nafsu”.
Sekalipun telah dianugerahi fitrah yang hanif, manusia tetap merupakan makhluk lemah. Kelemahan utamanya terletak pada dua sifat yang menonjol, yakni kepicikan atau sempit pikiran (al-dha`f) dan kekikiran (al-qatr). Hampir semua bentuk kesalahan, kekhilafan, dan dosa yang diperbuat manusia timbul akibat dua sifat tersebut (QS. al-Ma`rij 70:19-21, an-Nisa`, 4:128, al-Hasyr, 59:9, at-Taghabun, 64:16, al-Isra`, 17:100).
Karena kepicikan dan kekikirannya itu manusia mudah tergoda oleh daya tarik jangka pendek suatu perbuatan sambil melupakan akibat jangka panjangnya yang seringkali merugikan dan membahayakan. Manusia cenderung sulit menahan diri dari godaan dosa dan zulm (kegelapan) sehingga menjadi pelaku dosa dan dirinya diliputi kegelapan. Makin parah manusia bergelimang dosa makin gelaplah hatinya dan pada akhirnya hati itu akan berubah dari nurani (terang benderang) menjadi zulmani (gelap gulita).
Kedua sifat buruk itulah yang menjadikan manusia mempunyai sifat tergesa-gesa (tidak sabaran), mudah panik, dan tidak suka merenungkan akibat jangka panjang dari semua tindakannya (QS. al-Anbiya`, 21:37, al-Isra`, 17:11, al-Qiyamah, 75:20-21, al-Baqarah, 2:10, dan al-Muzammil, 73:20). Sifat tergesa-gesa membawa kepada sifat sombong dan arogan, serta mudah putus asa atau frustrasi. Tidak ada makhluk lain yang demikian mudahnya menjadi arogan dan frustrasi seperti halnya manusia. Al-Qur`an berulang kali menandaskan kedua sifat tercela ini, yakni jika memperoleh rahmat dari Tuhan manusia lalu bersikap sombong dan arogan, seolah-olah rahmat itu datang karena ikhtiarnya semata. Sebaliknya jika rahmat Tuhan itu ditarik kembali dari dirinya merekapun menjadi putus asa dan kecewa, seolah-olah Tuhan tidak pernah menganugerahinya rahmat (QS. al-Fussilat, 41:49-51, dan al-Isra` 17:83, 10:12).
Fatalnya, sifat tercela itu juga mempengaruhi pola ibadah manusia, tidak sedikit manusia yang mengharapkan bahwa setelah melakukan sejumlah ibadah tertentu, misalnya setelah menunaikan puasa sejumlah beberapa hari, ia segera mendapatkan rahmat Tuhan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya material, seperti naik pangkat, usahanya berhasil, sekolahnya lulus. Sangat keliru menilai rahmat Tuhan hanya dalam bentuk keberhasilan jangka pendek seperti itu. Mungkin Tuhan pun akan berkata: kalau demikian cara kalian mempertuhankan Aku, silakan cari Tuhan lain, Aku tidak sudi menjadi Tuhan kalian. Aku tidak suka didikte untuk memenuhi keinginan-keinginan jangka pendek kalian.
Ibadah seharusnya dilakukan dengan perasaan tulus-ikhlas, tanpa ada pamrih apa pun. Rabiah al-`Adawiyah, sufi perempuan terkemuka (w. 801 H di Bagdad) mencontohkan sikap yang demikian dengan kata-katanya: “Tuhanku jika aku mnyembahMu hanya lantaran menginginkan surga-Mu, jauhkanlah surga itu dariku, sebaliknya jika aku menyembah-Mu lantaran takut kepada neraka-Mu, campakkanlah aku ke neraka-Mu, sebab aku ingin menyembah-Mu tanpa pamrih sedikit pun”.
Dengan bersikap ikhlas dan tanpa pamrih melepaskan seseorang dari perasaan arogan dan merasa sok suci. Jangan pernah menilai ibadah yang dilakukan, sebab yang berhak menilainya hanya Allah swt. Sebagai ilustrasi dapat dinukilkan kisah berikut. Ada seorang alim yang tinggal di depan rumah seorang perempuan pelacur. Setiap kali orang alim itu memandang ke rumah perempuan hina tadi ia memandangnya dengan penuh rasa jijik sambil di benaknya membayangkan kelakuan keji yang dilakukan perempuan itu, demikianlah selalu yang bermain dalam benaknya manakala ia memandang ke rumah perempuan lacur itu. Sebaliknya, sang perempuan setiap kali memandang ke rumah sang alim, hatinya selalu diliputi rasa kagum dan bangga serta takjub akan kesucian dan kemuliaan sang alim sambil merintih kepada Allah karena menyadari betapa kotor dan celaka dirinya. Konon kemudian di akhirat sang alim ditempatkan Tuhan di neraka sementara sang perempuan di surga. Sang protes kepada Tuhan bagaimana mungkin perempuan kotor itu masuk surga, malaikat menjelaskan: betul ia perempuan laknat, tapi hatinya selalu berpikir positif terhadap makhluk Tuhan, sedangkan dirinya yang alim itu selalu berpikiran negatif. Surga dan neraka adalah milik Tuhan tak satupun makhluk yang dapat mempengaruhi keputusan Tuhan dalam hal ini.
Untuk mengeliminir sifat-sifat tercela tadi Al-Qur`an memberikan terapi yang sangat efektif seperti diuraikan dalam surah al-Ma`arij ayat 21-34, yaitu mengerjakan shalat secara khusyuk dan konsisten; menafkahkan sebagian harta kepada orang-orang miskin, baik diminta atau tidak; meyakini adanya hari pembalasan dan takut akan azab Tuhan; menghindari segala bentuk hubungan seksual yang menyimpang; menjaga amanah dan menepati janji; dan memberikan kesaksian yang benar.
Semua ibadah yang diperintahkan Allah pada hakikatnya bertujuan melatih jiwa manusia untuk mengekang dan mengendalikan hawa nafsu. Puasa, misalnya merupakan media pensucian ruhani sebagai latihan mengendalikan diri dari berbagai godaan hawa nafsu sehingga menjadi manusia yang bertaqwa, yaitu manusia yang menang dalam perjuangan menghadapi segala macam godaan. Penyucian jiwa melalui puasa tidak terbatas pada aspek pengekangan diri terhadap kebutuhan fisik material belaka (makan, minum, dan hubungan seksual), melainkan mencakup juga sikap positif yang ditandai dengan sikap syukur kepada-Nya. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur`an menegaskan bahwa puasa yang produktif adalah puasa yang mampu mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa dan bersyukur.
Puasa membimbing manusia untuk kembali kepada fitrahnya, asal kejadiannya. Itulah sebabnya setelah usai berpuasa selama bulan Ramadhan umat Islam ber`idul fitri atau kembali ke fitrahnya. Diharapkan pada `Idul fitri ini setiap individu berhasil tampil kembali sebagai manusia suci seperti sediakala ketika ia dilahirkan, dan selanjutnya diharapkan ia dapat terus-menerus menyadari bahwa kesucian adalah pembawaan alami dirinya yang harus dipertahankan dengan ucapan, sikap, dan perilaku yang suci.
Mengapa Harus Saling Memaafkan?
“Mohon maaf lahir batin”. Apa makna ucapan seperti itu bagi seseorang? Pra ahli psikologi agama menyebutkan bahwa ucapan maaf itu besar maknanya, yakni sebagai langkah awal untuk menyatakan penyesalan. Itulah tindakan yang paling sederhana untuk menunjukkan sikap penyesalan seseorang terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Namun, yang lebih berarti bagi seseorang yang melakukan kesalahan adalah bahwa penyesalan yang diucapkan itu sungguh-sungguh merupakan refleksi batin dan sebagai komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan lagi.
Al-Qur`an mengajarkan tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang Muslim yang bertakwa berkenaan dengan orang yang berbuat kesalahan terhadapnya, yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik kepadanya (QS. al-Maidah, 5:134). Bahkan, sekalipun orang lain bersumpah untuk tidak berbuat baik kepadanya, ia pun tetap dianjurkan untuk memaafkan dan menghapuskan kesalahannya (QS. an-Nur, :22).
Ber`idul fitri pada hakikatnya bermakna merayakan kembalinya sifat kemanusiaan manusia yang setinggi-tingginya. Manusia hendaknya diliputi rasa cinta kasih dan kemurahan hati yang disertai dengan kemampuan menahan marah serta keinginan tulus untuk meminta maaf dan memaafkan sesama. Sikap-sikap terpuji inilah yang sesungguhnya merupakan wujud nyata dari fitrah manusia yang dituliskan Allah dalam diri manusia pada awal penciptaannya (QS. ar-Rum, 30:30).
Kesadaran akan fitrah manusia dan kenyataan bahwa dalam realitas tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan membawa kepada kesadaran baru akan perlunya meminta maaf kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua dan kerabat dekat, akan berbagai dosa dan kesalahan, baik tidak disengaja terlebih lagi yang disengaja, selama berinteraksi dengan mereka. Bukan hanya meminta maaf, tetapi juga memberi maaf kepada sesama tidak kalah pentingnya. Sebesar apapun kesalahan orang lain tidak perlu dihitung karena pasti Allah lebih tahu akan hal itu, berilah maaf dan tunjukkan sikap yang lebih baik kepadanya.
Dalam interaksi antar-sesama manusia sulit dihindarkan adanya saling benturan kepentingan, salah faham, dan salah persepsi. Namun kenyataan ini tidaklah membuat manusia mudah melupakan kesalahan orang lain atau meminta maaf kepada orang lain. Orang umumnya lebih suka membayar ganti rugi atau membayar sanksi daripada harus meminta maaf sebab meminta maaf diidentikkan dengan kehilangan harga diri atau kehilangan muka.
Untuk menghapus keengganan meminta maaf dan memaafkan sesama perlu direnungkan sifat-sifat Tuhan yang baik (al-asma`ul husna). Di antara 99 al-asma`ul husna empat yang berkaitan dengan sifat pemaaf, yakni sifat-sifat al-Ghaffar, al-Ghafur, al-Thawwab, dan al-Afwu. Sebagai al-Ghaffar, Allah senantiasa berjanji menutupi kesalahan dan dosa orang-orang yang bertaubat, bahkan kesalahannya akan ditukar dengan kebajikan (QS. al-Furqan, 25:70). Allah swt. menyambut permohonan tulus hamba-hamba-Nya yang berdosa, betapapun besar dan banyak dosanya selama yang bersangkutan tidak mempersekutukan Allah (QS. al-Furqan, 25:70). Allah swt. memerintahkan manusia agar meneladani-Nya dalam memberi maaf dan ampunan (Q.S. al-Jatsiyah, 45:15), bahkan ditegaskan bahwa: “siapa yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain maka hal demikian termasuk sifat utama” (asy-Syura`, 42:43). Ampunan Tuhan tak terbatas dan tak ternilai oleh apapun. Hanya satu syarat yang digariskan, yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Mari kita renungkan bunyi suatu hadis qudsi sebagai berikut: “Hamba-Ku, seandainya kalian datang kepada-Ku dengan membawa sepenuh isi bumi dosa, Aku pasti menyambut kalian dengan sepenuh bumi ampunan, asalkan kalian tidak mempersekutukan Aku” (HR Tarmizi dari Anas ibn Malik).
Menarik diketahui bahwa tidak dijumpai dalam Al-Qur`an perintah untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Ayat-ayat yang banyak ditemukan justru berisi perintah untuk memberi maaf atau menjadi pemaaf. Tentu saja ketiadaan perintah ini tidak berarti seseorang yang bersalah tidak harus meminta maaf, bahkan sebaliknya ia wajib meminta maaf. Tiadanya ayat yang mengandung perintah memohon maaf agaknya merupakan tuntunan bagi manusia agar memiliki sikap luhur untuk selalu bersedia memaafkan kesalahan orang lain, tanpa menunggu yang bersangkutan memohon maaf terlebih dahulu. Berilah maaf sebelum yang bersangkutan meminta maaf. Dengan demikian maaf yang diberikan itu tidak terkesan terpaksa karena memenuhi permintaan dari yang bersangkutan. Slogan “tiada maaf bagimu” jangan pernah ada dalam kamus kehidupan kita. Sikap saling maaf dan memaafkan inilah sesungguhnya yang menjadi fondasi bagi pemulihan dan penguatan hubungan silaturahim di antara sesama manusia.
Penutup
Sebelum menutup, perkenankan saya membacakan firman Allah swt. yang berbunyi: (“Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya” QS. al-Syams, 91:9-10).
Sebagai konklusi dapat disimpulkan bahwa halal bi halal bukan saja menuntut seseorang agar memaafkan orang lain, melainkan lebih dari pada itu, yakni agar setiap orang berbuat yang terbaik kepada siapa pun. Itulah landasan filosofis dari halal bi halal. Dengan demikian, esensi halal bi halal tidak terhenti hanya sesudah lebaran, tetapi hendaknya berlangsung sepanjang masa.
Untuk itu, marilah kita pada halal bi halal ini membuat komitmen baru pada diri kita masing-masing bahwa sepanjang tahun ini jiwa kita tetap bersih dan selalu berada dalam koridor fitrahnya sehingga kita tergolong dalam kelompok al-a`idin wal faizin. Amin, ya rabbal alamin.